Di Balik Pembangunan Museum Pertunjukan Budaya, Pusat Kebudayaan Bali Untuk Siapa?

Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Hilir Tukad Unda diwacanakan sebagai wahana pemuliaan Kebudayaan Bali, konstruksi ini juga bermuara pada upaya menjadikan kebudayaan Bali sebagai objek berharga yang dapat dijual kepada turis asing melalui jalur pariwisata budaya. Namun ada yang keliru pada proyek PKB baru, untuk memenuhi kebutuhan urug sejumlah bukit dikeruk dan lahan produktif dibebaskan.
Jembatan merah yang melintang di atas hilir Tukad Unda berdiri di tengah tanah lapang yang baru saja berubah wajahnya, debu-debu halus berterbangan dihantam panas dan deru angin pesisir. Beton-beton tinggi di sempadan sungai juga telah berdiri kokoh, normalisasi Tukad Unda tersebut sekaligus menjadi penanda bermulanya proyek berskala besar akan dibangun di tanah bekas galian C tersebut.
Sesekali melintas petani di jalanan beton bekas lubang-lubang tambang yang merupakan jalur lahar dari muntahan Gunung Agung di tahun 1963. Pada kawasan itu akan dibangun fasilitas pariwisata budaya bercorak modern berupa Pusat Kebudayaan Bali yang direncanakan bakal menggantikan Pesta Kesenian Bali di Denpasar. Historis Klungkung sebagai pusat kerajaan pertama di Bali disebut menjadi salah satu pertimbangan kabupaten ini dipilih menjadi kawasan Pusat Kebudayaan Bali.

Mahakarya monumental yang dicanangkan dapat menjaga hidup adat istiadat dan kearifan lokal yang selama ini menjadi nafas masyarakat Bali itu dibangun untuk mewujudkan Kawasan Pengembangan Terpadu yang mengintegrasikan Upaya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali, melalui pengembangan kegiatan yang dapat memberikan manfaat edukasi, konservasi, rekreasi, ekonomi kreatif, yang ramah lingkungan berkelanjutan (Green Sustainable Development) dan berbasis IT (Smart Integrated Development).
Di sisi lain, menjadi pemandangan lumrah bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung menyaksikan kendaraaan proyek berlalu-lalang sejak awal tahun 2022. Truk-truk itu mengangkut muatan tanah untuk memenuhi kebutuhan uruk pematangan lahan PKB baru. Sebelumnya, tak ada yang mengira lahan yang tertidur di Klungkung tersebut nantinya akan masuk ke dalam program kawasan strategis Pemerintah Provinsi Bali, bukit-bukit yang semula hijau akan dikeruk atau bagi petani penggarap, tidak mengira mereka akan kehilangan lahan garapannya.
Mulanya, cita-cita besar untuk membawa Bali menjadi pusat kebudayaan dunia sedikit tidaknya lahir dari kentalnya tradisi manusia Bali yang dijiwai oleh spirit Agama Hindu dan keinginan untuk memberdayakan dan mempertahankannya dalam waktu yang lama. Begitu gegap gempitanya umat Hindu Bali menggelar ritual bahkan sejak dalam kandungan hingga berstana di rong telu (persemayaman jiwa yang telah bersih setelah kematian) membuat Bali kian unik dan memikat. Kesadaran akan besarnya potensi sumber daya budaya tersebut lantas mendorong upaya-upaya pembangunan fasilitas penunjang pariwisata budaya di pulau seribu pura.
Kebudayaan, Roh Kehidupan Masyarakat Bali
Pulau Bali dengan manusia dan kebudayaan adalah satu kesatuan utuh, spirit hinduisme yang menjiwai napas kehidupan masyarakatnya dilandasi oleh tiga kerangka dasar atau batang tubuh yaitu, tatwa atau filsafat, susila atau etika, dan upacara atau ritual. Berdasarkan kerangka inilah dalam perjalanannya muncul kebudayaan-kebudayaan lokal atau tradisi Suku Bali yang kental akan nuansa magis. Manusia Bali dalam fase kehidupannya, mulai dari fase dalam kandungan, lahir, tumbuh dan berkembang hingga kematian tidak pernah lepas dari ritual sebagai penghubung antara manusia dengan Tuhannya.
Ngurah Suryawan dalam tulisannya Saru Gremeng Bali tahun 2020 menyebut, suka duka hidup sehari-hari selalu dimaknai dengan pelaksanaan ritual dalam setiap babak kehidupan. Garis panjang ritual dalam kehidupan orang Bali inilah yang diandaikan sebagai jalan raya yang tidak putus-putus. Itulah yang disebut dengan “jalan raya agama”. Sehingga kebudayaan atau adat istiadat telah menjadi roh yang menghidupi masyarakat Bali selama ini.
Menurut Ngurah Suryawan, bagi masyarakat Bali, jalan keagamaan yang kolektif dipraktekkan melalui ritual. Jalan keagamaan ini menjadi medium bagi masyarakat Hindu di Bali untuk menjalin konektifitas dengan Tuhanya. Ritual dalam hal ini dimaknai utuh atau dihayati sebagai sebuah suluh kehidupan, sebab umat Hindu adalah umat yang religius. Dalam aktivitas kehidupan sehari-harinya masyarakat Hindu di Bali selalu menempatkan unsur kekuatan Tuhan sebagai muara konsekuensi tanggung jawab. Hal ini dibuktikan dengan rutinitas keagamaan melalui pelaksanaan upacara yadnya sebagai wujud pelaksanaan bhakti kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa.
Ragam kebudayaan atau tradisi yang diekspresikan melalui bebantentan (sesajen), arsitektur, hingga nyanyian-nyanyian suci memiliki makna mendalam serta merupakan bentuk praktik pemuliaan manusia Bali terhadap hutan, danau, laut, serta lingkungannya yang diekspresikan melalui serangkaian ritual, menjadikan ekspresi budaya tersebut sebagai sebuah magnet yang menggugah rasa penasaran para pelancong untuk datang ke pulau ini. Ajeknya tradisi itu pada akhirnya memberikan bonus berupa suburnya sektor pariwisata budaya di Bali.
Pada sektor turisme massal, budaya tak hanya menjadi bagian dari pola kehidupan masyarakat, tapi juga poros dari perekonomian Bali. Menguatkan citra tersebut dibentuk Peraturan Daerah mengenai Pariwisata Kebudayaan yang saat ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali. Bermula sejak pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan industri pariwisata melalui wacana Baliseering, yaitu upaya Belanda untuk kembali memulihkan citra Bali pasca kejahatan perang yang dilakukan Kolonial Belanda untuk menaklukan kerajaan-kerajaan di Bali (Sendra, 2016). Melalui agenda politik itu, Belanda mencitrakan Bali sebagai pulau surga terakhir untuk menarik minat kunjungan ke Bali. Dengan berbagai promosi wisata akhirnya berhasil mendorong kedatangan turis asing untuk menetap atau sekadar mengunjungi dan mengenal Bali.
Selain itu, momen terpenting pariwisata massal adalah pada tahun 1980-an saat diberlakukannya deregulasi kebijakan penerbangan langsung ke Bali. Arus global tersebut kemudian direspons dengan membuka Bali untuk penanaman modal berskala besar di sektor pariwisata pada akhir 1980 (Ngurah Suryawan, 2020). Dari masa ke masa potensi sumber daya budaya dan bentang alam yang memesona di Bali kemudian melanggengkan mobilisasi para turis untuk datang ke tanah para dewa apalagi sederet fasilitas turut dibangun untuk menopang suburnya sektor pariwisata. Sebuah penelitian beberapa tahun silam yang dilakukan oleh Michel Picard mengungkap kebutuhan untuk mempromosikan kebudayaan mendorong Bali untuk melindungi kebudayaan tersebut hingga produk pariwisata dijadikan sebagai sebuah identitas budaya demi menjaga hayatnya (Michel Picard, 2006). Kajian yang dilakukan oleh Michel Picard terasa dekat kala melihat bagaimana sektor pariwisata Bali memanfaatkan sumber daya budaya yang dibungkus dengan agenda pelestarian untuk menarik minat wisatawan.
Lebih lanjut, pariwisata kebudayaan terwujud salah satunya melalui Pesta Kesenian Bali di Art Center. Pesta ini digagas 45 tahun silam oleh Gubernur Bali, Ida Bagus Mantra. Dalam tulisan milik seorang antropolog asal Bali, I Ngurah Suryawan, menuliskan Pesta Kesenian Bali dibangun oleh Ida Bagus Mantra mulanya sebagai pondasi untuk menetralisir ketakutan manusia Bali pasca tragedi 1965 di Bali dengan menyalurkan naluri dan ekspresi masyarakat Bali kepada dua hal pokok yaitu keagamaan, dan kesenian (festival)-kebudayaan.
Seiring berjalannya waktu, Pesta Kesenian Bali menjadi bagian dari ajang festivalisasi rutin yang diselenggarakan 1 tahun sekali sekaligus simbolik Bali sebagai pulau yang kaya dengan sumber daya budaya. Selo Sumardjan, seorang ahli ilmu sosial, menilai gagasan mendirikan Pesta Kesenian Bali sebagai sebuah gagasan yang berpandangan luas dalam rangka menciptakan sarana modern di Bali yang dapat mengembangkan kepariwisataan Bali (Agastia, 2006). Lewat Pesta Kesenian Bali, berbagai kegiatan atraksi budaya dan pameran produk lokal menarik atensi berbagai lapisan masyarakat untuk berkunjung. Kini, sesaknya area Art Center yang hanya berkisar lima hektar juga padatnya Kota Denpasar, disinyalir mendorong wacana pembangunan wisata kebudayaan baru, yaitu Pusat Kebudayaan Bali dengan fasilitas premium dan skala tampung yang lebih besar.

Landskap- Pemandangan Pusat Kebudayaan Bali dari ketinggian Bukit Buluh
Antara Merawat Kebudayaan dan Menggenjot Industri Wisata
Wajah Bali perlahan mulai berganti rupa. Bentangan lahan hijau mulai jarang dikenali di wilayah kota, utamanya di daerah yang sudah dijamah industri wisata seperti Kuta. Pelan tapi pasti, daerah-daerah lain di Bali juga mulai menggenjot pembangunan untuk menopang pariwisata. Polarisasi pembangunan di Bali saat ini mengarah pada masifnya pembangunan infrastruktur untuk mendongkrak sektor wisata, seperti proyek Reklamasi Teluk Benoa dan pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi. Sepanjang tahun 2022, Badan Pusat Statistik mencatat terdapat 3.528 hunian akomodasi di Bali, 434 diantaranya merupakan hotel berbintang. Kondisi ini bukan saja mengubah bentang alam Bali, tetapi juga mendorong perubahan dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri jasa.
Tidak dapat dipungkiri, sektor pariwisata menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang mendominasi di Provinsi Bali bahkan pada skala nasional. Agus, salah seorang pemandu wisata yang sudah berkecimpung selama 22 tahun lebih di dunia pariwisata menuturkan bagaimana industri wisata memberikan penghidupan bagi dirinya dan keluarga. Pekerjaan ini dilakoninya selepas menamatkan diri di Sekolah Menengah Atas, ketika itu Agus melihat peluang yang besar di sektor pariwisata.
Dari keseharian Agus selama menjadi seorang tour guide kecenderungan wisatawan untuk berkunjung ke Bali adalah melihat realitas kehidupan sehari-hari masyarakat Bali yang identik dengan laku ritual, pemahaman teologis dan pemaknaan yang utuh terhadap menjaga harmonisasi antara manusia dan alam semesta. Agus mengingat kembali perjalanannya selama memandu para turis yang bertandang ke Bali, bentangan pantai Bali memang menjadi destinasi yang banyak diincar, namun lebih dari itu, Agus mengungkapkan sumber daya budaya yang menjiwai kehidupan masyarakat Balilah yang mendatangkan turis datang ke pulau seribu pura ini.
Sebagai salah satu kekayaan tak ternilai, upaya menjaga ketahanan budaya terus dilakukan di tengah era transformasi, sejumlah ahli sosial dan kebudayaan dalam buku yang bertajuk “Transformasi Kebudayaan Bali Memasuki Abad 21” mengungkap profil kebudayaan Bali pasca masa agraris layaknya bermuka ganda, yaitu tradisional dan modern. Terdapat dua kubu dalam menanggapi keberadaan, dinamika dan perubahan kebudayaan Bali. Kelompok pertama berpandangan bahwasannya dinamika kebudayaan Bali tradisional menuju Kebudayaan Bali modern atau pasca-agraris menuruti konsep continuity in changes. Kelompok ini berpandangan kebudayaan tradisional di tengah-tengah arus modernisasi dan globalisasi hanya akan merubah sisi permukaan dari kebudayaan itu sendiri. Lain lagi kubu kedua yang menilai dinamika kebudayaan Bali tradisional menuju Bali modern mengandung ancaman yang serius, krisis dan ketidakberdayaan tradisional tengah mengalami distorsi, diskontinu dan disintegrasi (Wayan Geriya,2008).
Sikap yang diambil Pemerintah Provinsi Bali terhadap masuknya modernisasi dalam aspek kebudayaan dapat dilihat dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1991 pasal 3 yang menjelaskan bahwasanya tujuan penyelenggaraan pariwisata budaya bertujuan untuk memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata, mempertahankan norma-norma dan nilai-nilai kebudayaan agama dan kehidupan alam Bali yang berwawasan lingkungan hidup, mencegah dan meniadakan pengaruh-pengaruh negatif yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan kepariwisataan.
Upaya pelestarian budaya kemudian muncul dalam deretan jargon yang digaungkan , misalnya Ajeg Bali hingga Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Jargon- jargon tersebut mengakar sebagai landasan untuk membangun dan menyikapi persoalan budaya di tengah masyarakat. Pertama kali Ajeg Bali dibicarakan pasca terjadinya Bom Bali di tahun 2002. Ketika itu, dibentuknya salah satu group media di Bali begitu aktif menyuarakan wacana Ajeg Bali, kendati jargon Ajeg Bali sendiri belum menemukan makna definitifnya. Penelitian oleh Carmencita Palermo dalam tajuk “Multiple Meanings, Diverse Agenda” mencatat sejumlah wawancara dengan berbagai tokoh seniman, jurnalis, dalang dan antropolog yang mendefinisikan mengenai Ajeg Bali dalam perspektif beragam (Carmencita, 2005). Namun demikian, dengan hingar-bingarnya Ajeg Bali sempat menjadi jargon yang sukses untuk mengorganisir berbagai kepentingan dalam bingkai “pelestarian budaya”
Selanjutnya, untuk mengantisipasi dampak negatif masuknya modernisasi juga nampak dengan lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali. Dalam bagian umum peraturan tersebut dijelaskan pembentukan peraturan ini tidak dapat dilepaskan dari dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh pariwisata. Aspek fundamental Bali yang meliputi Alam Bali, Krama Bali, dan Kebudayaan Bali cenderung telah berubah secara masif dan sistemik. Lingkungan Alam Bali, Krama Bali, dan Kebudayaan Bali secara keseluruhan telah terjadi penurunan atau degradasi, baik secara kualitas maupun kuantitas.
Maka, dalam rangka menjaga kelestarian tersebut sejumlah gebrakan yang disebut dapat menjaga hidup kebudayaan Bali kembali digalakkan Gubernur Wayan Koster bersama wakilnya, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati. Pada awal kepemimpinannya, dimulai dengan mengedepankan identitas Bali lewat kewajiban penggunaan pakaian adat setiap hari Kamis, terbitlah Pergub No. 79 Tahun 2018 tentang Penggunaan Busana Adat Bali. Setelahnya terbit Pergub No. 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Melengkapi pergub tersebut, keluarlah dua Perda (Peraturan Daerah) yaitu Perda No. 1 Tahun 2018 Tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali. Selanjutnya terbit pula Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat yang Paling menyita perhatian publik Bali. (Ngurah Suryawan, 2020)
Menyusul serangkaian kebijakan yang dibingkai agenda pelestarian kebudayaan Bali, Wayan Koster hadir dengan ide besar berupa pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di pesisir Kabupaten Klungkung. Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) ini dilaksanakan dalam rangka perlindungan, penguatan, dan pemajuan kebudayaan Bali didukung penetapan kawasan tersebut sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam Perda No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas perda 16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali Tahun 2009-2029. Pembangunan ini juga dicanangkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan wilayah melalui pengembangan pusat-pusat kegiatan pembangkit perekonomian melalui pariwisata budaya.

Terminologi “pariwisata budaya” tersebut menjadi kata sakti yang menyatakan bahwa (sepatutnya) pariwisata bersifat budaya untuk diterima orang Bali. Dengan demikian, harusnya juga kebudayaan Bali diupayakan dapat ditawarkan di pasaran sebagai produk pariwisata. (Ngurah Suryawan, 2020:6). Salah satu bentuk pembangunan pariwisata budaya adalah PKB baru yang merupakan bagian Visi dan Misi Pembangunan Bali 2018-2023, yaitu Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang artinya menjaga keharmonisan alam Bali beserta dengan isinya.
Jargon itu santer didengungkan melalui berbagai sosialisasi sebagai jalan menuju tatanan Bali Era Baru dan juga melalui Perda Bali tentang Pariwisata Budaya. Dalam sebuah wawancara di kanal youtube TvOne pada Minggu, (29/01), Wayan Koster menjelaskan Bali Era Baru merupakan era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru, suatu tatanan yang berisi spirit untuk kebangkitan kekuatan dengan energi baru Bali, sesuai dengan kekuatan alam, manusia dan kebudayaan Bali.
Melalui visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, spirit untuk mewujudkan Bali sebagai pusat kebudayaan nasional bahkan dunia terus digaungkan. Lebih lanjut, megaproyek yang menelan dana triliunan rupiah tersebut akan menjadi etalase bagi kebudayaan Bali. Di dalamnya terdapat 3 zona pembangunan yang dicanangkan yakni zona inti, zona penyangga, dan zona penunjang. Zona inti akan dikhususkan untuk pemuliaan dan penguatan Kebudayaan Bali. “Kita ingin membuat showcase kepada dunia, pada semua dan kepada diri kita sendiri bahwa budaya kita begitu adiluhung, kita akan buatkan itu semua yang namanya Pusat Kebudayaan Bali, sebuah Kawasan Terpadu yang intinya nanti ada namanya zona inti. Itulah wahana pemuliaan Kebudayaan Bali, ” terang Arca Eriawan, kelompok ahli bidang infrastruktur Pemerintah Provinsi Bali (14/17).

Rancangan PKB yang direncanakan rampung pada tahun 2024 itu, disebut bakal menggantikan Art Center di Denpasar saat ini, Pusat Kebudayaan Bali diperkirakan akan berkapasitas hingga puluhan ribuan orang. Berbeda dengan Pesta Kesenian Bali atau PKB yang ada di Denpasar, Pusat Kebudayaan Bali yang sedang dibangun di Kabupaten Klungkung ini tidak akan berdiri sebatas ajang festivalisasi atau area pertunjukan, rancangan PKB baru di Klungkung lebih mirip resor wisata yang disebut-sebut dapat memperluas lapangan pekerjaan, menggenjot sektor pariwisata di Bali Timur serta melindungi Kebudayaan yang selama ini telah menjadi roh masyarakat Bali, terutama Klungkung sebagai Pusat Kerajaan Bali yang tentunya akan secara signifikan berpotensi menggenjot pertumbuhan ekonomi Bali dan nasional. “Enggak hanya Pusat Kebudayaan Bali, namanya aja Pusat Kebudayaan Bali, tapi sebenarnya itu adalah kawasan terpadu ekonomi yang kuat Pusat Kebudayaan Bali ini. Itu yang enggak dimiliki oleh bangsa manapun di dunia,” terang Arca Eriawan.
Arah pembangunannya tidak hanya berfokus pada aspek penguatan kebudayaan melainkan juga berorientasi pada penguatan pariwisata menjadi wacana yang tidak dapat dilepaskan dari Pusat Kebudayaan Bali. Sehingga dua kawasan terpadu lainnya disiapkan untuk mendobrak kunjungan wisatawan. Dua kawasan itu ialah, zona penunjang untuk membangun berbagai fasilitas komersil seperti perhotelan, apartemen, mall, rumah sakit serta zona penyangga seperti ruang terbuka hijau dan pelabuhan. Dengan kawasan terpadu ini, Bali diharapkan bisa menjadi pintu gerbang marketing industri kreatif di Nusantara. “Dah ada berbagai panggung seni budaya, tapi budaya juga butuh biaya. Budaya bukan benda mati untuk dinikmati. Orang berbudaya butuh biaya kita melaksanakan adat ritual tersebut butuh biaya, sehingga dia harus hidup kawasan itu, harus ada UMKM-nya, harus ada jual belinya itu. Kemudian, dia juga harus menjadi karena kawasan terpadu ya harus ada ibaratnya pelaba (untung – red) ya ada yang cari duitnya ininya udah dapat juga nanti tiket masuk orang.” jelas Arca Eriawan.

Ia menambahkan Pusat Kebudayaan di Timur Bali ini nantinya akan mendongkrak perekonomian seperti di Kota Denpasar, “karena kita kalau bisa pelihara kebudayaan, pariwisata akan tumbuh. Begitu pariwisata tumbuh keliatan sekali Denpasar sekitarnya lebih maju dari sekitarnya.”
Bumi, Manusia dan Investasi Pembangunan
Musim panen bulan Juli membuat Pastya dan Darti lebih sibuk dari biasanya, meski kini sawah yang mereka garap tak seluas dulu. Sebelumnya tak ada yang mengira pengukuran lahan di bekas Galian C akan menyeret lahan penghidupan petani sekitar. Bermula sejak awal tahun 2020 sekumpulan alat berat, truk pengangkut material dan tukang-tukang hilir mudik di sekitar kawasan bekas Galian C yang berhenti beroperasi pada tahun 2002. Untuk mewujudkan megaproyek Pusat Kebudayaan Bali tersebut pematangan dilakukan pada lahan seluas 334 hektar, termasuk pada sejumlah lahan produktif miliki petani setempat.
Pembangunan Kawasan direncanakan di Kabupaten Klungkung, dengan pertimbangan bahwa pusat Kerajaan Bali dan pusat perkembangan kebesaran kebudayaan Bali masa lalu berada di Kabupaten ini. Pembangunan berskala besar tersebut juga diklaim sebagai salah satu bentuk upaya perlindungan, penguatan, dan pemajuan kebudayaan Bali. Namun, dalam usaha-usaha untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan industri sering kali meminta “pengorbanan” di bidang-bidang lain, salah satunya kepedulian terhadap lingkungan hidup, hal ini seringkali kontradiktif dengan wacana konservasi atau pembangunan berwawasan lingkungan yang dimuat dalam setiap agenda-agenda pembangunan. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan urug sebagai pondasi PKB Baru sejumlah tanah-tanah dari bukit yang ada di sekitar proyek dikeruk.
Megaproyek PKB juga berujung pada pembebasan lahan milik sejumlah petani yang berada di sekitar kawasan PKB, sejumlah lahan produktif yang menopang hidup para petani pada akhirnya turut terenggut, meski pada perencanaan awal pembangunan PKB baru ini disebut tidak akan menyasar lahan produktif. Kenyataan tersebut membuat Nengah Sukarta kecewa. Sebagai Kelian Subak Sampalan Delod Margi, dirinya paham betul bahwa lahan produktif itu sangat berarti bagi sesama petani. Sebab di Kabupaten Klungkung Pertanian merupakan salah satu profesi yang mendominasi. Sepanjang tahun 2017, tercatat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung 2019, jumlah petani di Kabupaten Klungkung yaitu 33.680 orang. Kemudian di tahun 2021 berdasarkan data yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, jumlah petani dan pekebun yaitu 31.575, sedangkan buruh tani dan perkebunan yaitu 2.334.

Mulanya Nengah Sukarta menyambut baik pembangunan di lahan bekas galian C tersebut setelah memastikan bahwa tidak akan ada sedikitpun lahan produktif yang tersentuh pembangunan, “Kemarin kami dari perencanaan, mandat perencanaan Pak Gubernur karena kami dilibatkan dalam hal niki dia bilang, oh itu tidak kena, kami merasa lega sebagai Kelian Subak. Akhirnya kami sampaikan kepada petani-petani, baik pemilik atau penggarap bahwa pembangunan ini fokus di bagian galian C. Tau-tau merambat-merambat sampai kena di tanah produktif. Kami sangat kecewa, apa daya kami sebagai Kelian Subak kan endak bisa berbuat apa, karena ini kan program pemerintah ya bagaimana kita terima aja.”
Kekecewaan Nengah Sukarta bukan tak beralasan, ia ingat betul dulu para petani diarahkan untuk mengedepankan Perda dan membuat awig-awig subak agar tidak ada lahan hijau yang dialihfungsikan. “Kadang-kadang kekecewaan pemilik tanah juga apalagi dulunya kita disuruh menyiapkan perda atau istilahnya awig subak biar lahan itu tidak dialihfungsikan,” tandasnya dengan wajah yang sarat akan kekecewaan pada inkonsistensi pemerintah terhadap upaya pelestarian subak.
Sedangkan, bagi petani penggarap seperti Ketut Pastya, ia harus kehilangan satu hektar lahan garapan yang semula dua hektar. Namun dirinya tidak bisa berbuat apa-apa, karena penjualan lahan menjadi urusan si empunya, sedangkan sebagai seorang petani penggarap ia hanya bisa berpasrah, “saya jadi petani kan nak buruh. Tidak ada bos, buruhnya berhenti.” Rekan Pastya sesama petani penggarap yang telah kehabisan lahan garapan terpaksa harus mencari pekerjaan lain untuk menyambung hidup. Sebab urusan dapur harus tetap berjalan dan ada yang harus diberi makan.
Nengah Sukarta bercerita sampai saat ini lahan produktif yang dialihfungsikan untuk pembangunan Pusat Kebudayaan Bali sudah mencapai 15 hektar dari luasan lahan produktif 49,98 hektar yang ada.”Karena kami sebelum kena PKB ini wilayah subak kami hanya 49,98 hektar itu yg produktif. Sekarang karena sudah kena 15 hektaran itu, belum lagi karena kami saat tanggal 14 kami ada Pemnas di Sumatera yang dikirim oleh provinsi (didelegasikan oleh Provinsi -red), kita dapat surat itu untuk ada rapat perluasan kawasan, tapi kami belum bisa datang, pas ada di Sumatera itu. Mungkin kedepannya ada lagi rapatnya, kami bisa dilibatkan, nanti di sana kita bisa mempertahankan lagi supaya tidak meluas.”

Alih fungsi lahan produktif untuk pembangunan di Bali memang bukan kondisi baru lagi. Setiap tahunnya di Bali tercatat 600 hingga 1000 hektar tanah beralih fungsi menjadi akomodasi pariwisata atau industri lainnya (Bisnis.com). Konversi lahan pertanian mengakibatkan ruang gerak petani semakin terbatas, hal ini turut memunculkan kekhawatiran-kekhawatiran akan taraf hidup yang harus dipenuhi di kemudian hari.
Bali kini telah jauh berubah, Ngurah Suryawan (2020) menyebut sektor pertanian pelan tapi pasti mulai ditinggalkan. Kebudayaan dan praktik beragama yang semula berpusar pada pertanian perlahan bergeser. Sudah lumrah terjadi lahan-lahan pertanian berubah menjadi perumahan bahkan deretan ruko. Pura-pura subak semakin terhimpit meski para penyungsung-nya masih setia di situasi serba sulit. Jauh sebelumnya Ngurah Bagus (2011) telah mencatat bahwa transformasi dari pertanian ke pariwisata menyebabkan perubahan drastis secara fisik, lahan pertanian berubah menjadi resort atau hotel, dan investor masuk menyulap bentangan sawah yang menjadi lumbung pangan dan sumber penghidupan petani.
Sementara itu, Para petani seperti Nengah Sukarta, Pastya dan Darti hanya khawatir apa yang menjadi ladang penghidupan mereka sekaligus sumber ketahanan pangan semakin terhimpit “Karena ketahanan pangan itu otomatiskan ada di pertanian kalau tanpa itu mana kita bisa kan? Nah pakan kita kan memang dari sana tapi kita semua kan tidak bisa ngomong apa, ya kita menyerah saja karena ini program pemerintah,” lontar Nengah Sukarta dengan nada pasrah.
Di sisi lain, pembangunan Pusat Kebudayan Bali yang diwacanakan menjadi pusat perekonomian baru sekaligus motor penggerak industri di Bali Timur ini dijelaskan akan mengadopsi nilai filosofi Sad Kertih (enam pemuliaan yang dilakukan untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian antar alam semesta dan kebudayaan Bali dengan memberdayakan nilai-nilai kehidupan lokal -red) sebagai landasan pokok dalam pembangunan Pusat Kebudayaan Bali. “Pertama itu atma, kita bagian dari alam semesta, kita harus harmoni dengan alam semesta, supaya harmoni kita harus punya jana, pikiran yang bersih untuk mengelola kekayaan alam. Caranya gimana? keluarlah Wana Kerthi, kita harus hidup dengan tanaman hutan, konsepnya kuat sekali. Danu, sumber air, kita butuh air. Segara masuk itu pelebur, perputaran iklim untuk kehidupan, baru masuk ke jagat, itu lingkungan, filosofinya kuat sekali dan seluruh itu konek dengan aktivitas ritual, ” terang Arca Eriawan.
Berbanding terbalik dengan visi yang digaungkan, proyek Pusat Kesenian Bali dalam pembangunannya tidak berjalan lurus dengan esensi ramah lingkungan berkelanjutan. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali dengan tegas menyebutkan ramah lingkungan sebagai salah satu parameter yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pariwisata budaya Bali yang berlandaskan filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari kearifan lokal Sad Kerthi.
Nyatanya, dalam memenuhi kebutuhan uruk pembangunan PKB sejumlah perbukitan di wilayah sekitar dikeruk. Salah satunya di Desa Pikat, Kecamatan Dawan, sejumlah truk-truk pengangkut tanah berlalu-lalang membawa material untuk pematangan wilayah PKB. Pada akhirnya kendaran proyek tersebut meninggalkan jejak kerusakan pada sepanjang jalan yang dilaluinya. Bongkahan bukit yang dikeruk, debu-debu halus yang dihempas angin dan lubang-lubang jalan menjadi pemandangan lumrah bagi warga sekitar. “Nggih debunya jek aduh kanti subak tanah gen nika (debu dari pengerukan menyebabkan subak di sekitar areal bukit yang dikeruk dipenuhi debuan tanah -red), yen iraga ngelarang gak bisa nika istilahnya karena hak pribadi (kalau kami melarang juga tidak bisa karena itu adalah lahan milik pribadi – red), perbekel pun engga bisa, karena dia (pemilik tanah -red) minta surat keterangan dari desa juga mungkin napi ketenya dari desa, ten uning tiang.” tukas Wayan Winata, Kelian Subak Telaga yang tinggal di dekat areal pengerukan.
Tanah dari bukit yang terkeruk dibeli pengembang dari warga desa sekitar. Penjualan lahan perbukitan ini diakui oleh salah seorang warga Desa Pikat karena faktor lahan yang nonproduktif “Ini cuma kebetulan aja, ada banyak orang-orang disini (Desa Pikat -red) yang menjual untuk pengerukan. Kebetulan juga ada lahan disana, dianjurin lah mau jual ininya (lahan di bukit -red), dikeruk. Karena lahan itu tidak berfungsi, terpaksa saya jual. Makanya dibelilah lahan itu.”
Selain itu, menjadi mudah baginya ketika lahan perbukitan tersebut dikeruk sehingga ia tak perlu mengeluarkan uang untuk meratakan lahan, “Ya disamping itu kita kan mengolah lahan jadinya. Kalau berbukit begini, selain tidak produktif kalau didatari kan istilahnya daya jualnya lebih bagus lagi gitu, soalnya kalau itu kalau kita pribadi mau datarin itu bukan puluhan juta kita habisin, ratusan juta untuk datarin aja. Soalnya 1 alat per hari bisa 6 juta, 1 alat itu. Untuk dalam artian kerja 8 jam lah itu 6 jutaan biayanya.”
Sementara itu, terkait aktivitas pengerukan sejumlah bukit di Kecamatan Dawan, dalih pengerekuan yang dilakukan pada wilayah terkategorisasi Galian C tersebut dipatahkan. Faktanya di Kecamatan Dawan tidak terdapat wilayah Galian C selain dari lokasi Galian C di kawasan PKB baru yang sudah tidak beroperasi sejak tahun 2002. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung, I Gusti Ngurah Yudantara, “PKB memang dari kalau kita gini kan memang dikasih manfaat sama PKB. Nah dibalik manfaat itu kita babak belur karena tanah urug yang dipake ngurug PKB itu diambil dari bukit-bukit yang ada di Kecamatan Dawan, dimana kita di Kabupaten Klungkung di Kecamatan Dawan dari segi tata ruang tidak ada wilayah Galian C. Terakhir itu wilayah Galian C kan yang di PKB itu udah ditutup, kita tidak punya wilayah galian C, itu yang pertama. Yang kedua kita sebagai orang lingkungan kalau kita biarkan salah, penggalian bukitnya itu. Kalau kita tutup juga tidak punya kewenangan karena kita tidak mengeluarkan izin, izinnya tetap di provinsi.”
Di lain sisi, menurut pengakuan warga Desa Pikat tersebut bahwa memang perizinan pertambangan tidak dikantonginya. “Dia istilahnya minta izin dadakan istilahnya karena ada PKB-nya, diprioritaskan istilahnya. Kalau memang izin gini kan engga boleh, kalau di Bali cuman berapa izinnya itu, 4 (daerah -red) kalau engga salah itu ada izin penambang, di Karangasem sama di Singaraja. Mungkin kalau engga ada PKB engga ada izin untuk penambangnya. Ini karena ada PKB-nya kita sama-sama menyukseskan istilahnya, kerjasama dalam hal ini, itu bisa diolah, dikeluarin istilahnya, kalau engga ada PKB-nya kalau pribadi itu mungkin engga dikasi itu, harus ada istilahnya izin penambangan.”

Menanggapi masalah perizinan pengerukan bukit, pihak Dinas Tata Ruang tidak menampik adanya pengerukan-pengerukan liar tak berizin. “Jadi gini, dalam proses membangun itu kan ada dokumen-dokumen ya, kan tidak dinas tata ruangnya yang membangun, dia akan bekerjasama dengan pihak ketiga, perencana, kontraktor, tapi kerangka acuannya ada disini, ngapain, ngapain. Soalnya ada persyaratannya, pada saat poin ini udah, kemudian kan pematangan lahannya kan diurug kan, butuh material. Mereka pihak ketiga, nah disana pihak ketiga, material itu harus diambil dari sumber yang legal. Legal artinya sudah punya izin. Yang punya material itu sudah punya izin. Kita sampai disitu. Memang saat pelaksanaannya memang agak liar. Ternyata masyarakat melihat itu sebuah peluang, sebuah peluang. Dia nawarin oh lebih murah di sini, lebih murah di sini. Kita stop di awal, nanti hasil kesepakatan, yang penting dia punya dokumen pendukung lingkungannya itu. Yang penting kita di posisi kita itu kita terima legal.”
Perihal tidak adanya izin pengerukan, I Gusti Ngurah Yudantara menyampaikan harus adanya dokumen lingkungan untuk menjamin kondisi lingkungan tetap terjaga, “Kita arahkan dia untuk ke arah yang lebih mendekati hukum para pengusaha disana, minimal lah mengurus dokumen lingkungan, artinya kan dari dokumen lingkungan itu kita bisa rem dampak yang terjadi.”
Hal ini tentu akan berkaitan dengan bagaimana aspek Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang ada. Apabila dilihat dari kacamata Analisis Dampak Lingkungan, pengambilan bahan uruk dengan mengeruk bukit secara otomatis mengubah bentuk dan bentang alam. Terlebih pengerukan yang tidak dilakukan dengan sistem terasering menimbulkan ancaman besar bagi warga yang tinggal di sekitaran bukit, tak terkecuali Wayan Winata, Kelian Subak Telaga. Tanah longsor menjadi suatu bencana alam impak pengerukan bukit “iya nika kan ada Pura Dalem, sebelah utara Pura Dalem nika dah longsor.” tutur Wayan Winata.
Ancaman tanah longsor lainnya, tepatnya di titik pengerukan di Pura Daerah Punduk Dawa Pesinggahan. I Gusti Ngurah Yudantara menegaskan jika dari pihak masyarakat sekitar tidak mempermasalahkan aktivitas pengerukan tetapi menyayangkan lalu-lalang kendaraan yang bertonase berat yang merusak jalan. “Kalo masyarakat sih tidak mempermasalahkan, karena kan bukit-bukit itu tanah kepemilikan, yang menjadi masalah dari masyarakat itu adalah jalan, karena jalan yang di kecamatan Dawan itukan bukan jalan untuk kendaraan berat, sekarang truk-truk pengangkut galian itu kan hancurlah jalan itu, itu yang dipermasalahkan oleh masyarakat”.
Bukit yang tempo hari penuh pepohonan hijau mulai menyusut dan menyisakan sisa bukit dengan lekuk asimetris tanah batuan. Hilangnya pepohonan diakui Wayan Winata meningkatkan teriknya sinar matahari, “Kalau alam mungkin panas, karena kan sekitar situ biasa rimbun dia, sebelah subak itu kan dulunya hutan itu, semakin ini udah keliatan batu-batu aja gitu,” tukas Wayan Wirawan.
Tanpa sadar, dengan pembangunan Pusat Kebudayaan Bali sebagai Kawasan Pengembangan Terpadu yang dapat memberikan manfaat Edukasi, Konservasi, Rekreasi, Ekonomi Kreatif, yang Ramah Lingkungan Berkelanjutan saat ini pada realisasinya telah memberikan realitas bagaimana eksploitasi sumber daya budaya dan alam dalam bungkus pelestarian yang dikemas dalam konsep pariwisata budaya. Linier dengan pernyataan David Harvey (1993) bahwa kebijakan ekowisata dan konservasi yang dianggap pro-lingkungan tidaklah pernah netral. Desain ekowisata atau desa wisata rentan terperangkap green grabbing, yaitu praktik-praktik perampasan tanah atau eksploitasi sumber daya alam dengan menggunakan tanah atau eksploitasi sumber daya alam dengan menggunakan isu dan legitimasi konservasi dan lingkungan. Ujungnya adalah kegagalan menyelamatkan alam dan juga krisis bagi manusia yang menjadikan alam sebagai ruang hidup mereka (Ngurah Suryawan, 2020).
Bagi Siapa Saja yang Menaruh Asa pada PKB
Di tengah hingar-bingar pembangunan Pusat Kebudayaan Bali dan sederet fasilitas premiumnya, menyesak sedikit asa bagi mereka yang berada di akar rumput, khususnya masyarakat Kabupaten Klungkung sebagai tuan rumah dari megaproyek ini. Buaian janji untuk mempekerjakan mereka yang terdampak pembangunan begitu dinanti.
Masih lekat dalam memori Nengah Sukarta komitmen Gubernur Bali untuk memberi lapangan kerja di Pusat Kebudayaan Bali bagi lima desa prioritas yaitu Gunaksa, Sampalan Kelod, Jumpai, Tangkas dan Gelgel yang paling terdampak pembangunan Pusat Kebudayaan Bali. “Mudah-mudahan dengan program ini kami harapkan nanti kedepannya apa janji-janji Pak Gubernur dulu baik lapangan pekerjaan, kategori orang-orang masih tamat SMA akan dibiayai untuk sekolah gratis, akan diterima di lapangan pekerjaan yang akan dibuka di PKB ini, mudah- mudahan itu kan janjinya pak gubernur yang pertama. Kedua, UMKM yang digadang-gadang untuk mengganti mata pencaharian yang punya punya-punya tanah itu yang menjadi lapangan untuk PKB nya ini mudah mudahan itu juga ditepati janji-janjinya karena juga ia (Pak Gubernur -red) menyampaikan begitu kemarin,” tandasnya sembari menatap langit sore menuju temaram di depan gapura Pusat Kebudayaan Bali.
Sedangkan bagi petani penggarap seperti Pastya tak terlalu yakin kalau-kalau di usianya yang sudah senja tenaganya dibutuhkan. Pastya dan istrinya, Ketut Darti, hanya bisa berharap Pusat Kebudayaan Bali nantinya akan benar-benar memberikan pekerjaan bagi anak-cucunya kelak. Harapan masyarakat tidak muluk-muluk, meski menjadi pekerja di tanah sendiri, syukur sudah dihaturkan setinggi-tingginya.
Begitu pula pelakon budaya yang menaruh asa untuk diikutsertakan dalam kegiatan Pusat Kebudayaan Bali, Putu Ariyasa, salah satunya. Sebagai kelian Sekaa Gong Suarga Suara yang kini sedang dihadapkan dilematika penerus kesenian Gong Mandolin di desanya, Sulang. Di usianya yang menginjak 60 tahun, besar harapannya Pusat Kebudayaan Bali nanti akan mendorong minat generasi muda untuk mengenal kesenian musik Mandolin, “nah mudah-mudahan nanti setelah dibangun PKB yang di Gunaksa itu ya harapan saya supaya diperhatikan apapun yang ada. Potensi seni yang ada di Klungkung, di Bali itu kalau bisa all out dimunculkan ditampilkan. Nika harapan tiang. Dengan adanya itu kan tiang bisa semangat, generasi yang hobi , yang senang jadi dia ada rasa ingin , tertarik untuk belajar, pentas dan mungkin ada imbalannya.”

Kepasrahan tergambar jelas dari wajah Ketut Darti, bertani di usia senja serta tidak memiliki keterampilan selain menggarap. Kepasrahan yang muncul menjadi gambaran bagaimana ketidakpastian selalu dibebankan pada masyarakat.

Di tengah gersang pembangunan Pusat Kebudayaan Bali, harapan itu terus mengalir. Kendati belum nampak seperti apa pastinya, masyarakat selalu memiliki harapan, seperti halnya Ketut Darti “Ndak tau jalannya kedepan. Jalannya masih panjang, Ndak tau besok bagaimana lagi, dua hari lagi bagaimana, ndak tau lah. Orang besok kalau ini sudah jadi kota kan lain jalannya. Sekarang petani kan lain jalannya. Ndak tau lah gimana kerja besok-besok. Kalo ada pekerjaan yang lebih baik, lebih baik kerja disana.”
Daftar Pustaka
Ari Dwipayana, AAGN, dkk, 2004, Bali Menuju Jagadhita Aneka Perspektif. Denpasar : Pustaka Bali Post
Picard, Michel,2006. Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata, Jakarta : KPG
Geriya, I Wayan, 2008, Transformasi Kebudayaan Bali Memasuki Abad XXI. Surabaya : Paramita
Made Sendra, 2016, Paradigma Kepariwisataan Bali Tahun 1930-an: Studi Genealogi Kepariwisataan Budaya dalam Jurnal Kajian Bali Volume 6 , Nomor 2.
Suryawan,Ngurah, 2020. Saru Gremeng Bali, Denpasar : Pustaka Larasan.
Undang-Undang No.10 Tahun 2020 tentang Kepariwisataan
Perda (Peraturan Daerah) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali.
Perda (Peraturan Daerah) Nomor 3 Tahun 1991 Tentang Pariwisata Budaya.
Saputra, Harian Noris. “Alih Fungsi Lahan Jadi Tantangan Bali Jaga Daya Tahan Pangan” Bisnis.com. diakses pada sabtu 29 Agustus 2023. https://bali.bisnis.com/read/20220622/537/1546781/alih-fungsi-lahan-jadi-tantangan-bali-jaga-daya-tahan-pangan.
Penulis : Cintya, Wida, Cynthia
Penyunting : Cintya

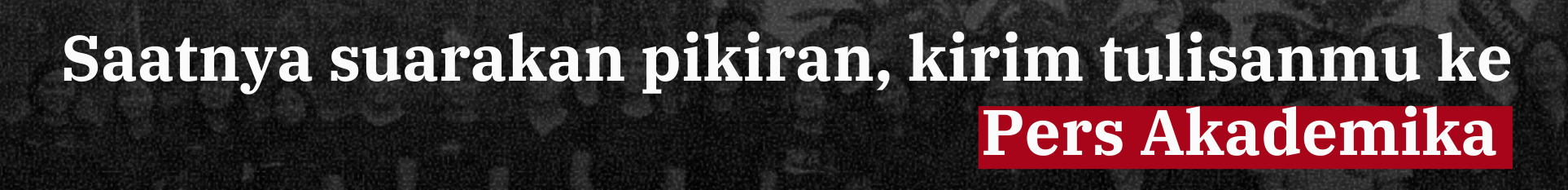






Hola! I’ve been reading your blog for some time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Atascocita Texas! Just wanted to tell you keep up the excellent job!
Great blog post. What I would like to add is that laptop or computer memory needs to be purchased should your computer still cannot cope with anything you do with it. One can deploy two good old ram boards of 1GB each, in particular, but not one of 1GB and one with 2GB. One should look for the maker’s documentation for own PC to ensure what type of memory is necessary.
Heya just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same outcome.
Thank you for sharing this article with me. It helped me a lot and I love it. http://www.hairstylesvip.com
The articles you write help me a lot and I like the topic http://www.hairstylesvip.com