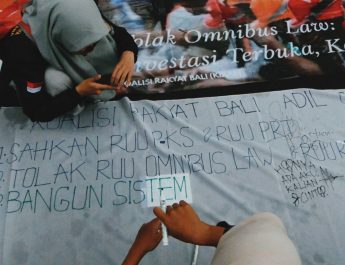*Seluruh isi tulisan ini telah diterbitkan atas izin penyintas*
Kasus kekerasan seksual kembali terungkap di Universitas Udayana, Bali. Tidak sedikit pelaporan jumlah kasus, namun langkah konkret Unud dalam memberi jaminan perlindungan dan ruang aman bagi penyintas masih kelabu. Inilah yang membuat Binar tidak melapor dan pesimis mendapat keadilan.
Nada suaranya mendadak berat pada sore itu (4/1/2020). Mata Binar (bukan nama yang sebenarnya -red) sembab, kemudian menghela napas panjang.Pikirannya memutar kembali insiden kekerasan seksual yang menimpa Binar saat akhir tahun 2019. Kejadian itu masih di dalam area Kampus Universitas Udayana (Unud). Binar saat itu hanya berjalan seperti biasanya setelah kegiatan kampus yang ia laksanakan. Ia mendeskripsikan baju yang dikenakannya: baju kemeja batik berlengan panjang dan rok di bawah lutut. Seorang dosen tiba-tiba saja memanggil Binar. Sontak, ia menyahut panggilan itu. “Ya dia kan dosen, dengan siapapun saya di kampus pasti saya menyapa balik,” tutur Binar.
Tidak diduga, dosen tersebut mendadak merangkulnya dari belakang. Segera Binar menangkisnya. Tangan dosen tersebut pun terlepas. “Saya pikir sudah tidak ada pergerakan lagi,” lanjutnya. Sebaliknya, dosen tersebut menarik leher Binar dan mendekatkan kepalanya kepada kepala Binar. Binar hendak dicium. Ia terlampau kaget, tak kuasa bergerak (freezing), tiada tenaga untuk melawan. “Akhirnya saya menggunakan siku kanan saya pukul ke belakang dan saya berjalan cepat. Kejadiannya berjalan cepat dan benar-benar cepat sekali,” katanya seraya mengerutkan dahi. Ia sangat tertegun kala dirinya menjadi korban dari dosen yang tertuduh itu. Sebab, beberapa kali ia pernah bertemu di kampus dan bahkan diajar oleh dosen tersebut. “Tidak pernah terlintas orang ini akan berlaku seperti itu kepada saya,” ujar Binar. Ia terburu-buru melangkah menjauh dengan perasaan shock dan takut, lalu hanya dapat menangis.
Pasca kejadian, Binar tetap harus bertemu dengan sang dosen lantaran ia masih mengambil mata kuliah yang diampu dosen itu. Ketika Binar masuk kelas dan mengetahui bahwa dosen tersebut akan mengajar hingga selesai SKS, ia memutuskan untuk tidak pernah masuk ke kelas itu lagi. “Karena saya merasa jijik, takut, dan saya tidak mau bertemu dengan orang ini lagi,” tegasnya. Hal ini pun berpengaruh terhadap urusan akademiknya jika mengharuskan untuk meminta tanda tangan kepada dosen yang ternyata merupakan pembimbing akademiknya sendiri. Untung, pihak staf fakultas mengerti posisi Binar. Sehingga, tidak dipermasalahkan jika berkas-berkasnya tidak terdapat tanda tangan dosen pembimbing akademik.
Viktimisasi Berganda Penyintas: Mendapat Stigma dan Diragukan
Masih di hari yang sama, Binar bertemu dengan teman terdekatnya. Ia memutuskan untuk menceritakan kejadian yang baru saja menimpanya di kampus. “Jawaban yang mereka berikan membuat saya semakin down. Karena mereka mengatakan, ah palingan gara-gara kamu itu, makanya dia kayak gini-kayak gitu,” ungkap Binar. Binar hening seketika. Ia mengungkapkan bahwa dirinya menjadi merasa kian direndahkan dan disudutkan. Binar kehilangan kepercayaan pada orang-orang terdekatnya.
Stigma dan keraguan teman terdekatnya itu membuat Binar memutuskan untuk mengendapkan kasus di tahun 2019 itu. Tidak melaporkan pada siapapun. “Saya tahu cara pembuktian ini dengan visum, dengan apapun. Tapi yang saya rasakan, perasaan saya dilecehkan seperti itu akan saya bawa sampai kapanpun,” tuturnya. Binar merasa kejadian tersebut menorehkan luka batin baginya. Sebab, hingga satu tahun berlalu, pikirannya kerap mengingat kembali kejadian tersebut. Binar merasa takut jika harus bertemu orang baru dan merasa sangat was-was jika sedang berada di luar rumah. “Sampai sekarang saya tidak bisa menghilangkan trauma itu. Bahkan belum ada merasa saya dilindungi,” ujarnya.
Perkara melaporkan pada pihak kampus, Binar sudah terlebih dahulu pesimis. Ia tidak memiliki bukti autentik. Tiada saksi mata, tiada bekas luka. “Kalau pun saya mengadu (kepada pihak kampus), apakah mereka akan membela saya?” tanya Binar dengan memicingkan mata. Binar mengaku tidak mengharapkan apapun pada pihak kampus, apalagi perihal keadilan baginya. Ia sempat memperhatikan upaya advokasi beberapa lembaga, baik internal maupun eksternal kampus terkait kasus kekerasan seksual di lingkup Universitas Udayana, banyak diantaranya mengalami kebuntuan. “Jujur saya tidak mengharapkan apapun dari kampus ini (Unud). Ketika kita melawan orang yang besar, dan kita cuma bagian kecil dari mereka, kita tidak akan pernah menang,” kata Binar. Ketiadaan sistem penanganan kasus kekerasan seksual di Unud membuatnya bungkam.
Keputusannya berani bersuara pun dipicu keinginan Binar untuk memberi dukungan jika ada korban kekerasan seksual lainnya. “Saya bukan mau memproses kasus ini lebih lanjut, tapi agar menyadarkan teman-teman biar lebih aware kalau kasus ini ada dan korban tidak dipojokkan,” tegas Binar. Sekelebat ia kembali memikirkan apa yang telah menimpanya, Binar masih terheran. “Etis tidak sih seseorang yang berpendidikan dan jabatan yang lebih tinggi daripada kita, tiba-tiba merangkul dan menarik leher?” ucapnya.
Kasus Kekerasan Seksual Terus Terulang
Tidak hanya Binar, sejak Juli tahun 2020, menurut data yang dihimpun oleh Seruni Bali, terdapat 28 aduan kekerasan seksual di Unud, sementara satu aduan berasal dari mahasiswa non-Unud. Data tersebut diantaranya, 6 korban mengalami kekerasan seksual di lingkungan Unud, 19 korban mengalami kekerasan seksual di luar lingkungan Unud, dan 3 korban mengalami kekerasan seksual di sosial media. Kasus ini banyak datang dari Fakultas Ilmu Budaya, yakni sebanyak 13 laporan. “Pelakunya paling banyak itu adalah mahasiswa dan pihak staf pengajar, tetapi tidak menutup kemungkinan masyarakat umum juga menjadi pelaku ataupun staf TU, misalnya,” papar Ufiya Amirah, selaku pihak Seruni Bali (22/9). Mayoritas korban memutuskan untuk tidak menindaklanjuti laporan kekerasan seksual ke pihak kepolisian atau Unud dengan alasan kredibilitas lembaga.
Adapun perempuan yang kerap disapa Mirah itu melihat kekerasan seksual yang terjadi tidak lepas dari ketimpangan relasi kuasa. Misalnya, terjadi antara dosen dengan mahasiswa bimbingan skripsi. Saat proses bimbingan tersebut, terkadang tindak kekerasan seksual terjadi secara verbal, yakni pembicaraan bimbingan yang merujuk pada hasrat seksual dan pengetahuan dosen akan privasi mahasiswa bimbingan. Di sisi lain, pola kasus pelecehan seksual dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) mengalami intensitas yang meningkat di tengah pandemi. Mirah, lebih lanjut, mengatakan keseluruhan penyintas mengalami trauma psikis.
Tindak kekerasan seksual yang terulang kembali di Unud disorot oleh Psikolog Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Ni Luh Indah Desira Swandi, S.Psi., M.Psi., Psikolog. Indah menyorot ketimpangan relasi kuasa yang menjadi faktor utama dalam terjadinya tindak kekerasan seksual. “Perasaan bahwa saya memiliki perasaan yang otoritas/dominan dan memiliki kekuasaan di atas korban. Ditambah stimulus lingkungan/sekitar yang mendukung,” papar Indah dalam wawancara dengan Pers Akademika via Zoom Meeting (18/10). Konteks relasi kuasa tersebut ialah ketika rasa dominasi yang timbul saat korban merasa memerlukan pelaku. Adapun faktor lingkungan yang ‘mendukung’ adalah ketika situasi sedang sepi maupun kondisi sosial yang menyepelekan tindak kekerasan seksual. Di sisi lain, terdapat pula faktor biologis, adanya ketimpangan seksual yang dialami oleh pelaku. “Yang ketiga ialah karakteristik atau kepribadian seseorang yang cenderung ingin melakukan hal yang dirasa menantang dalam kehidupan seksualnya,” lanjut Indah.
Meski jumlahnya yang tergolong banyak, namun sebagian besar penyintas tidak melaporkan kepada pihak kampus. Selain ketimpangan relasi kuasa dalam konteks kampus, keraguan korban juga berakar dari kondisi konstruksi masyarakat yang menyepelekan tindak kekerasan seksual (rape culture). Adanya rape culture mempengaruhi pandangan masyarakat untuk memiliki tendensi menyalahkan korban. Di sisi lain, konstruksi gender dalam masyarakat patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak superior dan dominan, sementara perempuan tersubordinasi dan inferior. Inilah yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang rentan dalam kekerasan seksual.
Mitos-mitos yang menyangkut tubuh perempuan inilah bagi Mirah menjadi alasan hingga saat ini kasus kekerasan seksual terabaikan, bahkan kedaluarsa. “Ketika kekerasan seksual itu berlangsung, bukan pelaku yang ditanyakan, tapi korban yg ditanya. Jadi korban yang selalu disudutkan dan dipojokkan, otomatis ia tidak mau berbicara karena malu,” ujarnya. Tidak hanya itu, pasca pelaporan oleh penyintas, kerap kali pelaku justru mengancam dan menekan korban. Hal ini diperparah dengan kondisi landasan hukum maupun penegak hukum yang belum berperspektif korban. “Jika diseriusin ke prosesi hukum, pertanyaannya, apakah hukum mengakomodir itu? dan apakah itu memprioritaskan korban?” lanjutnya.
Sehingga penanganan kasus kekerasan seksual di kampus menemui kebuntuan. Hal ini tidak hanya dimulai dari kemauan korban untuk berbicara, lebih daripada itu, ialah proses penanganan yang belum berperspektif korban, yakni tidak menempatkan hak-hak korban sebagai acuan utama dalam bertindak, tidak berprinsip menjaga kerahasiaan dan keselamatan korban, hingga tidak meminimalisir tindakan balasan dari pelaku. Di samping itu, penyebaran identitas pelaku membuat penyintas yang melapor malah terkena Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sehingga, “korban itu seringkali sekedar laporan saja, ‘saya adalah korban kekerasan seksual, tapi tidak mau diproses lebih lanjut lagi,” tambah Mirah.
Memacu Pihak Universitas Udayana Lebih Terlibat
Sementara itu, dalam lingkup kampus, perguruan tinggi yang dibayangkan menjadi ruang paling aman justru belum memiliki jaminan atas keterlindungan korban kekerasan seksual. Bahkan, Universitas Udayana belum memiliki regulasi dan Standar Operasional Penanganan (SOP) dalam rangka penanganan kasus kekerasan seksual di kampus. Secara historis, Universitas Udayana telah mengeluarkan Peraturan Rektor yang mengatur perihal kode etik, dosen, staf, beserta mahasiswa. Kode etik ini tertuang dalam Peraturan Rektor Universitas Udayana No. 13 Tahun 2018, kode etik mahasiswa tertuang dalam Peraturan Rektor No.14 Tahun 2018, dan kode etik tenaga kependidikan tertuang pada Peraturan Rektor No. 11 Tahun 2018.
Kendati demikian, peraturan rektor tersebut belum terkhusus mengatur tentang tindak kekerasan seksual yang terjadi di lingkup kampus. Kekosongan regulasi atas penanganan kekerasan seksual di Universitas Udayana ini membuat pelaporan kasus kekerasan seksual seolah tenggelam dan tiada rimbanya. Berdasarkan pengamatan Pers Akademika, belum ada upaya untuk mengakomodir penanganan kasus kekerasan seksual hingga tuntas oleh pihak Unud sebagai pertanggungjawaban institusi pendidikan tinggi yang beretika.
Adapun lembaga internal kampus juga turut memperjuangkan keadilan bagi penyintas. Pada 13 Juli 2021, Kementrian Adkesma dan Kebijakan Kampus Badan Eksekutif Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa (BEM PM) Unud mengirim surat permohonan informasi kepada rektor terkait kejelasan regulasi pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual di Unud. Surat balasan pun diterima pada 28 Juli 2021. Surat tersebut memuat ‘Unud tidak mengatur secara khusus tentang pelecehan seksual karena tidak adanya kewenangan yang didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan terkait’.
Rektor Unud: Jalur Hukum bagi Tindak Kekerasan Seksual
Sementara itu, rektor baru Universitas Udayana, Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng.IPU., menyatakan komitmennya untuk pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di Unud. Komitmen ini dipaparkannya kala dijumpai Pers Akademika pada (5/9). Namun, pada saat melakukan wawancara ini, Pers Akademika tidak diperkenankan untuk menggunakan alat rekam, foto, maupun video ke dalam ruangan rektor. Adapun upaya konfirmasi hasil transkrip wawancara Pers Akademika dengan rektor hingga saat ini tidak mendapatkan respons.
Ketika ditanya tanggapan mengenai tindak kekerasan seksual yang terjadi di jam operasional dan lingkungan kampus, ia sebagai pucuk pimpinan Unud tidak akan tebang pilih dalam menindak lanjut pelaku, baik mahasiswa maupun dosen. “Objektif apa adanya, saya tidak melindungi siapa-siapa. Saya harus menyosialisasikan ke mahasiswa, dosen, pegawai, saya tidak akan bertindak sendiri, langsung saja ke pidana dan yang mengerti,” ujarnya. Ia melanjutkan, bila tindak kekerasan seksual terjadi di lingkup kampus, ia akan menindak dan mengkomunikasikannya dengan para wakil rektor. “Namun, di luar properti Unud bukan urusan kami,” tutur rektor.
Lebih lanjut, Prof Antara belum dapat memaparkan regulasi terkait pencegahan dan penanganan tindak kekerasan seksual di kampus. Kendati demikian, ia dapat memastikan bahwa pihak Unud tidak akan menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang sudah terbukti dengan jalur kekeluargaan. “Misalnya yang bersangkutan malah penyelesaian masalahnya dengan saling memaafkan, diselesaikan kekeluargaan, no no no, kita tidak akan seperti itu. Tapi langsung aja lanjut ke ranah hukum,” tegasnya. Perihal regulasi, di hari wawancara, pihak rektorat belum menyusun hal tersebut. Sebaliknya, Prof. Antara bertanya terkait saran dari mahasiswa untuk menindak pelaku kasus kekerasan seksual di kampus. “Ide menarik, kalau dia (pelaku) di–blacklist dari jabatan kemahasiswaan,” tambahnya.
Adapun perihal mekanisme dan solusi yang ditawarkan oleh Prof. Antara saat itu ialah: (1) Kolaborasi dengan program studi, seperti psikologi. Adanya pelaporan kasus akan dikomunikasikan kepada para wakil rektor dan pihak dekanat. Prof Antara juga berencana agar setiap fakultas memiliki Bimbingan Konseling (BK), serta memberi jaminan perlindungan bagi penyintas, dan memfasilitasi penyintas untuk lulus, (2) Lecture Bulding, adanya pembangunan khusus gedung tenaga pendidik yang ditujukan untuk mengurangi kejadian layaknya kekerasan seksual. Ruang kerja dosen akan menjadi lokasi bimbingan yang wajib berada dalam jam kerja. “Laporkan saja masalah seperti pelecehan seksual itu. Kalau sudah ada gedung (lecture building), dan masih kejadian seperti itu, telpon langsung saya,” papar Prof Antara.
Bisakah Penyintas Mendapatkan Keadilan?
Berbagai rintangan baik dalam tataran hukum hingga kondisi sosial yang menghalau penyintas untuk mendapatkan keadilan, selalu menjadikan kasus kekerasan seksual seolah tenggelam. Adapun dalam memperoleh keadilan bagi penyintas, Direktur LBH Bali Women’s Crisis Center (WCC), Ni Nengah Budawati, membagikan pandangannya. Selama pengalaman dalam menjadi kuasa hukum beberapa kasus kekerasan seksual, kesaksian korban menjadi kunci terpenting. “Keberanian korban untuk berbicara. Apa artinya bukti yang sudah dikantongi kalau korban terdiam. Keadaan korban yang terjadi di pengadilan sangat berpengaruh, terutama ketika sudah membuka suara untuk berbicara,” tuturnya saat ditemui di kantor LBH Bali WCC (24/9). Di sisi lain, terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang tidak memiliki bukti otentik, bukti visum psikis dapat menjadi dukungan bukti yang kuat. Oleh karenanya, konseling menjadi pintu awal untuk memperkuat adanya kerugian psikis yang ditanggung korban pasca kasus kekerasan seksual yang menimpa.
Meski belum adanya kepastian Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), bagi Buda, tiada benar kondisi kekosongan hukum untuk menindak kasus kekerasan seksual dalam kampus. “Kalau KUHP tidak cukup, kalau kasus di rumah tangga maka pakai KDRT, kalau anak di bawah umur maka pakai UU perlindungan anak. Sampai menunggu RUU PKS yang paling komplit,” kata Buda menjelaskan. Ia tidak gusar untuk mencari celah dalam regulasi yang dapat dijadikan sarana untuk meraih keadilan bagi penyintas. Justru, Buda khawatir terhadap kondisi sosial masyarakat. “Contoh, korban yang dinikahkan dengan pelaku, oleh kakek/bapaknya. Di satu sisi menjawab anak yang dilahirkan itu tidak dijadikan anak haram, maka dinikahkan korban dengan pelakunya,” tambahnya.
Buda mewakili LBH Bali WCC mengaku siap untuk membantu menjadi pendamping hukum maupun kuasa hukum bagi korban kekerasan seksual dalam lingkup kampus. LBH Bali WCC memiliki mekanisme penanganan yang berfokus pada pemulihan korban pasca kejadian. Maka, pertemuan antara penyintas dengan psikolog LBH Bali WCC menjadi prioritas. “Kemudian psikolog kami yang mengkoordinasikan untuk memberikan penanganan. Yang saya senang, mereka (penyintas) sudah ditangani secara psikologis, minimal, daripada tidak, meskipun tidak melaporkan,” ungkap Buda seraya tersenyum.
Perspektif korban adalah prinsip utama yang diamini oleh LBH Bali WCC, tentu juga bagi Buda. Hal ini untuk memberikan dukungan penuh bagi penyintas agar dapat bersuara. “(Kebenaran) itu diperlukan kajian. Sikap kita yg pertamanya itu 1000% percaya dulu, berjalannya waktu, kalau memang salah jangan menjadi pembela tapi jadilah pemberdayaan,” jelas Buda. Ketika pihak yang bersangkutan ternyata adalah pelaku, namun memanipulasi menjadi korban, jalan keluar bagi Buda ialah memosisikan diri sebagai pendamping dan memberikan pemberdayaan bahwa apa yang diperbuat adalah hal yang tidak dapat dibenarkan. “Saat perempuan menjadi pelaku, dirimu bersikap menjadi pendamping. Kalau dia korban, bela menjadi pembela sampai ke ujung dunia,” lanjutnya seraya menatap tajam.
Saat ini, aturan mengenai penanganan tindak kasus kekerasan seksual di lingkup kampus sudah diterbitkan dalam Permendikbud No. 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Permendikbud itu pun diperuntukkan sebagai pedoman bagi Perguruan Tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di dalam atau di luar kampus.
Penanganan kasus kekerasan seksual yang bertumpu pada pihak petinggi kampus dipandang pesimis oleh Buda, hal ini dikarenakan kerap kali kampus hanya mempertimbangkan citra institusi dan bermuara pada pembiaran penanganan. Inilah cikal-bakal ketidakpercayaan penyintas jika ingin melapor. “Korban berani melapor dan didukung oleh kampus. Itu saja. Jika kampus mendukung, maka semua korban siap!” seru Buda menyarankan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkup kampus.
Jika Orang di Sekitar Kita menjadi Korban Kekerasan Seksual
Kekerasan seksual memang dapat terjadi di mana saja. Bahkan orang di sekitar kita dapat menjadi korban kekerasan seksual. Bagi Indah, ada beberapa hal secara psikologis yang dapat digunakan untuk melatih empati terhadap korban kekerasan seksual. “Korban kekerasan seksual yang pasti pada saat kejadian akan merasakan freeze,” papar Indah. Freeze ini terjadi tatkala penyintas tidak tahu akan melakukan apa. Gejalanya; korban yang mendadak tidak ingin berinteraksi dalam rentang beberapa hari. Hal ini disebabkan karena korban menarik diri dari lingkungan sosialnya. “Itu dapat menjadi mirip seperti ‘seseorang yang mengalami gangguan psikologis’. Untuk mendeteksi itu hanya dari sini saja. Meningkatkan empati, empati itu di kalangan mahasiswa,” tambah Indah. Lebih lanjut, selain gejala gangguan psikologis, hal ini dapat ditelusuri terhadap ketidak-mauan seseorang untuk berada dalam ruangan atau keadaan yang menjadi stimulus trauma.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika masing-masing dari kita menjadi tempat seseorang untuk menceritakan tindak kekerasan seksual yang menimpanya. “Pertama, harus memastikan diri kita sendiri sebagai pendengarnya. Kedua, kita perlu menjadi pendengar aktif, kita mendengarkan tanpa mendistraksi penderita dengan berbagai pertanyaan yg mungkin tidak diperlukan, mereka hanya perlu didengarkan,” paparnya. Indah menegaskan untuk menghindari pertanyaan yang bersifat ‘kepo’. Selanjutnya, komitmen membantu dapat ditunjukkan dengan mencari maupun memberi informasi yang berkaitan dengan pemulihan penyintas. “Kalau merasa tidak mampu mendengar, kita dapat memberikan refer atau mencarikan informasi mengenai orang yang kita ketahui dan kita yakin dapat membantu korban kekerasan seksual,” jelas Indah. Di sisi lain, dukungan secara emosional menjadi hal yang penting bagi pemulihan penyintas. Bentuknya; menunjukkan kepercayaan kepada penyintas.
Terkait wacana bimbingan konseling yang diupayakan dengan program studi Psikologi FK Unud, Indah mengaku siap mendukung program tersebut untuk mencegah adanya pelecehan dan kekerasan seksual di kampus. “Harapan saya, semuanya tidak tutup mata, karena sudah ada fakta yang menunjukan bahwa ini terjadi, dan harapan saya semua mendukung upaya pencegahan.” Tutup Indah.
Liputan oleh Pers Mahasiswa Akademika ini adalah bagian dari kolaborasi bersama 21 Lembaga Pers Mahasiswa lain di seluruh Indonesia demi kampus yang aman bagi semua. Kolaborasi yang dimulai sejak Oktober 2021 ini didukung oleh Project Multatuli.
Penanggung Jawab: Bagus Perana
Reporter: Galuh Sriwedari, Kamala Dewi, Lefira, Ihsan Muhabil, Yuko Utami, Hasnah Yunita
Penulis: Galuh Sriwedari
Penyunting: Gangga Samala
Ilustrator: Made Astrawan
Tata Letak: Iyan Merta, Tryadhi Putra
Riset: Dewi
Kontak bantuan
Apabila kamu pernah mengalami kekerasan seksual, seluruh pengalaman dan perasaanmu valid. Kamu berharga dan kami berpihak kepadamu. Jika kamu mengalami kekerasan seksual, memiliki kerabat yang mengalami kekerasan seksual, atau menemukan tindak kekerasan seksual di sekitarmu, jangan ragu untuk melaporkannya dan mencari bantuan psikologis maupun hukum dari lembaga-lembaga berikut:
- Pengada Layanan dan pencegahan Kekerasan Seksual di Unud (HopeHelps)
Hotline (Whatsapp): 081337982562
Email: advokasi.hopehelps.unud@gmail.com
- Badan Eksekutif Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa (BEM PM) Unud
Hotline (Line): @bem_udayana
3. Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI) Bali
Tautan aduan: http://bit.ly/StopBungkam
Email: serunibali1@gmail.com
- LBH BALI WCC
Hotline (Whatsapp): +62 881-0387-76371
Telfon: (0361)8444352
Email: lbhbwcc@gmail.com
5.Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)
Hotline (Whatsapp): 08111-129-129