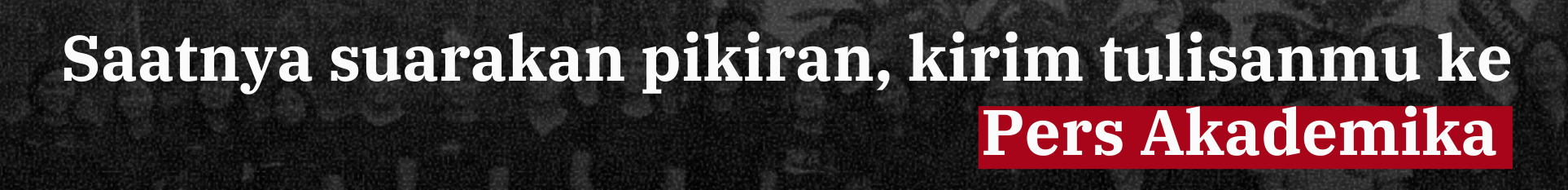OSS dan Kekosongan RDTR: Menakar Risiko Tata Ruang di Situs Warisan Dunia Jatiluwih

Desa Jatiluwih, yang terletak di kawasan agraris Kabupaten Tabanan, menghadapi tekanan pembangunan yang semakin masif akibat pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata. Di tengah posisinya sebagai situs Warisan Budaya Dunia, desa ini justru berada dalam situasi regulatif yang lemah. Sistem perizinan berusaha terpusat seperti OSS tetap berjalan meskipun wilayah ini belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), sehingga membuka ruang bagi pembangunan yang tidak terkendali. Ketidakhadiran instrumen pengaturan ruang yang spesifik menjadikan kawasan ini rentan terhadap alih fungsi lahan dan degradasi nilai-nilai budaya maupun ekologis yang seharusnya dilindungi.
Pengantar
Provinsi Bali menunjukkan pertumbuhan sektor pariwisata yang signifikan. Data BPS Bali (2024) mencatat, jumlah wisatawan mancanegara yang datang langsung ke Bali pada April 2024 mencapai 503.194 kunjungan, naik 7,24 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Lonjakan aktivitas pariwisata ini mendorong percepatan pembangunan fasilitas akomodasi di berbagai wilayah, termasuk di kawasan agraris. Sejak 1990 hingga 2000-an, di Bali terjadi alih fungsi lahan persawahan sekitar 750 hektar setiap tahun. Menurut Ketua Unit Subak Bidang Sosial Ekonomi Universitas Udayana I Ketut Suamba, tren alih fungsi lahan yang berlanjut disertai pertumbuhan jumlah penduduk dapat mengancam ketersediaan lahan persawahan di Bali pada 2050. Kondisi ini, sebagaimana diberitakan Kompas (2022), dinilai berbahaya bagi kelangsungan Subak yang telah diakui UNESCO sebagai warisan dunia sejak 2012. Situasi ini semakin kompleks dengan diterapkannya sistem Online Single Submission (OSS), yaitu sistem perizinan usaha terpusat berbasis daring yang memungkinkan pelaku usaha memperoleh izin tanpa keterlibatan langsung dari pemerintah daerah. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum (2024), Provinsi Bali telah memiliki 24 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Tabanan hanya memiliki 2 RDTR, yakni RDTR Kawasan Perkotaan Tabanan dan RDTR Kecamatan Selemadeg Barat. OSS tetap dapat beroperasi di wilayah yang belum RDTR, dengan hanya berpedoman pada RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang bersifat makro. Akibatnya, pembangunan yang tidak sesuai fungsi ruang tetap bisa mendapat izin secara administratif, meskipun secara substansi bertentangan dengan prinsip tata ruang yang baik. Tanpa dokumen resmi yang memuat rincian zonasi, batas kawasan lindung, dan intensitas bangunan, OSS membuka celah legalisasi pembangunan yang tidak berbasis kondisi spasial riil. Hal ini membuat banyak pembangunan yang sah di atas kertas, tetapi tidak legitimate secara tata ruang.
Kabupaten Tabanan, yang terdiri dari 10 kecamatan dan 133 desa dengan dominasi lahan pertanian subur, juga menghadapi tekanan pembangunan. Salah satu wilayah yang kini berada dalam tekanan pembangunan yang cukup tinggi adalah Desa Jatiluwih, yang terletak di Kecamatan Penebel. Desa ini merupakan salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) utama sekaligus situs Warisan Budaya Dunia (WBD) yang ditetapkan UNESCO sejak tahun 2012 berkat kelestarian sistem Subak. Setelah penetapan tersebut dibentuk Badan Pengelola DTW Jatiluwih berdasarkan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 84 Tahun 2013. Sejak pengakuan tersebut, aktivitas pariwisata di Jatiluwih meningkat pesat. Dalam tiga tahunn terakhir, lebih dari 200.000 turis domestik dan mancanegara mengunjungi kawasan ini setiap tahun yang diiringi dengan bertambahnya pembangunan akomodasi wisata seperti villa dan penginapan. Sayangnya, hingga tahun 2025, kawasan ini belum memiliki RDTR, padahal dokumen tersebut telah lama didesak oleh pemerhati lingkungan untuk menjamin perlindungan spasial kawasan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) I Made Dedy Darmasaputra tidak menafikan ihwal Jatiluwih belum memiliki RDTR. Menurutnya, Forum Penataan Tata Ruang (FPTR) Kabupaten Tabanan dibentuk untuk memastikan kesesuaian lahan, mengendalikan tata ruang, serta membantu dalam penyusunan kajian RDTR yang hingga kini belum ditetapkan meski RTRW sudah ada. Tanpa adanya RDTR, tidak terdapat dasar legal yang kuat untuk membatasi pembangunan atau menegakkan pengawasan tata ruang, sehingga kawasan ini menjadi sangat rentan terhadap ekspansi pembangunan yang tidak terkendali. Sebagaimana dinyatakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (2012), RDTR dan Peraturan Zonasi sangat diperlukan sebagai acuan operasional dalam pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang, acuan dalam pelaksanaan pembangunan, serta acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk izin mendirikan bangunan. Lonjakan wisatawan yang mendorong pembangunan akomodasi ini pada akhirnya bukan hanya soal pariwisata, melainkan juga soal bagaimana lahan pertanian dialihkan dan sistem agraris tradisional Bali dipertaruhkan.
Pembangunan Masif Akibat Pariwisata di Bali
Pariwisata merupakan sektor utama mata pencaharian masyarakat di Provinsi Bali. Seiring meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan setiap tahunnya, baik dari dalam maupun luar negeri, kebutuhan akan fasilitas pendukung pun ikut melonjak. Kondisi ini mendorong pembangunan besar-besaran yang bertujuan untuk memenuhi kenyamanan wisatawan sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat lokal. Hotel, vila, restoran, dan berbagai jenis akomodasi lainnya mulai dibangun di berbagai penjuru Bali, tidak hanya di kawasan wisata populer, tapi juga mulai merambah desa-desa yang dulunya tenang dan agraris.

Gambar 1. Perubahan Tata Guna Lahan di Kawasan Jatiluwih (2002–2024).
Sumber: abc.net.au
Pertumbuhan infrastruktur pariwisata ini memang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di banyak tempat. Namun, perlu dicermati bahwa perkembangan tersebut tidak selalu dibarengi dengan pengendalian ruang yang ketat. Dalam banyak kasus, pembangunan berlangsung tanpa panduan tata ruang yang jelas dan sering kali mengabaikan karakter lingkungan dan budaya setempat. Pembangunan hotel atau villa di kawasan subak, misalnya, berpotensi mengganggu sistem irigasi tradisional yang telah diwariskan turun-temurun. Tidak sedikit pula pembangunan dilakukan di kawasan tanpa izin yang sesuai, atau di wilayah yang belum memiliki rencana tata ruang terperinci. Hal ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara dorongan ekonomi melalui pariwisata dan kesiapan regulasi tata ruang yang seharusnya mengarahkan pembangunan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Namun, di balik geliat pembangunan pariwisata tersebut, aspek yang paling terancam justru adalah sistem agraris. Sawah produktif yang menopang Subak perlahan bergeser menjadi villa dan restoran, sehingga isu pariwisata sesungguhnya bermuara pada persoalan agraria, seperti halnya yang terjadi di Jatiluwih.
Kekosongan RDTR dan Penerapan OSS di Tengah Perkembangan Pariwisata Jatiluwih
Kawasan Desa Adat Jatiluwih merupakan salah satu wilayah yang hingga kini belum memiliki RDTR. RDTR merupakan dokumen rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi. Ketiadaan RDTR menimbulkan persoalan dalam hal kepastian hukum pemanfaatan ruang, terutama di kawasan yang memiliki status penting seperti Desa Adat Jatiluwih yang telah ditetapkan sebagai WBD UNESCO. Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP No. 21/2021) menyatakan, RDTR kabupaten/kota mengacu pada RTRW kabupaten/kota, serta RDTR ini mencakup kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, serta kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) PP yang sama. Dengan demikian, RDTR menjadi instrumen wajib yang tidak hanya memuat arahan peruntukan ruang, tetapi juga berfungsi sebagai acuan utama dalam pemanfaatan ruang serta instrumen pengendalian agar tidak terjadi penyimpangan tata ruang di lapangan.
Lebih lanjut, ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 58 ayat (4) PP No. 21/2021 yang menyatakan bahwa penyusunan RDTR dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan menteri. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang yang menegaskan, setiap RDTR harus dilengkapi dengan peraturan zonasi. Peraturan zonasi berfungsi sebagai instrumen pengaturan teknis pemanfaatan ruang yang berisi ketentuan mengenai persyaratan pemanfaatan ruang dan pengendaliannya, yang wajib disusun untuk setiap blok atau zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik kawasan. Dengan adanya peraturan zonasi dalam RDTR, maka kegiatan pembangunan dapat diarahkan secara lebih terukur, baik untuk menjaga fungsi asli kawasan maupun untuk mengakomodasi pengembangan fungsi-fungsi baru yang sesuai dengan karakteristik dan daya dukung lingkungan setempat
Tabel 1. Ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kabupaten Tabanan.
| Nama RDTR | Luas Wilayah (Ha) | Luas Wilayah Kabupaten/Kota (Ha) | Persentase Ketersediaan RDTR (%) |
| RDTR Kawasan Perkotaan Tabanan | 26608,7 | 84.931,59 | 3,14 |
| RDTR Kecamatan Selemadeg Barat | 10857,95 | 84.931,59 | 12,78 |
13.526,03 84.931,59 15,93
Sumber: tarubali PUPRKIM prov. Bali
Kekosongan RDTR diperparah dengan penerapan sistem OSS di Desa Jatiluwih. OSS merupakan bentuk inovasi pelayanan publik di bidang perizinan dengan mengadopsi teknologi informasi di bidang pelayanan perizinan. Pelayanan OSS tersebut bertujuan agar mekanisme perizinan yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat dilakukan secara efektif dan efisien, serta untuk menghindari terjadinya praktik korupsi yang seringkali terjadi dalam sektor perizinan. Namun dalam implementasinya, sistem ini justru membuka celah baru karena proses perizinan dapat diselesaikan secara daring tanpa verifikasi mendalam terhadap kondisi riil di lapangan. Gubernur Bali I Wayan Koster menyatakan, sistem OSS membuka peluang bagi investor asing untuk menguasai sektor strategis, bahkan hingga level mikro seperti penyewaan kendaraan dan penginapan (Muliantari, N. P. P., 2025). Hal ini menjadi persoalan serius di kawasan seperti Jatiluwih, yang belum memiliki RDTR sebagai acuan tata ruang. Sejak ditetapkan sebagai DTW dan masuk dalam kawasan WBD oleh UNESCO pada 2012, Desa Jatiluwih mulai menarik perhatian pelaku industri pariwisata. Perlahan-lahan, pembangunan fasilitas wisata mulai bermunculan, mulai dari vila, restoran, hingga warung makan yang menyasar wisatawan domestik maupun mancanegara. Sayangnya, geliat pembangunan ini tidak diiringi dengan pengaturan tata ruang yang memadai. Tanpa adanya RDTR, sulit untuk menentukan zona mana yang boleh atau tidak boleh dibangun, serta jenis bangunan yang sesuai dengan karakter dan fungsi kawasan. Situasi ini diperparah oleh fakta di lapangan. Sejak diberlakukan, sistem OSS memicu lonjakan perizinan untuk sektor wisata di Bali bahkan di wilayah tanpa regulasi tata ruang yang rinci seperti Jatiluwih. Izin bisa keluar secara administratif tanpa verifikasi lapangan, selama pelaku usaha memenuhi persyaratan dokumen secara daring. Hal ini membuka celah bagi berkembangnya pembangunan yang tampak sah di atas kertas, tetapi secara nyata tidak sesuai dengan fungsi ruang dan karakter lingkungan kawasan ini. Kasus nyata terjadi di Jatiluwih dan tengah menjadi sorotan. Forum Penataan Ruang Kabupaten Tabanan mencatat ada 13 usaha wisata yang terindikasi melanggar tata ruang, seperti Villa Yeh Baat, The Rustic/Sunari Bali, serta beberapa warung seperti Warung Manalagi dan Cata Vaca Jatiluwih yang dibangun di area Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan di dalam kawasan WBD UNESCO. Kasus ini semakin memuncak hingga jumlah pelanggar diduga bertambah menjadi lebih dari 20 lokasi, mencerminkan keterbatasan upaya penegakan terhadap pelanggaran yang sudah terdeteksi sebelumnya (Yoni, I. G. K., 2025).
Guru Besar Unud I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja menjelaskan, ketiadaan RDTR dapat mengakibatkan pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang, misalnya pendirian bangunan industri di kawasan yang sebenarnya bukan diperuntukkan sebagai kawasan industri. Ketiadaan RDTR dalam hal ini tidak hanya menjadi hambatan, melainkan juga memperbesar risiko terjadinya penyelewengan pemanfaatan ruang. Tanpa adanya kepastian zonasi dan peraturan yang legal serta mengikat, OSS berpotensi dimanfaatkan untuk memperoleh izin secara instan meskipun bertentangan dengan kepentingan pelestarian kawasan. Dalam konteks Jatiluwih, kondisi ini menjadi ancaman langsung terhadap keberlanjutan statusnya sebagai WBD serta keseimbangan ekologis yang menopang kehidupan masyarakat adat setempat. Tanpa adanya RDTR, perizinan melalui OSS membuka ruang bagi alih fungsi lahan yang merugikan petani dan merusak Subak. Inilah yang menegaskan bahwa persoalan tata ruang bukan sekadar administratif, melainkan menyangkut masa depan agraria Jatiluwih. Lebih lanjut, fenomena tarik-menarik kewenangan dalam pengelolaan ruang di Jatiluwih dapat dibaca melalui perspektif pluralisme hukum. Menurut John Griffiths dalam jurnal berjudul Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional karya Sartika Intaning Pradhani, legal pluralism menggambarkan adanya lebih dari satu sistem hukum yang hidup dan berlaku dalam satu masyarakat. Griffiths membedakan dua bentuknya: weak legal pluralism, yakni ketika hukum negara tetap dominan dan hanya mengakui hukum adat sejauh diatur oleh regulasi formal; serta strong legal pluralism, ketika hukum adat berdiri sejajar dengan hukum negara sebagai sistem hukum yang otonom.
Kasus Jatiluwih memperlihatkan praktik weak legal pluralism. Sistem perizinan berbasis OSS mewakili hukum negara yang menekankan legalitas administratif, sementara Subak sebagai lembaga adat yang mengatur tata air, tanah, dan solidaritas petani tidak mendapatkan posisi formal dalam proses perizinan. Akibatnya, izin pembangunan vila atau restoran di kawasan sawah bisa sah secara hukum negara, tetapi dianggap melanggar norma adat karena merusak keseimbangan agraris yang dilestarikan oleh Subak. Kondisi ini menimbulkan konflik legitimasi. Secara formal, izin OSS memiliki kekuatan hukum positif, tetapi secara sosial, keberadaannya sering dipandang tidak legitimate oleh masyarakat adat. Subak melihat tanah bukan sekadar objek ekonomi, melainkan ruang hidup spiritual yang terikat dengan sistem irigasi, upacara, dan solidaritas sosial. Di sisi lain, negara cenderung memandang sawah hanya sebagai zonasi teknis yang bisa dialihfungsikan apabila peraturan tata ruang mengizinkan. Ketegangan ini semakin nyata ketika kekosongan RDTR membuka ruang abu-abu. Tanpa RDTR, OSS berjalan sendiri sebagai instrumen hukum negara, sementara Subak kehilangan daya tawar sebagai hukum adat. Akibatnya, negara gagal menyediakan instrumen tata ruang yang legitimate, dan masyarakat adat merasa dipinggirkan dari pengambilan keputusan atas ruang hidupnya sendiri. Dengan demikian, kasus Jatiluwih memperlihatkan bagaimana pluralisme hukum tidak hanya menghasilkan keragaman norma, tetapi juga membuka potensi konflik ketika negara menempatkan hukum adat dalam posisi subordinat.
Agraria dan Subak sebagai Fondasi Tata Ruang Jatiluwih
Lahan pertanian Jatiluwih merupakan inti dari lanskap budaya yang diakui UNESCO sebagai WBD. Melalui sistem Subak, masyarakat setempat telah mengembangkan tata kelola agraris yang berlandaskan prinsip kebersamaan. Subak tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme distribusi air, tetapi juga sebagai sistem sosial yang mengatur pola tanam, kerja kolektif, serta hubungan antar petani. Inilah yang menjadikan Subak bukan sekadar praktik pertanian, melainkan warisan budaya yang mencerminkan harmoni antara masyarakat dengan lingkungan sekitarnya. Peran Subak dalam tata ruang Jatiluwih sangat vital karena keberadaannya memastikan pemanfaatan lahan selalu memperhatikan daya dukung lingkungan. Pola terasering yang khas, misalnya, bukan hanya menghadirkan pemandangan indah, tetapi juga mencerminkan adaptasi manusia terhadap kondisi geografis setempat. Hal ini membuat sawah Jatiluwih memiliki fungsi ekologis yang penting, yakni menjaga resapan air, mencegah erosi tanah, dan mendukung ketersediaan pangan lokal. Dengan kata lain, Subak adalah fondasi tata ruang yang menempatkan agraria sebagai pusat keberlanjutan wilayah. Lebih jauh, Subak bukan hanya sistem produksi pangan, melainkan pranata sosial yang merekatkan identitas masyarakat Jatiluwih. Upacara-upacara adat yang menyertai siklus tanam padi mencerminkan keterhubungan erat antara praktik agraris dengan nilai spiritual masyarakat Bali yang menjadi kerangka filosofis dalam menjadikan Subak lebih dari sekadar sistem irigasi. Di Bali, tanah bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga ruang sakral yang menyimpan nilai kultural. Dengan demikian, keberlanjutan Subak merupakan syarat utama bagi keberlanjutan tata ruang Jatiluwih secara menyeluruh. Namun, tekanan terhadap Subak semakin besar seiring berkembangnya pariwisata. Sebagaimana diingatkan oleh Diarta dan Sarjana (2019), diperlukan aturan ketat untuk mengendalikan alih fungsi lahan dan membatasi masuknya tenaga eksternal ke Subak guna mempertahankan sistem agraris tradisional. Tanpa pengendalian yang jelas, saluran irigasi terganggu, lahan produktif berkurang, dan nilai sosial gotong royong mulai tergerus. Pergeseran orientasi tata ruang dari basis agraris ke basis kapital ini menimbulkan ancaman serius terhadap kelestarian Subak. Jika pola ini dibiarkan, maka keunikan Jatiluwih sebagai lanskap agraris berpotensi hilang dan status warisan dunia bisa terancam. Krisis ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari dinamika agraria yang lebih luas di Bali. Kendati Jatiluwih memiliki status istimewa sebagai warisan dunia, tetap tidak terlepas dari tren tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa tanpa perlindungan tata ruang yang kuat, bahkan kawasan dengan pengakuan internasional pun rentan kehilangan karakter agrarisnya.
Prinsip hukum agraria Indonesia sejatinya sudah menegaskan bahwa tanah memiliki fungsi sosial. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menekankan bahwa hak atas tanah tidak dapat dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan harus memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Dalam jurnal berjudul Polemik Fungsi Sosial Tanah dan Hak Menguasai Negara Pasca UU Nomor 12 Tahun 2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/ PUU-X/2012 karya King Faisal Sulaiman menjelaskan, fungsi sosial tanah merupakan jiwa UUPA yang memastikan pemanfaatan lahan selalu sejalan dengan kepentingan bersama, bukan hanya logika ekonomi individu. Lebih lanjut, fungsi sosial tanah berkaitan erat dengan hak asasi manusia, pembangunan berkelanjutan, serta kewajiban negara untuk menjamin keadilan antargenerasi. Dalam konteks Jatiluwih, pemanfaatan sawah yang dialihfungsikan menjadi vila atau restoran tanpa mempertimbangkan keberlanjutan Subak jelas bertentangan dengan prinsip fungsi sosial tanah. Dengan kata lain, praktik alih fungsi lahan yang difasilitasi oleh celah regulasi tidak hanya mengancam ekologi dan budaya, tetapi juga mencederai mandat konstitusional agraria yang menempatkan tanah sebagai basis kesejahteraan bersama. Subak di Jatiluwih sesungguhnya dapat dilihat sebagai contoh tata kelola ruang berbasis masyarakat (community-based spatial governance). Mekanisme pengaturan air dan tanah dilakukan secara partisipatif, melalui kesepakatan petani dan pemuka adat, tanpa perlu birokrasi yang rumit. Sistem ini membuktikan bahwa kearifan lokal dapat menjadi instrumen efektif dalam menjaga keberlanjutan agraris. Sayangnya, model partisipatif tersebut semakin tersisih ketika OSS memungkinkan perizinan usaha ditentukan secara daring tanpa konsultasi dengan masyarakat lokal. Pergeseran ini menimbulkan jurang antara tata kelola tradisional dengan tata kelola modern, yang pada akhirnya memperlemah posisi Subak dalam mempertahankan keberlanjutan ruang. Dengan demikian, menjaga keberlangsungan Subak bukan hanya urusan pelestarian budaya, melainkan juga bagian dari strategi agraria nasional. Lahan sawah Jatiluwih bukan sekadar pemandangan indah untuk turis, tetapi basis produksi pangan, benteng ekologi, serta identitas kolektif masyarakat Bali. Apabila keberadaan Subak tidak lagi diperhitungkan dalam tata ruang, maka ancaman yang dihadapi bukan hanya hilangnya status UNESCO, melainkan juga hilangnya fondasi agraria yang menopang ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan di Bali.
Kebijakan Agraria dalam Perlindungan Lahan Pertanian Jatiluwih
Secara normatif, Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi yang menjadi dasar perlindungan lahan pertanian. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) mengamanatkan agar pemerintah pusat maupun daerah menjaga lahan sawah sebagai aset strategis yang tidak dapat dialihfungsikan sembarangan. Demikian pula, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mewajibkan adanya keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan kawasan yang memiliki fungsi ekologis dan agraris. Kedua instrumen hukum ini kemudian dijabarkan dalam RTRW yang seharusnya ditindaklanjuti oleh RDTR. Dalam konteks Jatiluwih, keberadaan RDTR semestinya menjadi tameng utama yang memastikan sawah tidak tersentuh oleh pembangunan non-agraris. Sayangnya, tanpa RDTR, perlindungan tersebut menjadi lemah. OSS tetap dapat mengeluarkan izin usaha hanya dengan berpedoman pada RTRW yang bersifat makro. Akibatnya, investor dapat memperoleh izin legal secara administratif meskipun bangunan berdiri di atas sawah produktif yang seharusnya dilindungi. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi normatif dengan realitas implementasi di lapangan. Selain masalah regulasi, terdapat pula tantangan dalam hal penegakan hukum. Banyak kasus pelanggaran tata ruang di Bali, termasuk di Jatiluwih, tidak ditindak tegas. Ketika pelanggaran hanya berakhir dengan teguran tanpa sanksi nyata, pesan yang sampai kepada publik adalah hukum tata ruang bersifat lunak dan dapat dinegosiasikan. Kondisi ini mendorong semakin banyak investor untuk memanfaatkan celah tersebut, karena risiko hukum yang dihadapi relatif kecil dibandingkan dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh. Fenomena tersebut juga tercermin dalam wawancara yang dihimpun oleh Sistem Informasi Wilayah dan Tata Ruang Bali, di mana seorang narasumber mengakui bahwa ia pada akhirnya ikut melakukan pelanggaran, dengan alasan bahwa pelanggaran serupa sebelumnya tidak pernah ditindak secara tegas. Situasi ini menunjukkan bahwa lemahnya penegakan aturan tata ruang ditambah dengan ketiadaan RDTR di sejumlah wilayah Bali semakin memperbesar peluang terjadinya pembangunan yang tidak sesuai peruntukan ruang.
Dari perspektif agraria, kondisi tersebut merupakan bentuk pengabaian terhadap hak masyarakat lokal untuk mempertahankan sumber penghidupan. UU PLP2B sebenarnya menempatkan petani sebagai subjek yang harus dilindungi, tetapi dalam praktiknya, perlindungan lebih sering diberikan pada pelaku usaha melalui izin-izin yang cepat dan instan. Akibatnya, lahan sawah yang seharusnya menjadi bagian dari ketahanan pangan justru menyusut di bawah tekanan logika pasar. Di Subak Jatiluwih sendiri, luas lahan produktif mengalami penurunan dari sekitar 303 hektar menjadi 270 hektar, atau berkurang sebanyak 33 hektar dalam beberapa tahun terakhir. Penyusutan ini terjadi akibat alih fungsi lahan dan terganggunya sistem irigasi, sehingga mengancam keberlanjutan Subak sekaligus memperlemah peran sawah sebagai penopang ketahanan pangan masyarakat setempat (Bali Express, 2023). Dengan demikian, kebijakan agraria yang ada tidak cukup hanya hadir di atas kertas. Perlindungan lahan pertanian di Jatiluwih baru akan efektif jika disertai RDTR yang mengikat secara hukum dan dilaksanakan dengan pengawasan ketat. Tanpa itu, aturan sebaik apa pun akan tetap menjadi formalitas, sementara alih fungsi lahan akan terus berjalan.
Konflik dan Dinamika Agraria di Jatiluwih
Alih fungsi lahan pertanian Jatiluwih telah menimbulkan konflik multidimensi, mulai dari sosial, ekonomi, hingga politik tata ruang. Tercatat sedikitnya 13 usaha wisata melanggar tata ruang, termasuk pembangunan vila dan restoran di kawasan LSD di Subak Jatiluwih, Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Pelanggaran ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi mencerminkan lemahnya komitmen perlindungan agraria di kawasan warisan dunia. Bagi petani Subak, sawah yang dikonversi tidak hanya kehilangan fungsi produksinya, melainkan juga merusak sistem sosial dan spiritual yang telah mereka jaga secara turun-temurun. Konflik sosial muncul ketika masyarakat adat Subak berhadapan dengan pelaku usaha wisata yang membawa logika kapital. Subak memandang tanah sebagai warisan leluhur yang harus dijaga dan diwariskan, sementara investor melihatnya sebagai instrumen akumulasi modal. Perbedaan orientasi ini menimbulkan ketegangan, terutama ketika pembangunan vila atau restoran dilakukan di tengah area sawah produktif. Banyak petani merasa ruang hidupnya terancam, sementara mereka tidak memiliki daya tawar yang cukup untuk menolak izin yang telah dikeluarkan oleh OSS. Dari segi ekonomi, ketimpangan juga tampak jelas. Keuntungan besar sektor wisata lebih banyak dinikmati oleh investor dari luar desa, sementara petani mengalami penurunan produktivitas akibat berkurangnya lahan dan terganggunya sistem irigasi Subak. Kondisi ini membuat kesejahteraan masyarakat lokal tidak ikut meningkat secara proporsional dengan perkembangan wisata. Generasi muda Jatiluwih pun mulai melihat pertanian sebagai profesi yang tidak menjanjikan, sehingga memilih meninggalkan sawah untuk bekerja di sektor jasa. Hal ini ditegaskan oleh salah seorang pemuda Desa Jatiluwih yang diwawancarai pada 2 Agustus 2025. Menurutnya, bertani merupakan kegiatan mulia, tetapi dalam segi pendapatan relatif rendah dan fluktuatif, sedangkan pekerjaan di sektor pariwisata menawarkan penghasilan bulanan yang lebih stabil dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa tergantung pada siklus panen. Jika pola ini terus berlangsung, Jatiluwih berpotensi menghadapi krisis regenerasi petani, yang berarti Subak sebagai sistem agraris bisa runtuh dari dalam.
Selain dimensi sosial dan ekonomi, konflik juga erat kaitannya dengan dinamika politik dalam tata ruang. Proses perizinan melalui OSS kerap berlangsung tanpa melibatkan partisipasi masyarakat adat, sehingga keputusan yang diambil cenderung dipersepsikan kurang sah secara sosial. Hal ini juga ditegaskan oleh Perbekel Jatiluwih, I Nengah Kartika dalam wawancara, yang menyebutkan bahwa desa kerap kali tidak dilibatkan dalam proses awal pengajuan izin. Menurutnya, desa baru mengetahui setelah izin terbit, sehingga ruang untuk memberikan masukan terkait kesesuaian dengan adat dan kondisi lapangan menjadi sangat terbatas. Ketidakadilan ini diperparah oleh lemahnya pengawasan pemerintah daerah, yang kesulitan menindak pelanggaran karena terbentur oleh administrasi perizinan yang telah sah secara formal. Situasi ini menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara tata kelola ruang berbasis hukum formal dengan tata kelola ruang berbasis kearifan lokal. Apabila konflik agraria di Jatiluwih tidak segera diselesaikan, risiko yang muncul bukan hanya hilangnya sawah produktif, melainkan juga polarisasi sosial di dalam desa. Petani yang merasa tersisihkan bisa kehilangan kepercayaan pada pemerintah, sementara investor terus memperluas bisnisnya dengan legitimasi izin formal. Hal ini berpotensi melahirkan sengketa agraria berkepanjangan yang merusak stabilitas sosial. Oleh karena itu, penyelesaian konflik agraria di Jatiluwih harus ditempuh melalui pendekatan partisipatif, dengan menempatkan masyarakat Subak sebagai aktor utama dalam setiap kebijakan tata ruang.
Menakar Dampak dan Risiko Kekosongan RDTR di Jatiluwih
Ketiadaan RDTR di Jatiluwih membawa implikasi yang luas terhadap tata ruang, ekologi, sosial ekonomi, dan budaya. Dari aspek ekologis, pembangunan vila dan restoran di atas lahan sawah berpotensi menimbulkan gangguan serius pada sistem Subak. Saluran irigasi yang semestinya mengalir ke sawah menjadi terputus, pola tanam menjadi terganggu, dan daya serap air tanah menurun drastis. Selain itu, konversi lahan sawah menjadi bangunan permanen meningkatkan risiko erosi tanah dan menurunkan kualitas ekosistem agraris. Jika dibiarkan, daya dukung lingkungan Jatiluwih dapat menurun sehingga fungsi sawah sebagai penyokong ketahanan pangan tidak lagi optimal. Pada dimensi sosial-ekonomi, kekosongan RDTR memicu pertumbuhan pembangunan wisata yang tidak terkendali. Investor dapat memperoleh izin usaha melalui OSS meski tidak ada zonasi yang mengatur detail lokasi pembangunan. Akibatnya, pembangunan skala besar sering kali mengabaikan kepentingan masyarakat lokal. Ketimpangan pun muncul: pelaku usaha memperoleh keuntungan finansial, sementara petani kehilangan lahan garapan dan mengalami penurunan produktivitas. Dalam jangka panjang, kondisi ini mendorong perubahan struktur sosial desa, di mana generasi muda lebih memilih sektor pariwisata dibandingkan melanjutkan pekerjaan agraris. Hal ini berpotensi menimbulkan krisis regenerasi petani yang berdampak pada keberlangsungan sistem Subak. Selain itu, risiko budaya juga tidak bisa diabaikan. Subak sebagai praktik agraris sekaligus sistem sosial-religius merupakan inti pengakuan UNESCO terhadap Jatiluwih. Namun, tanpa RDTR, pembangunan kerap masuk ke zona-zona sensitif yang justru menjadi simbol identitas budaya.
Degradasi tata ruang tanpa kendali menyebabkan nilai-nilai kearifan lokal memudar, karena sawah yang semula menjadi ruang kolektif kini berubah menjadi komoditas wisata. Jika kondisi ini tidak diantisipasi, UNESCO berpotensi mencabut status Jatiluwih sebagai WBD, sebagaimana pernah terjadi di situs warisan lain di dunia yang gagal menjaga otentisitas dan integritas lanskapnya. Lebih jauh, OSS dalam situasi wilayah tanpa RDTR justru memperbesar risiko penyelewengan pemanfaatan ruang. Izin usaha dapat diterbitkan secara instan hanya dengan memenuhi persyaratan administratif, tanpa verifikasi kondisi lapangan. Inilah yang memunculkan fenomena “Legalitas semu”, yang mana izin usaha sah secara hukum, tetapi merusak substansi tata ruang. Dalam konteks Jatiluwih, kondisi ini membuka peluang besar bagi eksploitasi lahan pertanian demi kepentingan pariwisata. Tanpa instrumen zonasi yang ketat, pemerintah daerah kehilangan dasar hukum yang kuat untuk menolak pembangunan yang merugikan kawasan agraris. Risiko jangka panjang dari kekosongan RDTR sangat serius. Hilangnya keseimbangan ekologis Bali, meningkatnya kerentanan pangan akibat menyusutnya lahan sawah, serta terkikisnya identitas agraris yang selama ini menjadi daya tarik utama pariwisata, semuanya dapat terjadi bersamaan. Ironisnya, hal ini justru akan merugikan sektor pariwisata sendiri, karena wisatawan tidak lagi menemukan keunikan lanskap Subak yang lestari. Dengan kata lain, tanpa penyusunan RDTR yang segera dan berpihak pada perlindungan agraris, Jatiluwih menghadapi ancaman kehilangan bukan hanya lahannya, tetapi juga identitas kultural yang selama ini menjadi kebanggaan Bali di mata dunia.
OSS dan Ancaman terhadap Sistem Agraris Jatiluwih
Penerapan OSS sebagai sistem perizinan nasional menambah kompleksitas persoalan kekosongan RDTR. Secara prinsip, OSS membutuhkan dasar hukum tata ruang yang jelas untuk mengeluarkan izin usaha. Namun, tanpa RDTR, izin justru bisa terbit secara instan meskipun melanggar peruntukan ruang. Parikesit menuturkan, pada dasarnya sistem OSS merupakan hal yang baik dan layak didukung, tetapi penerapannya tetap harus disertai dengan pengendalian agar sesuai dengan aturan hukum. Pandangan ini menegaskan bahwa OSS merupakan instrumen positif untuk mendorong iklim investasi. Namun, efektivitasnya sangat ditentukan oleh keberadaan RDTR. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP No. 28 Tahun 2025), setiap kegiatan usaha wajib memperoleh Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebelum izin dapat diterbitkan. Jika wilayah telah memiliki RDTR digital yang terintegrasi dalam OSS, pelaku usaha otomatis mendapat Konfirmasi KKPR (KKKPR), sedangkan tanpa RDTR harus mengajukan Persetujuan KKPR (PKKPR) melalui verifikasi tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa RDTR menjadi instrumen kunci agar OSS berjalan cepat sekaligus tetap sesuai dengan peruntukan ruang. Dalam konteks agraria di Jatiluwih, ketiadaan RDTR berakibat fatal. Sawah-sawah produktif yang menjadi bagian integral dari sistem Subak rentan dialihfungsikan menjadi vila, restoran, atau akomodasi wisata melalui mekanisme OSS. Alih fungsi ini bukan hanya mengurangi luas lahan pertanian, tetapi juga mengancam hak agraria masyarakat adat Subak yang selama berabad-abad mengelola lahan secara kolektif dan berkeadilan. Subak sebagai sistem sosial-agraris tidak hanya berfungsi dalam pengaturan air, tetapi juga memelihara keseimbangan hubungan antara manusia, alam, dan spiritualitas sesuai dengan ajaran Tri Hita Karana
Dari perspektif hukum agraria, penerbitan izin usaha yang mengabaikan peruntukan sawah di Jatiluwih bertentangan dengan prinsip dasar dalam UUPA, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jika izin diberikan melalui OSS tanpa pengendalian RDTR, maka orientasi agraria bergeser dari keberlanjutan pangan dan kesejahteraan petani menjadi sekadar komoditas pariwisata. Konsekuensinya, izin usaha yang melanggar peruntukan agraris dapat dinilai cacat hukum, sebab bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP No. 28 Tahun 2025 yang menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha wajib sesuai dengan rencana tata ruang. Di sisi lain juga karena mengabaikan fungsi sosial tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPA. Kondisi ini dapat memicu konflik agraria antara masyarakat adat dengan investor, sekaligus membuka peluang gugatan maladministrasi ke Ombudsman atau pembatalan izin melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pada akhirnya, OSS yang dimaksudkan sebagai instrumen percepatan investasi justru berpotensi menjadi ancaman bagi keberlanjutan agraris Jatiluwih, yang selama ini menjadi basis identitas budaya Bali dan daya tarik utama pariwisata. Jika alih fungsi sawah terus berlangsung, maka tidak hanya keseimbangan pangan lokal yang terganggu, tetapi juga status Jatiluwih sebagai WBD terancam dicabut oleh UNESCO. Dengan demikian, OSS yang semula dimaksudkan sebagai instrumen percepatan investasi justru menjadi ancaman terbesar bagi sistem agraris tradisional Jatiluwih. Kontradiksi inilah yang menjadi dasar pentingnya melihat kembali RDTR sebagai benteng terakhir perlindungan Subak dan WBD.
Solusi
- Percepatan Penyusunan RDTR Jatiluwih
Pemerintah Kabupaten Tabanan wajib segera menyusun dan menetapkan RDTR sesuai Pasal 56 PP No. 21 Tahun 2021, dengan berpedoman pada Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021. RDTR ini harus dilengkapi peraturan zonasi yang mengatur secara rinci peruntukan ruang, termasuk perlindungan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan kawasan Warisan Budaya Dunia (WBD
- Integrasi RDTR dengan OSS Berbasis Risiko
RDTR yang sudah disahkan perlu segera diintegrasikan ke dalam sistem OSS Berbasis Risiko, sehingga setiap izin usaha dan bangunan otomatis diverifikasi berdasarkan kesesuaian zonasi. Hal ini sejalan dengan fungsi RDTR menurut Kementerian PUPR sebagai acuan operasional pemanfaatan ruang, pengendalian, pelaksanaan pembangunan, dan pemberian izin
Penutup
Realitas kekosongan RDTR di Desa Jatiluwih menunjukkan bahwa tata kelola ruang di kawasan warisan dunia ini masih rapuh. Tanpa arahan zonasi yang jelas, pembangunan akomodasi wisata terus menggerus sawah produktif yang menjadi inti sistem Subak. Penerapan OSS tanpa pengendalian mempercepat alih fungsi lahan, sehingga melemahkan hak agraria masyarakat adat dan mengganggu keseimbangan agraris yang telah bertahan berabad-abad. Kondisi ini menimbulkan risiko serius: hilangnya fungsi ekologis lahan pertanian, melemahnya ketahanan pangan lokal, munculnya konflik agraria antara masyarakat dengan investor, hingga ancaman pencabutan status Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO. Jatiluwih berada pada titik krusial antara mempertahankan identitasnya sebagai lanskap agraris berkelanjutan atau terjerumus ke dalam arus komodifikasi pariwisata. Dengan demikian, keberadaan RDTR bukan hanya soal dokumen teknis tata ruang, tetapi merupakan instrumen vital untuk menjaga keberlanjutan agraris, kedaulatan pangan, serta pelestarian nilai budaya Jatiluwih. RDTR berfungsi sebagai pedoman hukum yang memastikan setiap pembangunan berjalan selaras dengan fungsi ruang, sehingga sawah produktif tetap terlindungi, Subak tetap lestari, dan keseimbangan ekologis tidak terganggu. Lebih dari itu, RDTR juga menjadi wujud komitmen negara dalam menjamin hak-hak agraria masyarakat adat serta menempatkan pembangunan pariwisata dalam kerangka keberlanjutan. Tanpa langkah cepat, Jatiluwih berisiko kehilangan bukan hanya lahannya, tetapi juga identitas kolektif yang selama ini menjadi daya tarik dan kebanggaan Bali di mata dunia. Hilangnya lanskap Subak bukan hanya mengancam ketahanan pangan lokal, tetapi juga dapat mengguncang fondasi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Bali. Oleh sebab itu, RDTR harus dipahami sebagai benteng terakhir yang dapat menyeimbangkan kepentingan investasi dengan kewajiban pelestarian agraris dan budaya.
Daftar Pustaka
Atnews. (2025). Jatiluwih diakui UNESCO, 13 pelanggar tata ruang WBD belum ditindak tegas, warga: FPTR kok belum bersikap? Atnews. URL: Jatiluwih Diakui UNESCO, 13 Pelanggar Tata Ruang WBD Belum . (Diakses pada 9 Agustus)
Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2024). Perkembangan pariwisata Provinsi Bali April 2024. BPS Provinsi Bali. URL: Perkembangan Pariwisata Provinsi Bali April 2024 – Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (Diakses pada 5 Agustus)
Dayatri. (2022). Implementasi kebijakan Online Single Submission (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan, 1(5).
Diarta, I. P., & Sarjana, M. (2019). Strategi pengendalian alih fungsi lahan Subak, transformasi tenaga kerja, dan pembatasan tenaga kerja luar ke Subak. Agrimeta: Jurnal Pertanian Berkelanjutan, 23(3).
Iga Kusuma Yoni. (2025). DPRD Tabanan temukan 13 pelanggaran di kawasan LSD DTW Jatiluwih, ini datanya! Bali Express. URL: DPRD Tabanan Temukan 13 Pelanggaran di Kawasan LSD DTW Jatiluwih, Ini Datanya! – Bali Express (Diakses pada 9 Agustus)
Khiyaroh, E. W., & Taryono, I. (2017). Analisis kesesuaian perubahan penggunaan lahan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati tahun 2009–2017. Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota.
Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan pluralisme hukum dalam studi hukum adat: Interaksi hukum adat dengan hukum nasional dan internasional. Undang: Jurnal Hukum, 4(1), 81–124.
Sulaiman, K. F. (2021). Polemik fungsi sosial tanah dan hak menguasai negara pasca UU Nomor 12 Tahun 2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012. Jurnal Konstitusi, 18(1), 91–111.
Tarubali Baliprov (2024) Status TRTW dan RDTR di Provinsi Bali. URL : https://tarubali.baliprov.go.id/satus-rtrw-dan-rdtr-di-provinsi-bali. (Diakses pada 11 Agustus)
Widari, D. A. D. S. (2013). Perkembangan desa wisata Jatiluwih setelah UNESCO menetapkan Subaknya sebagai bagian dari Warisan Budaya Dunia. Jurnal Master Pariwisata (JUMPA), 1(1), 1–18. Universitas Udayana.
Penulis: Irene, Titis
Penyunting: Adi Dwipayana
Sumber foto: Balipremiumtrip.com