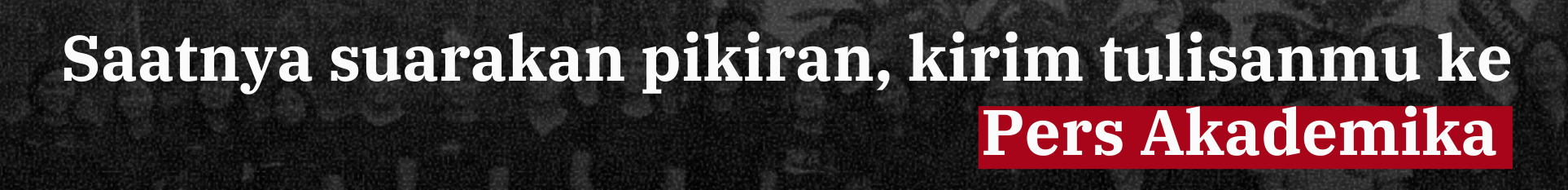Lumbung Padi di Ambang Senyap: Menyusutnya Regenerasi Petani di Desa Gadungan

Desa Gadungan di tanah Lumbung Padi Bali sedang mengalami krisis regenerasi petani di tengah lahan subur. Penghasilan yang tidak menentu serta banyaknya referensi pekerjaan di bidang lain menyebabkan potensi agraria tersebut kurang dilirik oleh generasi muda saat ini. Para pemangku kebijakan pun berupaya menyiapkan strategi dalam menanggulangi persoalan tersebut.
Pengantar
Kabupaten Tabanan dikenal sebagai daerah penghasil padi terbesar di Bali, dengan jumlah petani dan produksinya yang relatif stabil. “Lumbung Padi Bali” menjadi julukan yang cocok bagi Tabanan dengan karakteristik agrarisnya yang kuat. Namun di tengah reputasi tersebut, nyatanya beberapa tahun terakhir, muncul tren penurunan jumlah petani muda di Tabanan, salah satu di antaranya adalah Desa Gadungan. Hal tersebut didukung oleh fakta lapangan, bahwa hanya terdapat sedikit petani berusia 20-30 tahun di Desa Gadungan. Alih fungsi lahan serta kurangnya insentif petani dalam memaksimalkan lahannya membuat sektor ini semakin meredup. Penghasilan yang tidak menentu dan produktivitas yang terikat dengan pola musiman panen juga merupakan alasan menurunnya minat generasi muda untuk menjadi petani. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi kelangsungan peran Tabanan sebagai lumbung padi Bali.
Dikutip dari website Pemerintah Kabupaten Tabanan, daerah Tabanan memiliki topografi yang terletak di antara ketinggian 0–2.276 mdpl, dengan rincian pada ketinggian 0–500 mdpl yang merupakan wilayah datar dengan kemiringan 2–15%. Sedangkan pada ketinggian 500–1.000 mdpl merupakan wilayah datar sampai miring dengan kemiringan 15–40%. Daerah yang memiliki kemiringan 2–15% dan 15–40% merupakan daerah yang cukup subur untuk para petani melakukan kegiatan pertanian dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sebanyak 23.358 Ha atau 28,00% dari luas lahan yang ada di Kabupaten Tabanan merupakan lahan persawahan, sehingga Kabupaten Tabanan dikenal sebagai daerah agraris. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2010 menyatakan sekitar 43,96 persen penduduk angkatan kerja di Kabupaten Tabanan bekerja di sektor pertanian. Potensi agraris di Tabanan ini mampu memberikan peluang mata pencaharian bagi masyarakat. Dalam website antaranews.com, dinyatakan bahwa pendapatan rumah tangga usaha pertanian di Bali berdasarkan hasil sensus pertanian tahun 2013 rata-rata Rp35,61 juta per tahun atau Rp2,97 juta per bulan. Di sisi lain, menurut Suwinasih dkk. (2023), pendapatan petani Desa Gadungan masih sekitar Rp 15,4 juta per tahun untuk usaha tani kakao dan Rp 11,6 juta per tahun untuk usaha tani non-kakao. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa pendapatan petani di Desa Gadungan sekitar Rp2,25 juta. Hal tersebut masih terpaut jauh dari UMR Kabupaten Tabanan yang berkisar di angka Rp 3,1 juta per bulan.
Penurunan Minat Regenerasi Petani
Minat generasi muda di dunia pertanian menurun setiap tahun, diikuti oleh adanya pertumbuhan minat di bidang lainnya (Widyawati & Setyowati, 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian Salamah et al. (2021) bahwa nilai kontribusi angkatan kerja usia muda pertanian dari tahun 2014 hingga tahun 2019 cenderung mengalami penurunan. Terhitung sebanyak 12,6% generasi muda menganggap bertani adalah pekerjaan yang berat secara fisik dan tidak memberikan penghasilan yang cukup memadai. Generasi muda memiliki kecenderungan untuk tidak berminat bekerja pada sektor pertanian terutama menjadi seorang petani sebab kurang bergengsi dan kurang bisa memberikan jaminan untuk masa depan, terutama para generasi muda yang berasal dari pedesaan yang melihat realitas orang tua atau sekitar yang jauh dari kata mewah dan sukses sehingga orang tua tidak ingin hal tersebut terjadi di anaknya kelak di masa depan (Susilowati, 2016). Menurut narasumber petani setempat di Desa Gadungan, salah satu alasan anak muda enggan menjadi petani adalah faktor gengsi. Kurangnya kesadaran dari generasi milenial mengenai kondisi pertanian yang semakin memburuk yang pada akhirnya menyebabkan kurangnya minat terhadap pertanian di kalangan generasi milenial dan anak muda lainnya (KRKP, 2015). Di era gencarnya perkembangan teknologi sekarang, tidak dapat dipungkiri bahwa intensitas anak muda dalam beraktivitas di luar lapangan pun juga menurun drastis. Akibatnya, anak-anak muda menjadi semakin asing dengan pekerjaan lapangan seperti bertani. Di sisi lain, perkembangan zaman saat ini menumbuhkan berbagai pekerjaan yang menawarkan prospek lebih menjanjikan, seperti sektor pariwisata yang lebih diminati oleh anak-anak muda. Ditambah lagi, banyak anak muda yang pada dasarnya tidak memiliki niat untuk terjun di bidang pertanian dan lebih memilih bekerja sesuai dengan passion mereka. Kondisi ini semakin menyulitkan regenerasi petani, karena anak muda lebih memilih pekerjaan tetap yang dianggap lebih menjanjikan dan enggan beralih ke sektor pertanian.
Lahan Semakin Sempit
Mengutip dari website balitribune.co.id, setiap tahunnya alih fungsi lahan menjadi permukiman di Kabupaten Tabanan terus bertambah. Setiap tahun, rata-rata 53 hektare lahan pertanian berkurang sebab beralih fungsi menjadi permukiman. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Tabanan, I Gusti Putu Wiadnyana, menjelaskan bahwa alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Tabanan menjadi permukiman atau perubahan dalam satu tahun rata-rata 53,4 hektare atau 0,25% per tahun. “Berdasarkan data dari tahun 2011 sampai tahun 2017 rata-rata alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman sebesar 53,4 hektare,” jelasnya.
Diagram 1. Luas Lahan Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2011-2017
Sumber: balitribun.co.id
Data di atas menunjukkan adanya penurunan luas lahan pertanian di Kabupaten Tabanan setiap tahunnya. Kondisi lahan yang semakin sempit ini tentu berpengaruh pada hasil pertanian, sehingga menyebabkan anak muda yang memiliki lahan cenderung menganggap sektor pertanian sebagai prospek kerja di usia tua, bukan usia produktif. Lebih lanjut lagi, beberapa anak muda lebih memilih untuk menyewa tenaga dalam mengelola lahannya. Kondisi ini berpotensi menghambat regenerasi petani, karena sawah tetap dikelola oleh para petani yang sudah berusia lanjut. Luas lahan sawah yang dikelola petani di Desa Gadungan hanya sekitar 169 hektare atau rata-rata 37 hektare per kelompok, masih jauh di bawah standar kawasan pertanian pangan berkelanjutan, yaitu 500 hektare. Pendapatan petani akan meningkat dengan bertambahnya luas lahan, begitu pula sebaliknya. Jika luas lahan yang digunakan sempit, maka pendapatan petani juga akan turun. Oleh karena itu, terdapat korelasi positif antara pendapatan usaha tani dengan luas lahan (Dia, 2023). Pendapatan yang minim membuat para petani hanya mampu menutup biaya operasional, tanpa adanya keuntungan lebih.
Penyuluhan atau Sosialisasi
Penyuluhan atau sosialisasi yang bertujuan mengajak remaja atau anak muda untuk terjun ke bidang pertanian tergolong jarang, atau bahkan tidak pernah, dilakukan di Desa Gadungan. Saat ini dari desa setempat, yang baru dilakukan hanya sebatas uji coba konsep pertanian modern, tetapi belum pernah disebarluaskan ke masyarakat luas. Begitu pula, dari pihak dinas sendiri, mengaku cukup kelimpungan dalam melakukan sosialisasi akibat kurangnya tenaga yang tersedia, sehingga mengakibatkan sosialisasi terhambat dan tidak bisa dilakukan secara konsisten serta merata di semua daerah. Untuk sekitar 133 desa yang tersebar di Kabupaten Tabanan, hanya tersedia 40 orang penyuluh. Adanya selisih yang cukup besar antara penyuluh yang tersedia dengan penyuluh yang dibutuhkan di lapangan tentu mempersulit proses sosialisasi serta penyuluhan yang dilakukan. Kurangnya penyuluhan atau sosialisasi ini menimbulkan efek berantai bagi keberlanjutan populasi petani di Desa Gadungan. Kurangnya penyuluhan membuat sebagian petani tidak mengetahui perkembangan kebijakan, teknik, maupun teknologi terbaru. Akhirnya, efektivitas dan efisiensi pengelolaan lahan pun terhambat, dan pendapatan yang diperoleh pun berpotensi stagnan, atau bahkan menurun. Hal ini jelas berisiko semakin menurunkan daya tarik dari sektor pertanian bagi generasi muda, dan memperparah ancaman krisis regenerasi petani di masa depan. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kantor Desa Gadungan, baru sekitar 70% petani yang mampu dan mau melaksanakan PHT (Pengendalian Hama Terpadu). Padahal, PHT memegang peranan penting untuk meminimalisasi penggunaan pestisida sekaligus memanfaatkan musuh alami untuk memberantas hama tanaman. Pengendalian hayati yang memanfaatkan musuh alami seperti: parasitoid, predator dan patogen merupakan teknik pengendalian utama program PHT. Pelestarian dan pemanfaatan berbagai musuh alami yang banyak terdapat di pertanaman sawah merupakan hal utama yang perlu dikembangkan dan diterapkan di tingkat petani. Agar penggunaan musuh alami efektif, maka penggunaan pestisida berspektrum luas harus dihindari (Hasibuan dkk., 2017). Bahkan, lebih parah lagi, baru sekitar 55% petani yang bersedia menerapkan pola tanam 2:1 dan SRI. Berdasarkan data yang dihimpun dari Nugroho dkk. (2020), SRI dapat meningkatkan produktivitas lahan 100% di Madagaskar, 78% di Indonesia bagian timur khususnya Nusa Tenggara dan Sulawesi, 65% di Afghanistan, 42% di Irak, dan 11.3% di China. Peningkatan produktivitas dengan menerapkan metode budidaya SRI (System of Rice Intensification) menunjukkan jangkauan yang cukup luas, dipengaruhi oleh perbedaan iklim dan kondisi tanah pada suatu daerah tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho et al. (2018) juga turut menunjukkan terjadi peningkatan produktivitas dengan rata-rata 13% di Jawa Tengah. Produktivitas air dengan budidaya SRI (System of Rice Intensification) juga meningkat signifikan biasa sebagaimana dilaporkan peningkatan 28% di Jepang dan 40% di Indonesia bagian timur (Chapagain & Yamaji, 2010; Sato et al., 2011). Selain itu, budidaya SRI juga mampu mengurangi emisi gas rumah kaca seperti gas metana (CH4), N2O dan CO2 yang terjadi di lahan padi sawah, perlakuan irigasi berselang pada budidaya SRI dinilai dapat menurunkan emisi gas metana sampai sebesar 46.5% dan potensi Global Warming Potential (GWP) sampai sebesar 46.4%.
Nilai Tukar Petani (NTP)
Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar oleh petani. Secara konsep, NTP mengukur kemampuan tukar produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga petani dan barang atau jasa yang diperlukan dalam menghasilkan produk pertanian (Riyadh, 2015 dalam Aulia dkk., 2021). Oleh karenanya, NTP adalah salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan seorang petani. Ketika kondisi nilai tukar petani berada di atas angka 100 (NTP > 100) dan menunjukkan bahwa indeks harga yang diterima petani (It) lebih besar dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib), maka dapat dikatakan petani mengalami surplus dan lebih sejahtera. Apabila nilai tukar petani berada di bawah angka 100 (NTP < 100), artinya petani mengalami defisit dengan kenaikan harga produksinya lebih kecil. Sedangkan apabila nilai tukar petani sama dengan 100 (NTP = 100), artinya petani mengalami impas atau break even yaitu tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode waktu adalah tetap, dengan persentase kenaikan atau penurunan harga produksi sama dengan harga konsumsinya (BPS, 2011 dalam Aulia dkk., 2021). Berdasarkan penuturan dari I Made Subagia selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, daerah Tabanan belum memiliki sarana serta prasarana yang dibutuhkan untuk memproduksi data NTP secara mandiri, sehingga untuk saat ini, rilis data NTP Kabupaten Tabanan masih merujuk pada NTP Provinsi Bali. Berdasarkan data yang dihimpun dari BPS Provinsi Bali, terlihat pada data yang diperoleh hingga bulan Juni 2025, NTP Provinsi Bali cenderung berfluktuasi di antara 102 hingga 104 dan menyentuh nilai terendahnya di bulan Juni, yaitu 102,47. Meskipun terlihat cukup bagus, karena nilai yang berada di atas ambang batas 100, tetapi bila dibandingkan dengan NTP nasional, NTP Bali masih memiliki selisih yang cukup lebar. Hingga bulan Juni tahun 2025 sendiri, NTP Indonesia berfluktuasi di angka 121 hingga 123, dengan nilai terkecil yaitu 121,06 pada bulan April, dan nilai terbesar pada bulan Maret dengan nilai 123,72. Jarak yang cukup besar ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan petani di Bali masih belum dapat dimaksimalkan, setidaknya hingga menyamai standar nasional.
Tabel 1: Nilai Tukar Provinsi Bali Tahun 2025
| Nilai Indeks | Nilai Tukar Provinsi Bali | |||||
| 2025 | ||||||
| Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | |
| Indeks Diterima | 128,87 | 128,10 | 130,72 | 131,35 | 128,99 | 128,95 |
| Indeks Dibayar | 125,09 | 123,93 | 125,53 | 126,51 | 125,21 | 125,83 |
| Nilai Tukar Petani | 103,02 | 103,37 | 104,14 | 103,83 | 103,02 | 102,47 |
Sumber: BPS Provinsi Bali (2025)
Upaya Penyelesaian Permasalahan oleh Pemangku Kebijakan
- Dari pihak desa, terdapat rencana untuk mengadakan sosialisasi terkait teknik pertanian modern. Teknik pertanian tersebut merupakan teknik yang mengombinasikan pemanfaatan gabungan antara pertanian dan peternakan, dengan manajemen dan pengelolaan yang lebih modern. Artinya, ada pemanfaatan silang, antara hasil pertanian untuk peternakan, maupun hasil peternakan untuk pertanian. Konsep ini direncanakan untuk diintegrasikan dengan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Adanya KDMP juga membuat penyaluran bantuan modal bagi para petani yang kesulitan menjadi lebih mudah.
- Dari pihak dinas, solusi pertama yang sudah dijalankan adalah pemberian harga beli minimum kepada petani. Saat ini, harga beli minimum yang ditetapkan adalah sebesar Rp 5.000,00/kg. Adanya kebijakan ini membuat potensi permainan harga kepada para petani dapat dikurangi, dan petani bisa mendapat keuntungan yang lebih sesuai. Dinas pertanian juga telah melaksanakan sebuah sistem reposisi alat pertanian, yang berjalan dengan cara peminjaman atau penukaran alat-alat pertanian antara satu subak dengan subak lainnya. Program ini mengurangi potensi adanya alat pertanian yang menganggur dan memastikan semua alat pertanian dimanfaatkan dengan maksimal, dengan mengutamakan pemberian alat-alat pada subak yang membutuhkan. Juga, ada program Kontrak Tani Nelayan Andalan (KTNA), yang berisi relawan-relawan dari petani ataupun pekaseh yang sudah berpengalaman, untuk membantu memberikan bantuan berupa penyuluhan maupun implementasi teknologi kepada para petani. Selain itu, dinas berupaya memberikan jalan keluar atas permasalahan pendapatan petani yang kurang mencukupi. Menurut Made Subagia selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan sendiri, masih kerap ada petani yang kurang tepat dalam menyusun rancangan biaya pengelolaan lahan pertanian. Menurutnya, perlu dilakukan penyesuaian kembali antara biaya yang dikeluarkan dengan waktu aktual pengelolaan sawah. Dengan kata lain, perlu pemisahan antara waktu kerja di sawah dan kegiatan lainnya agar pengeluaran bisa lebih efisien. Terakhir, pihak dinas juga menyarankan para petani untuk bisa memprioritaskan penanaman buah ataupun sayuran yang zero waste, sehingga seluruh potensi buah tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal dan menyeluruh.
- Dari sisi anak muda, perlu dilakukan penyuluhan atau sosialisasi yang bukan hanya lebih gencar, tetapi lebih on-point kepada audiens Gen-Z. Contohnya, bisa dengan menggaet para influencer yang relevan dengan bidang pertanian. Selain itu, bisa juga dengan upaya perubahan mindset tentang profesi petani atau bidang pertanian ke arah yang lebih positif. Upaya ini bisa dilakukan dengan membuat anak-anak muda, atau bahkan anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah, merasa lebih familier dengan bidang pertanian. Contohnya, seperti mengutamakan penyebarluasan citra positif dari para petani di kalangan anak-anak, atau bahkan mengajak anak-anak itu untuk terjun langsung ke lahan pertanian.
Penutup
Fenomena menurunnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian di Tabanan, khususnya di Desa Gadungan, menunjukkan adanya tantangan besar dalam proses regenerasi petani. Meskipun didukung oleh kenyataan bahwa Tabanan merupakan salah satu daerah dengan potensi agraris terbaik di Bali, tetapi dengan pendapatan yang kurang stabil, luas lahan yang semakin menipis, gengsi dan lingkungan kerja yang semakin beraneka ragam, serta penyuluhan dan sosialisasi yang kurang, sektor pertanian menjadi semakin kurang menarik di mata anak-anak muda.
Tanpa respons dan solusi yang relevan dan memadai, kondisi ini berpotensi memburuk di masa mendatang. Oleh karenanya, terdapat beberapa upaya yang sudah dilakukan berbagai pihak yang terlibat untuk mengikis potensi dampak terburuk dari ancaman krisis regenerasi ini. Upaya yang telah dilakukan oleh pihak desa maupun dinas menunjukkan langkah awal yang menjanjikan. Namun demikian, langkah-langkah tersebut harus diiringi dengan strategi yang mampu menyentuh lebih dalam perspektif masyarakat awam secara keseluruhan, seperti membangun citra positif pertanian, melibatkan anak muda secara aktif, dan memperkuat pendidikan serta teknologi pertanian sejak usia dini. Regenerasi petani tidak hanya memastikan hadirnya petani-petani baru dalam jangka pendek, tetapi juga menjamin kesejahteraan mereka dalam jangka panjang.
Jika tidak ditangani secara serius dan konsisten, peran Tabanan sebagai lumbung agraria Bali bisa benar-benar lenyap. Oleh karena itu, momentum refleksi inilah yang harus dimanfaatkan untuk memaksimalkan kembali peran sektor pertanian di tengah tantangan zaman yang terus berkembang.
Daftar Pustaka
ANTARA Kantor Berita Indonesia. (2014, 19 Agustus). Pendapatan Petani di Bali Rp35,61 juta/tahun. Antaranews. https://www.antaranews.com/berita/449068/pendapatan-petani-di-bali-rp3561-juta-tahun
Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2025). Nilai Tukar Petani Provinsi Bali, 2025, dalam Nilai Tukar Petani Provinsi Bali – Tabel Statistik – Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Diakses pada 30 Juli 2025.
Dia, H. S., & Hamid, R. S. (2023). Peran Modal Kerja, Tenaga Kerja, Dan Luas Lahan Dalam Meningkatkan pendapatan petani. Jesya, 6(1), 479–491. https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.934
Hasibuan R., et al. (2017). SOSIALISASI ANALISIS AGROEKOSISTEM DALAM PENERAPAN PENGENDALIAN HAMA TERPADU (PHT) PADA TANAMAN JAGUNG.
Mardiyanti, E., Gunawan, G., & Hafizh, R. (2023). Persepsi Generasi Z Terhadap nbsnbProfesi Petani (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Pertanian, Universitas nfndbSultan Ageng Tirtayasa). Jurnal Ilmu Pertanian Tirtayasa, 5(2).
MEDIA INDONESIA. (2024, 24 September). Mengapa Generasi Muda Enggan Bertani? Tantangan dan Upaya Regenerasi di Sektor Pertanian Indonesia, dalam mediaindonesia.com. https://mediaindonesia.com/ekonomi/703577/mengapa-generasi-muda-enggan-bertani-tantangan-dan-upaya-regenerasi-di-sektor-pertanian-indonesia#goog_rewarded
Nawawi, F. A., Alfira, Z. N., & Anneja, A. S. (2022). Faktor penyebab nfmnketidaktertarikan generasi muda pada sektor pertanian serta penanganannya. ndfbjIn Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS) (Vol. 1, pp. 585-mnm593).
Pemerintah Kabupaten Tabanan. (2024, 29 Juli). Selayang Pandang. Tabanankab.go.id. https://tabanankab.go.id/home/mengenal-tabanan/selayang-pandang
Suwinasih, N. M., Dewi N. L., Dewi I. A. (2023). Kontribusi Usahatani Kakao ajdjjterhadap Pendapatan Petani (Studi Kasus Di Subak Abian Suci Desa vncnGadungan Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan). ISSN: 2685-jjjjjjj3809 Vol. 12, No. 2.
Syifa Aulia, S., Sulistiyo Rimbodo, D., & Ghafur Wibowo, M. (2021). Faktor Faktor Yang Memengaruhi Nilai Tukar Petani (NTP) di indonesia. JEBA (Journal of Economics and Business Aseanomics), 6(1), 44–59. https://doi.org/10.33476/j.e.b.a.v6i1.1925
Penulis: Ryan dan Ayu Parwati
Penyunting: Cahya
Sumber foto: Beritabali.com
kampung bet kampungbet kampungbet