Draft RUU Penyiaran: Kabut Kebebasan Berekspresi

Draft RUU Penyiaran tersorot,pasal-pasal kontroversial nan multitafsir termuat di dalamnya. Tumpang tindih kewenangan lembaga sampai larang siaran eksklusif jurnalistik investigasi seolah semakin menghimpit kerja jurnalis, lalu apa makna yang tersisa dari kemerdekaan pers?
Pengantar
Kini draft RUU Penyiaran tengah menuai atensi. Pasalnya di dalam RUU Penyiaran termuat beberapa pasal kontroversial dan terindikasi membatasi baik masyarakat maupun penggiat jurnalistik dalam memproduksi dan menayangkan konten siaran tertentu. Hal tersebut secara tidak langsung menekan pula kebebasan dalam berekspresi, padahal Indonesia sebagai negara demokrasi tidak dapat dipisahkan dari kebebasan berekspresi.
Konstitusi Indonesia secara tegas mengatur terkait kebebasan berekspresi melalui Pasal 28F, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Serta dalam Pasal 28 E ayat (3) yang berbunyi bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Pemaknaan ini berkorelasi dengan pendapat Toby Mendel yang menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi hal yang penting. Pertama, karena hak ini merupakan dasar demokrasi. Kedua, kebebasan dan berpendapat berekspresi berperan dalam pemberantasan korupsi. Ketiga, kebebasan berpendapat dan berekspresi mempromosikan akuntabilitas. Keempat, kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam masyarakat dipercaya merupakan cara terbaik menemukan kebenaran.
Kini kebebasan berekspresi yang telah dijamin konstitusi berusaha untuk dikebiri melalui draft RUU Penyiaran. Hal ini membuat banyak protes dan kritik digaungkan. Aksi protes dominan dilakukan oleh para jurnalis sebagai salah satu pihak yang paling terdampak jikalau draft RUU Penyiaran sah sebagai undang-undang. Di Malang pada (17/05/2024), ratusan jurnalis lintas organisasi seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Pewarta Foto Indonesia (PFI) berkumpul di Balai Kota Malang menggelar aksi demonstrasi. Aksi serupa juga dilakukan di Sumatera Utara pada (21/02/2024), sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Jurnalis Anti Pembungkaman berkumpul di DPRD Sumatera Utara. Aksi demonstrasi dilakukan di Kantor DPRD Provinsi Bali pada (28/05/2024) dengan massa aksi berasal dari organisasi jurnalis, perusahaan media, mahasiswa, serta organisasi dan individu prodemokrasi di Bali yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bali Tolak RUU Penyiaran (AMKARA).
Cikal Bakal draft RUU Penyiaran
Kemajuan teknologi informasi memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan khalayak umum. Fenomena globalisasi dan modernisasi seharusnya juga didukung oleh pembangunan hukum yang dapat mengakomodir kepentingan publik. Hukum Responsif dalam Teori Pembangunan Hukum Philippe Nonet dan Philip Selznick mengungkapkan bahwa suatu aturan perundang-undangan ada untuk menyejahterakan masyarakat. Aturan mengenai Penyiaran di Indonesia dipandang harus segera dilakukan pembaharuan sebab teknologi penyiaran meluas ke ruang digital. Urgensi ini hadir agar tercipta kepastian hukum bagi masyarakat yang bergerak sebagai penyelenggara penyiar maupun sebagai konsumen dari produk siaran. Menyikapi hal tersebut, Komisi I DPR RI melakukan serangkaian upaya pembaharuan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran).
Draft RUU Penyiaran pertama kali masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada periode 2009-2014 masa kerja DPR. Namun, dalam pembahasannya mengalami banyak penundaan, salah satunya karena pembahasan definisi penyiaran masuk ke dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Kemudian, sampai berakhirnya masa kerja DPR periode 2009-2014, pembahasan hanya sampai pada DIM ke-40 dari 865 DIM RUU Penyiaran yang berarti bahwa pembahasan RUU belum masuk ke substansi RUU melainkan hanya pada tahap definisi (Herman & Udi, 2020). Kemudian, dalam perkembangannya, Draft RUU Penyiaran kembali dimasukkan dalam Prolegnas 2014-2019 sebagai pembahasan utama. Akan tetapi, hingga berakhirnya masa kerja DPR 2014-2019, draft RUU penyiaran belum mendapat hasil harmonisasi dan pemantapan konsep oleh fraksi di DPR. Selanjutnya, draft RUU Penyiaran kembali dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas dalam periode 2019-2024 masa kerja DPR dan dicanangkan akan selesai di tahun 2024 (Nesya & Rio, 2020).
Upaya pembaharuan Undang-Undang Penyiaran timbul karena perlunya penyesuaian terhadap keadaan saat ini. Adapun beberapa penyesuaian berkaitan akan eksistensi dari KPI. Berbagai pendapat mengenai kewenangan KPI berkembang di masyarakat. Sebagian memandang KPI sebagai lembaga yang bertugas dalam hal isi siaran saja, sebagian berpandangan bahwa KPI seharusnya menjadi legislator dalam bidang penyiaran. Ini kemudian menyebabkan ketidakjelasan wewenang yang dimiliki oleh KPI (Denico Doly, 2016). Selain itu, sudah tidak relevannya lagi peraturan yang mengatur terkait penyiaran tersebut membuat perlu dilakukannya pembaharuan hukum. Namun, perlu diingat juga baik dalam pembentukan maupun pembaharuan hukum harus dilandasi dengan prinsip yang baik serta bermanfaat bagi masyarakat yang akan terdampak dari keberlakuan peraturan tersebut.
Sebagaimana dijelaskan oleh DPR dan Pemerintah melalui Naskah Akademik Draft RUU Penyiaran adalah sebagai berikut:
- Secara teknik perancangan undang-undang (legal drafting) sudah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Terdapat ketentuan-ketentuan dalam UU Penyiaran saat ini yang bersifat multitafsir antara lain mengenai:
a. Kewenangan KPI dan pelaksanaan sistem stasiun jaringan yang disusun oleh KPI bersama Pemerintah. Walaupun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi akhirnya kewenangan tersebut dilakukan oleh Pemerintah;
b. Ketegasan kepada lembaga penyiaran swasta untuk berjaringan
c.Terdapat ketentuan yang tidak sinkron dengan UU lainnya antara lain mengenai kepemilikan silang antara lembaga penyiaran swasta yang tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; - Substansi UU Penyiaran sudah tidak dapat mengantisipasi perkembangan kemajuan teknologi di bidang penyiaran terutama terkait dengan perubahan sistem penyiaran analog menjadi sistem penyiaran digital (teknologi digitalisasi penyiaran).
Seperti yang tertuang dalam Naskah Akademik draft RUU Penyiaran, hadirnya UU Penyiaran bertujuan untuk menjawab tantangan komunikasi dan informasi yang sekarang tengah berkembang menuju era digitalisasi. Di sisi lain, undang-undang harus memberikan kepastian hukum dan ketertiban berkaitan dengan pertumbuhan serta perkembangan lembaga-lembaga penyiaran. Namun, dalam proses perancangannya, seyogyanya para legislator harus memperhatikan pula prinsip dari pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (UU No. 12/2011). Pasal tersebut menyatakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:
a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.
Ketujuh asas tersebut harus dimaknai benar dan digunakan oleh legislator sebagai acuan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Jika salah satu saja tidak terpenuhi membuat produk hukum menjadi cacat dalam pembentukannya, baik secara formil maupun materiil.
Adapun makna dari setiap asas tersebut yaitu: Pertama, Asas Kejelasan Tujuan mengharuskan setiap pembentukan peraturan perundang-undangan mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai. Kedua, Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat berkaitan dengan kewenangan lembaga legislatif dalam membentuk peraturan perundang-undangan maupun kewenangan eksekutif dalam membuat produk perundang-undangan yang diamanatkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan yang mana dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan serta menyesuaikan dengan materi muatan dari jenis dan hierarki peraturan perundang undangan tersebut. Keempat, Asas dapat dilaksanakan, asas ini berkaitan dengan keefektivitasan suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk, dimana harus efektif di masyarakat, baik dari segi sosial, filosofis hingga yuridis. Kelima, Asas Kedayagunaan dan kehasilgunaan yang artinya asas ini mengamanatkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus bermanfaat dan harus dibutuhkan oleh masyarakat. Keenam, Asas Kejelasan rumusan yang artinya pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan teknis penyusunan, sistematika dan pemilihan kata agar dikemudian hari setelah disahkan tidak menimbulkan spekulasi dan multitafsir dalam pelaksanaannya. Ketujuh, Asas Keterbukaan yang berarti dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus terbuka sehingga memberikan kesempatan masyarakat untuk turut berpartisipasi di dalamnya (Ricky & Maharani, 2023).
Asas-asas dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 merupakan hal yang perlu terpenuhi supaya produk hukum menghadirkan suasana yang demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta meminimalisir tindakan represif dari penguasa kepada rakyat. Dalam nuansa yang demokratis memang sudah sewajarnya pembentukan peraturan perundang undangan dilakukan secara demokratis pula dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, dari segala golongan dan profesi, terutama kelompok masyarakat yang berprofesi rentan akan pembungkaman atas ditetapkannya peraturan perundang undangan terkait. Hal ini tentu sejalan dengan tuntutan negara hukum yang awalnya ditujukan untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang dan melindungi hak-hak masyarakat (Salahudin T. S., 2020).
Pasal Kontroversial Dalam Draft RUU Penyiaran
Terlepas motivasi disusunnya draft RUU Penyiaran demi memberikan kepastian hukum, draft tersebut banyak menuai kecaman publik. Adapun pasal-pasal dalam draft RUU Penyiaran yang problematik dan terindikasi mengancam kebebasan pers dan masyarakat adalah sebagai berikut:
Pasal-pasal dalam draft RUU Penyiaran sebagaimana disebutkan di atas memiliki potensi dalam membungkam publik ketika berekspresi. Pers sebagai pilar keempat demokrasi sudah seharusnya memiliki kebebasan dalam menyuarakan kebenaran kepada masyarakat. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pers menjelaskan terhadap Pers Nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Mengacu pada bunyi pasal tersebut, keberadaan Pers di Indonesia tidak terlepas dari teori libertarian John Milton. Kebebasan Pers dalam teori libertarian mengharuskan pers bebas dari hegemoni pemerintah dan bergerak sebagai fourth estate. Dalam hal ini, pers memiliki kebebasan yang seluas-luasnya untuk membantu manusia menemukan kebenaran yang hakiki serta menggali kebenaran-kebenaran lainnya yang disembunyikan oleh penguasa serta sekaligus menjadi penghubung antara masyarakat dengan penyusun kebijakan (Venezia I. G., & Praptining S., 2016). Pers harus diberi tempat yang sebebas-bebasnya, untuk membantu mencari kebenaran. Kebenaran akan diperoleh jika pers diberi kebebasan, sehingga kebebasan pers menjadi tolak ukur dihormatinya hak bebas yang dimiliki manusia (dalam Nurudin, 2004 :72-73). Jika dihubungkan dengan kondisi pers di Indonesia saat ini, maka belum didapatkannya kondisi yang ideal terhadap kebebasan pers. Muatan pasal-pasal yang bermasalah dalam draft RUU Penyiaran dapat mengindikasikan akan dikekangnya kebebasan dari pilar keempat demokrasi.
Selain Pers, pegiat media sosial juga terancam dibungkam hak kebebasannya. Melalui perluasan definisi Penyiaran dalam draft RUU Penyiaran yang saat ini mulai mencakup wilayah penyiaran digital, konten kreator dan produser film terancam dibatasi dalam berkreasi. Perluasan norma yang terdapat dalam definisi Penyiaran pada Pasal 1 angka 2 draft RUU Penyiaran menjadi akar dari diaturnya juga konten-konten dalam platform digital layanan Over The Top (OTT) dan User Generated Content (UGC) oleh UU Penyiaran baru nantinya. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 3 Tahun 2016, Over The Top (OTT) didefinisikan sebagai penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet yang tengah berkembang dalam kehidupan masyarakat luas seperti, layanan aplikasi massaging (Whatsapp, Telegram), layanan sosial media (Instagram, Facebook), layanan audio dan video streaming (Netflix, Youtube) serta layanan video calling dan video chatting (Skype, Zoom). Sementara itu, User Generated Content (UGC) didefinisikan sebagai segala konten yang dibuat oleh user dalam platform media seperti Youtube, Instagram, Tiktok, dan lain-lain yang tujuannya untuk memberikan review, feedback, studi kasus, atau segala postingan dalam media sosial yang bertujuan untuk menganalisa suatu objek dan/atau fenomena. Permasalahan yang timbul adalah draft RUU Penyiaran mengatur terkait ketentuan-ketentuan terkait isi dan konten siaran, baik terhadap media konvensional maupun platform digital, sedangkan aturan mengenai penyiaran tidak seharusnya disamakan dengan platform digital karena antar dua hal tersebut berbeda. Platform digital cakupannya sangat luas serta tidak terbatas pada frekuensi. Dengan demikian, disamakannya pengaturan terhadap isi dan konten dalam penyiaran konvensional dengan platform digital akan menimbulkan suatu masalah bagi pegiat media sosial dalam berekspresi dan berkreasi mengingat aturan penyiaran media konvensional sangat ketat (Berita KBR, 2024).
Tumpang Tindih Kewenangan Dewan Pers dan KPI
Draft RUU Penyiaran yang sekarang dalam tahap harmonisasi di Baleg juga memiliki indikasi yang kuat terhadap ketidakpastian hukum. Pasalnya, terdapat tumpang tindih dalam upaya penyelesaian sengketa dalam ranah pers. Dewan Pers memiliki fungsi untuk mengupayakan penyelesaian kasus atau sengketa dalam lingkup kegiatan pers atau jurnalistik. Hal ini jelas termuat dalam batang tubuh Undang-Undang Pers.
Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Pers menyatakan sebagai berikut:
“(2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.”
Dengan penyelesaian sengketa pers yang berlandaskan UU Pers, maka sudah seharusnya juga jurnalis maupun komunitas atau organisasi pers dalam hal pelarangan hanya tunduk pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Belakangan ini, indikasi tumpang tindih upaya penyelesaian terhadap sengketa pers menuai sorotan. Masalahnya, di dalam draft RUU Penyiaran juga mengatur upaya penyelesaian sengketa pers yang mana menjadi wewenang dari KPI. Adapun pasal yang mengatur hal tersebut yaitu:
Pasal 8A ayat (1) huruf q:
“(1) KPI dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), berwenang:
q. menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang Penyiaran.”
Implikasi diaturnya upaya penyelesaian sengketa jurnalis atau pers di dalam draft RUU Penyiaran selain menimbulkan tumpang tindih aturan hukum, juga akan dapat berakibat pada sengketa pers diadili di pengadilan biasa dengan tunduk pada proses beracara dan aturan yang lebih ketat. Dengan demikian, sengketa pers di bidang penyiaran tidak akan diadili melalui mekanisme etik melainkan lewat mekanisme hukum. Selain itu juga, penyelesaian sengketa jurnalistik melalui KPI berpotensi mengintervensi kerja-kerja jurnalistik. Ini membuat kewenangan dan independensi dari Dewan Pers digerogoti.
Adanya dua aturan yang mengatur terkait penyelesaian sengketa pers telah mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum di masyarakat. Padahal seharusnya tujuan dari adanya suatu aturan adalah menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat yang mana dengan kepastian hukum nantinya akan mencegah adanya tumpah tindih terhadap esensi atau substansi peraturan perundang undangan (Walim, 2020). Namun, dalam kondisi sekarang justru yang terjadi adalah sebaliknya, muatan pasal-pasal dalam draft RUU Penyiaran ini rawan konflik dan memiliki indikasi yang kuat terhadap ancaman dari kebebasan pers, baik dalam mengungkapkan kebenaran maupun dalam penyelesaian terhadap sengketa jurnalistik.
Dibatasinya Siaran Eksklusif Jurnalistik Investigasi
Jurnalistik Investigasi merupakan aktivitas mengumpulkan menulis, mengedit, dan menerbitkan berita yang bersifat investigatif, atau sebuah penelusuran panjang dan mendalam terhadap sebuah kasus yang dianggap memiliki kejanggalan. Kegiatan jurnalistik investigasi memiliki bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan kasus-kasus kejahatan yang terjadi dalam negeri, kemudian dipublikasikan kepada masyarakat luas sehingga dapat mengungkap fakta-fakta yang sengaja disembunyikan oleh pihak-pihak tertentu (Syahrianti S., 2022). Adapun hal yang membedakan jurnalistik investigasi dengan produk pers lainnya dapat dilihat dari kemampuan menyampaikan persoalan secara komprehensif dan kontekstual, serta menyampaikan isi yang relevansi dan pengaruhnya sangat kuat dengan masyarakat.
Di Indonesia, organisasi pers dan komunitas jurnalistik nasional mempunyai landasan hukum dalam melakukan kegiatan jurnalistik investigasi. Pasal 28F Undang-Undang NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Sementara itu, pengaturan khusus terhadap pers dapat juga dilihat dari UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, terkhusus pada pasal 4 yang menyebutkan beberapa hal sebagai berikut:
Pasal 4 UU No. 40 Tahun 1999:
(1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
(2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
(3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
Dengan adanya landasan hukum ini, pers seharusnya memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan jurnalistik, terutama hal-hal yang menyangkut kepentingan khalayak ramai. Peran dari kerja pers melalui jurnalistik investigasi dapat dilihat dari kasus-kasus yang kemudian dapat terungkap ke permukaan, seperti kasus penembakan anggota front pembela islam yang berhasil diungkap dalam Majalah Tempo (Arvin, et.al., 2021). Selanjutnya, Media Tempo melalui jurnalistik investigasi juga telah berhasil mengungkap kasus perbudakan anak buah kapal (ABK) Indonesia di kapal-kapal ikan Taiwan (Mustafa M., 2017). Dengan berhasil terungkapnya kasus-kasus yang sebelumnya disembunyikan kebenarannya kepada publik, membuktikan bahwa kinerja dari pers melalui jurnalistik investigasi merupakan hal yang sangat penting dan membawa dampak yang besar. Selain itu juga, kerja jurnalis melalui jurnalistik investigasi telah banyak mendatangkan manfaat kepada masyarakat luas seperti membongkar praktik-praktik ketidakadilan, mengungkap eksploitasi lingkungan, mempermalukan perusahaan, mengungkap manipulasi hukum, serta menjatuhkan pemerintahan yang korup (Ignatius H., 2024).
Namun, tidak semua orang merasa diuntungkan dengan tereksposnya kebenaran ke permukaan. Beberapa orang (oknum) merasa dirugikan dengan diungkapkannya fakta-fakta tersebut kepada publik. Pers yang merupakan lembaga independen, gencar mengungkapkan praktik-praktik kejahatan yang merugikan masyarakat melalui produk-produk jurnalistik. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk membungkam pers tidak jarang dilakukan dalam praktiknya di Indonesia. Upaya pembungkaman terhadap pers semakin terlihat terang-terangan sekarang. Muatan pasal dalam draft RUU Penyiaran yang mengatur terkait larangan penyiaran eksklusif jurnalistik investigasi cenderung dipandang oleh sebagian orang sebagai alat politik kekuasaan untuk membungkam kebebasan pers di Indonesia. Adapun muatan pasal tersebut menyatakan sebagai berikut:
Pasal 50B ayat (2) huruf c:
“(2) Selain memuat panduan kelayakan Isi Siaran dan Konten Siaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), SIS memuat larangan mengenai:
…. c. penayangan eksklusif jurnalistik investigasi.”
Adanya larangan terhadap siaran eksklusif jurnalistik investigasi membuat pers kehilangan fungsinya dalam mengungkapkan praktik kejahatan yang tersebar di masyarakat. Menurut Sekretaris Jenderal Analisis Jurnalisme Independen, Bayu Wardana, pasal yang mengatur terkait larangan terhadap siaran eksklusif jurnalistik investigasi merupakan pasal yang dapat membungkam kebebasan pers di Indonesia. Pasalnya, jurnalistik investigasi merupakan marwah dari pers dalam meneliti serta mengungkapkan kebenaran-kebenaran yang tersembunyi atau disembunyikan oleh pemegang kekuasan kepada masyarakat. Dilarangnya tayangan eksklusif jurnalistik investigasi membuat pers selaku pilar keempat demokrasi tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal.
Begitu pentingnya peran jurnalistik investigasi di Indonesia, sehingga tidak benar jika dikatakan bahwa kegiatan jurnalistik investigasi akan menghalangi penyelidikan kepolisian. Sebaliknya, kegiatan jurnalistik investigasi justru membantu kepolisian lebih cepat dalam mengungkapkan kebenaran terhadap kasus-kasus yang telah lama tertimbun tanpa kejelasan. Dengan begitu, apabila terdapat larangan untuk menyiarkan konten eksklusif jurnalistik investigasi ini akan berakibat pada tidak adanya lagi konten jurnalis yang dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang komprehensif serta mendalam kepada masyarakat, dan juga membuat berkurangnya cara yang dapat dilakukan oleh pers untuk mengungkap tabir kebenaran kepada masyarakat.
Indikasi Terancamnya Kebebasan Berekspresi dan Kreativitas Publik di Ruang Digital
Banyak orang terkhusus pengguna media sosial mengekspresikan dirinya melalui ruang digital. Berdasarkan data We Are Social, tercatat per-Januari 2024 terdapat 139 juta pengguna media sosial di Indonesia atau setara 49,9% dari total populasi nasional (Cindy M. A., 2024). Dengan jumlah yang begitu banyak tersebut, dampak yang ditimbulkan akan sangat besar apabila terdapat pengaturan hukum yang kurang jelas dan terkesan mengekang publik dalam menyalurkan ekspresinya. Berdasarkan laporan dari Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), selama tahun 2023 di Indonesia terdapat peningkatan tren kriminalisasi terhadap ekspresi di ranah digital jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang mana meningkat sebesar 15,9% dengan jumlah total 124 orang yang dilaporkan ke kepolisian. Mengutip dari pernyataan Ketua Komnas HAM, Dr. Atnike Nova Sigiro (2024) yang mengatakan bahwa fenomena demikian dikarenakan regulasi yang ada (UU ITE) sering terkendala perbedaan interpretasi dan juga dapat diskriminatif. Oleh karena itu, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi seharusnya tidak boleh sewenang-wenang atau semaunya (SAFEnet, 2024). Mengacu pada hal tersebut, regulasi yang bermasalah dapat menjadi faktor dari terancamnya kebebasan berekspresi. Kemudian, makin ke sini peningkatan terhadap tren kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital akan dapat terus meningkat apalagi dengan sekarang adanya beberapa muatan pasal yang bermasalah dan kontroversial dalam draft RUU Penyiaran yang dapat mengekang kebebasan pengguna layanan platform digital dalam berekspresi maupun dalam memproduksi konten siaran di ruang digital.
Perluasan definisi penyiaran yang awalnya hanya mencakup media konvensional, lalu sekarang meluas ke lingkup media digital atau internet membuat pengaturan terhadap isi dan konten siaran dalam ruang digital baik platform layanan over the top (OTT) maupun user generated content (UGC) harus tunduk pada peraturan yang termuat dalam Standar Isi Siaran (SIS). Draft RUU Penyiaran yang memuat SIS menuai banyak kecaman publik sebab beberapa muatan pasal dalam SIS terkesan membatasi ruang berekspresi pegiat media sosial maupun pengguna platform layanan digital dalam memproduksi konten-konten siaran. Adanya pelarangan terhadap konten-konten yang mengandung unsur mistik, supranatural, aksi kekerasan, rokok, dan alkohol menimbulkan kerancuan serta kebingungan karena tidak jelas maksud dari pasal tersebut ditujukan terhadap siapa. Mengingat juga Pasal 50B ayat (2) huruf k terdapat pengaturan terhadap larangan penayangan Isi Siaran dan Konten Siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik dan lain sebagainya, yang mana ini menimbulkan kebingungan karena tidak jelas tolak ukur yang digunakan dalam pengenaan pasal tersebut.
Penutup
Di negara demokrasi, rakyat memiliki hak untuk mengetahui segala hal mengenai dirinya dan kejadian-kejadian di sekitarnya (the right to know) yang juga berarti hak untuk memperoleh informasi yang lengkap dan cermat (the right to information). Sementara itu, sarana untuk mendapatkan informasi itu adalah melalui produk dari kegiatan jurnalistik dan berbagai informasi dalam layanan platform digital. Draft RUU Penyiaran yang sedang digodok oleh DPR saat ini berpotensi memperburuk kebebasan berekspresi dari lembaga pers yang merupakan salah satu pilar utama demokrasi.
Selain itu, pasal-pasal yang mengatur terkait sanksi atau larangan terhadap isi dan konten siaran juga memiliki indikasi yang kuat dalam membatasi atau membungkam kreativitas masyarakat di ruang digital. Dengan demikian, ruang informasi publik akan hampa dan steril dari laporan mendalam yang membongkar kesewenang-wenangan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Tidak hanya itu, draft RUU Penyiaran akan menjadi alat kekuasaan serta politik oleh pihak tertentu untuk mengebiri kerja-kerja jurnalistik yang profesional dan berkualitas. Implikasi dari draft RUU Penyiaran adalah turut menimbulkan pertentangan dan kekaburan norma sebab di dalamnya memuat beberapa ketentuan yang problematik dan mengancam kebebasan pers serta kebebasan informasi.
Penulis: Adi Dwipayana, Dian Purnami, Sinta Dewi, Ayu Made Nopri Yanti, Danisha Vanya Yusuf, Cahya, Cyn
Ilustrator: Utari
Daftar Pustaka
Annur, C. M. (2024) Ini Media Sosial Paling Banyak Digunakan di Indonesia Awal 2024. URL: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/01/ini-media-sosial-paling-banyak-digunakan-di-indonesia-awal-2024. Diakses pada 27 Mei 2024.
Berita KBR. (2024).Talk Show Ruang Publik KBR-Mengulik Pasal Bermasalah di RUU Penyiaran. URL: https://www.youtube.com/watch?v=CiNYE9o7CB8. Diakses pada 23 Mei 2024.
Doly, D. (2016). Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan , 4 (2), 215-230.
Ghassani, VI, & Sukowati, P. (2016). Bentuk Hubungan Pers Dengan Pemerintah Terkait Dengan Fungsi Media Sebagai Kontrol Sosial. Publikasi: Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 1 (2). Hlm. 172-180.
Handriana, R., & Nurdin, M. (2023). Analisis Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 6(1), 142
Hardian, A., dkk. (2021). Konstruksi Jurnalistik Investigasi Dalam Perspektif Analisis Wacana Model Teun A. Van Dijk (Sebuah Studi Kasus Penembakan Laskar Front Pembela Islam Di Majalah Tempo). Cakrawala-Jurnal Humaniora Dan Sosial, 21(1).
Haryanto, I. (2024). Sebab Jurnalisme Investigasi Harus Tetap Ada. URL: https://koran.tempo.co/read/opini/488595/apa-manfaat-jurnalisme-investigasi. Diakses pada 27 Mei 2024.
Herman, H., & Rusadi, U. (2020). Dualitas struktur di balik RUU Penyiaran. Jurnal Riset Komunikasi, 3(2), 210-223.
Moses, M. (2017). Cerita di Balik Investigasi Budak Indonesia di Kapal Taiwan. URL: https://nasional.tempo.co/read/834384/cerita-di-balik-investigasi-budak-indonesia-di-kapal-taiwan. Diakses pada 27 Mei 2024.
Nurudin. 2004. Sistem Komunikasi Indonesia, Jakarta; Rajawali Press.
SAFEnet. (2024). [Siaran Pers] SAFEnet: Pemilu 2024 Memperburuk Situasi Hak-hak Digital selama 2023. URL: https://safenet.or.id/id/2024/02/siaran-pers-safenet-pemilu-2024-memperburuk-situasi-hak-hak-digital-selama-2023/. Diakses pada 27 Mei 2024.
Seta, S. T. (2020). Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Legislasi Indonesia, 17(2), 154-166
Syam, S. (2022). Jurnalisme Investigasi: Elemen, Prinsip, dan Teknik Reportase. Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan, 8(2), 127-137.
Tania, N. (2020). The Urgency of Amendment to Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting as the Legal Umbrella for OTT Services. 108-122
Walim, W. (2020). Harmonisasi Undang-Undang Penemuan Informasi Publik (UU Pers dan UU Penyiaran). Wiralodra Gema, 11 (2), 250-264.

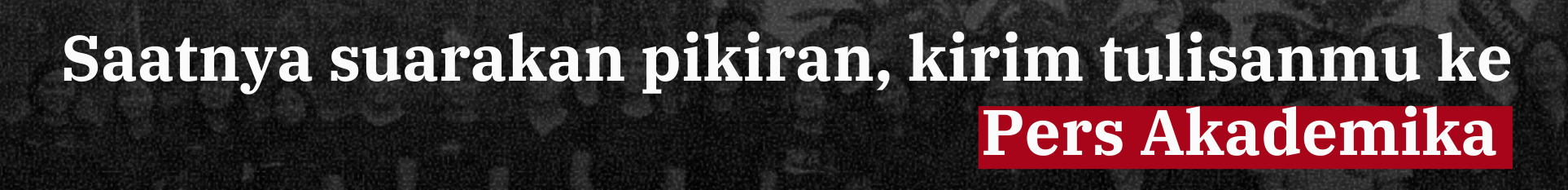


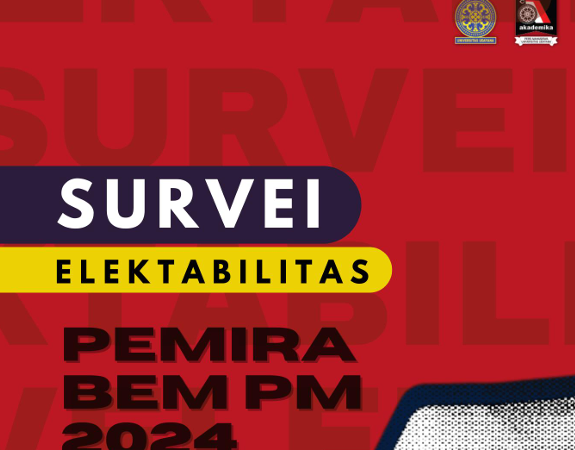


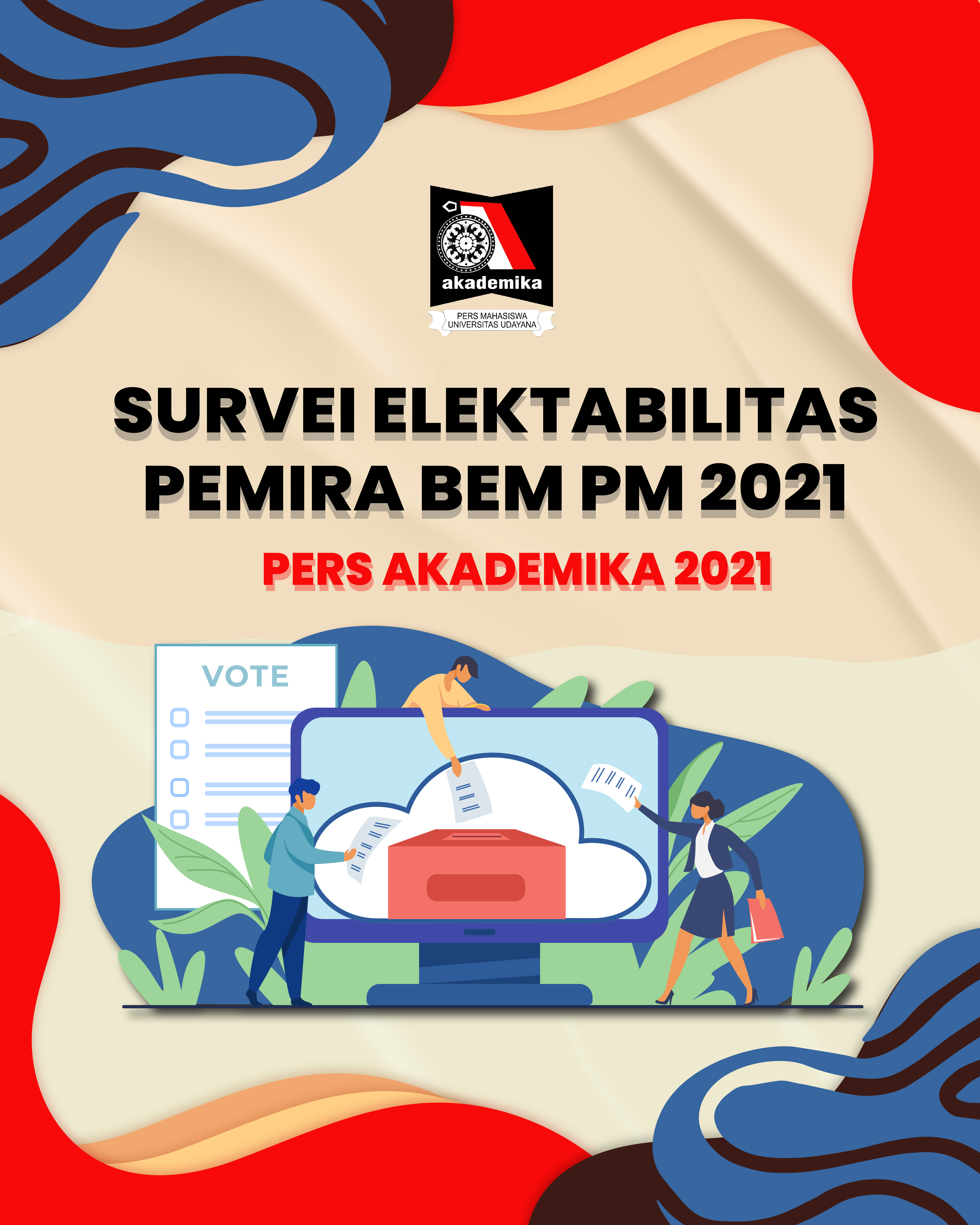

7bqlq7