Enggan Diam Tanpa Peran: Sinergi Masyarakat Desa Adat Kedonganan Kembangkan Potensi Wisata

“Tidak mau menjadi penonton di tanah sendiri”. Itulah tekad yang timbul di benak masyarakat lokal Desa Adat Kedonganan yang khawatir dengan tanah kelahirannya. Tidak mau diam berpangku tangan, masyarakat Kedonganan mampu bersinergi menjadi pelaku utama dalam penyelenggaraan pariwisata. Tanpa memarginalkan aspek sosial di lingkungan komunitas, bagaimana Kedonganan berdikari menyelenggarakan aktivitas wisata berbasis masyarakat?
1.Pengantar
Industri pariwisata telah menjadi lokomotif penggerak perekonomian Bali selama ini, utamanya Kabupaten Badung yang mendorong sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan dalam menggenjot perekonomian. Disokong sumber daya alam dan kearifan lokal masyarakatnya yang terpelihara di tengah turisme massal, membuat sektor wisata di Bali memiliki daya pikat tersendiri, hal ini tidak lepas dari harmonisasi antara manusia, alam, dan aktivitas spiritual masyarakat lokal yang menunjukan bagaimana peradaban Hindu di Bali benar-benar hidup. Lekatnya hubungan antara kehidupan masyarakat Bali dan pariwisata tersebut merangsang stakeholders terkait untuk terus berupaya mengembangkan segala potensi sumber daya yang dimiliki. Dengan kata lain, penyelenggaraan aktivitas wisata berbasis masyarakat menjadi poin penting bagi keberlanjutan sebuah destinasi wisata. Disarikan dari Jurnal Pariwisata Budaya berjudul Community Based Tourism Dalam Pengembangan Pariwisata Bali oleh I Wayan Wiwin, upaya tersebut tercermin dari gerakan-gerakan swadaya masyarakat untuk membangun dan mengembangkan potensi wisata di daerahnya masing-masing, mulai dari kepemilikan (ownership) sumber daya pariwisata, pengelolaan (management), dan kontrol (control). Gerakan ini sealir dengan konsep pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat atau dikenal dengan istilah Community Based Tourism (CBT).
Konsep ini menunjukan bahwa elemen masyarakat merupakan bagian penting dari sebuah atraksi wisata sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari upaya pembangunan industri wisata yang berkelanjutan. Dikutip dari Jurnal Ilmiah Hospitality Management berjudul Community Based Tourism (CBT) sebagai Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di DTW Ceking Desa Pakraman Tegallalang oleh Wijaya dan Sudawarman, konsep CBT menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan pariwisata sehingga kemanfaatan kepariwisataan sebesar-besarnya diperuntukan bagi masyarakat. Community Based Tourism berfokus pada peningkatan kesejahteraan tanpa memarginalkan aspek sosial di dalamnya. Lebih lanjut, menurut Rest (1997), CBT adalah wisata yang memperhatikan lingkungan, sosial masyarakat, dan kesinambungan budaya dalam satu fokus pengembangan. CBT dikelola dan dimiliki dari dan oleh masyarakat dengan tujuan memberikan pengalaman bagi wisatawan untuk merasakan kearifan lokal dan lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari komunitas.
Adapun CBT ditunjang oleh berbagai prinsip yang digunakan sebagai tools community development bagi masyarakat lokal. Dikutip dari Syafiqah (2022), menurut United Nation Environment Programme dan WTO (2005), Community Based Tourism memiliki prinsip dasar yakni: 1) mengakui, mendukung dan mengembangkan kepemilikan komunitas dalam industri pariwisata; 2) mengikutsertakan anggota komunitas dalam memulai setiap aspek; 3) mengembangkan kebanggaan komunitas; 4) mengembangkan kualitas hidup komunitas; 5) menjamin keberlanjutan lingkungan; 6) mempertahankan keunikan karakter dan budaya di area lokal; 7) membantu berkembangnya pembelajaran tentang pertukaran budaya pada komunitas; 8) menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia; 9) mendistribusikan keuntungan secara adil kepada anggota komunitas; dan 10) berperan dalam menentukan prosentase pendapatan (pendistribusian pendapatan) dalam proyek-proyek yang ada di komunitas.
Lebih jauh, Wiwin (2018) menegaskan bahwa konsep Community Based Tourism memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengontrol dan berperan dalam pengelolaan pariwisata. Sebab, masyarakat menduduki posisi sebagai bagian integral yang ikut berperan, baik sebagai subjek maupun objek pembangunan itu sendiri sekaligus pelaku langsung kegiatan pariwisata dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan budaya, sehingga memiliki komitmen yang kuat untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan karena menyangkut kepentingan hidup mereka.
Di Bali, konsep ini telah diimplementasikan oleh Desa Adat Kedonganan sejak 19 tahun lalu terhitung sejak ditetapkannya Kedonganan sebagai Daya Tarik Wisata pada Peraturan Bupati Badung No.7 Tahun 2005 Tentang Objek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Badung. Sampai saat ini, masyarakat Kedonganan berdikari memaksimalkan berbagai potensi yang ada, menyulapnya menjadi destinasi yang memiliki daya tarik tersendiri. Cafe-cafe di sepanjang Pantai Kedonganan misalnya, telah menjadi surga kuliner bagi para pelancong. Setidaknya, terdapat dua puluh empat cafe di Desa Adat Kedonganan yang sistem pengelolaannya dihibahkan kepada enam banjar adat, yakni Banjar Pengenderan, Banjar Pasek, Banjar Kertayasa, Banjar Anyar Gede, Banjar Ketapang, dan Banjar Kubu Alit. Lalu, pasar ikan Kedonganan atau minawisata dengan ikan-ikan segar hasil melaut nelayan. Lebih lanjut, di tengah gempuran turisme saat ini, Kedonganan masih mempertahankan 5 kelompok nelayan yang tersebar di dua wilayah pantainya. Kedua wilayah pantai Kedonganan memiliki karakteristik yang berbeda. Di pantai barat Kedonganan terdiri atas kelompok nelayan Kerta Bali dan Putra Bali sedangkan di pantai timur Kedonganan terdiri atas kelompok nelayan Segara Ayu, Wana Segara Kertih, dan Ulam Sari.
2. Kilas Balik Pariwisata Kedonganan di tahun 1995-2021
Desa Adat Kedonganan menghuni pesisir selatan Pulau Bali yang diberkati potensi hasil laut yang melimpah. Untuk itu, sebagian besar masyarakat Kedonganan bermata pencaharian sebagai nelayan. Bendesa Kedonganan, I Wayan Sutarja menjelaskan, “Potensi Desa Adat Kedonganan memang dari nenek moyang kita itu adalah nelayan. Dan sekarang itu apakah masih tetap nelayan? Masih. Itu potensi yang kita punya di Desa Adat Kedonganan itu dari awalnya.”
Kedonganan telah lama dikenal dengan pasar ikan segar hasil tangkapan nelayan serta sajian kuliner seafood yang khas. Bermula dari para nelayan yang biasa membakar ikan ketika pulang melaut untuk di santap, lambat laun mendorong lahirnya usaha ikan bakar di Kedonganan yang kini menjamur. “Apalagi ikon disini dari Pak Bendesa dulu kan mina wisatanya. Ikon kita disini, kita jual mina wisatanya,” ujar Ketut Suardinata, Ketua Kelompok Nelayan Kerta Bali. Seiring berjalannya waktu, usaha ini berkembang menjadi wisata kuliner yang menjanjikan, sejalan dengan letaknya yang strategis dekat Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Kini, nelayan dan wisata kuliner berjalan beriringan dalam pariwisata Kedonganan dimana nelayan dan pariwisata telah menjadi potensi Desa Adat Kedonganan.
“Nelayan dengan mencari ikannya juga, kemudian pariwisatanya juga. Kalau pariwisata, misalnya destinasi yang kita punya, seperti destinasi kuliner yang ada di pantai itu, mulai operasinya itu biasanya dari jam 10 pagi sampai 10 malam sedangkan kalau nelayan kita melaut itu kebanyakan di sore hari sampai pagi. Nelayan kita itu cuma bisa melaut paling 6 bulan. Pada bulan September, Oktober, seperti itu, musim angin barat itu sudah tidak melakukan aktivitas ke laut. Inilah kuliner-kuliner ini, kita berkolaborasi, kita lakukan bagaimana itu agar masyarakat itu memanfaatkan semua,” lanjut I Wayan Sutarja.
Sama dengan daerah wisata lain yang mengalami pasang surut, terlebih saat dihantam pandemi beberapa tahun silam, Kedonganan juga berjuang untuk tetap hidup dengan memaksimalkan sejumlah potensi yang dimilikinya. Merujuk penelitian oleh (Dewi. dkk, 2023) pada Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN), konsep berkelanjutan yang diterapkan oleh Kedonganan mampu beradaptasi dan bertahan dari permasalahan-permasalahan ekonomi, salah satunya pandemi COVID-19. Bendesa Desa Adat Kedonganan menyatakan bahwa mina wisata mampu menjaga perekonomian desa tetap hidup dengan persentase sebesar 30%. Hal tersebut terlihat dari pendapatan rata-rata pasca pandemi sebesar Rp 200.000.000 melalui kontribusi parkir mobil. Jumlah tersebut menunjukan peningkatan dibandingkan dengan pada masa pandemi yang tidak memperoleh pendapatan sama sekali. Namun, belum mampu menyaingi pendapatan di masa sebelum terjadinya pandemi, sebesar Rp 350.000.000.
Dengan itu, menyadari vitalnya peran masyarakat dalam sebuah atraksi wisata dan menjadi pelaku langsung di dalamnya membuat Kedonganan sejak 2005 menerjemahkan konsep Community Based Tourism (CBT) dalam aktivitas pariwisatanya. Konsep ini telah diimplementasikan oleh Desa Adat Kedonganan sejak ditetapkannya Kedonganan sebagai Daya Tarik Wisata pada Peraturan Bupati Badung No.7 Tahun 2005 Tentang Objek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Badung.
Adapun masifnya pertumbuhan industri wisata di Kedonganan dari masa ke masa mendorong adanya zonasi wilayah dimana saat ini kawasan Pantai Kedonganan (wilayah Barat) dibagi menjadi 4 zona. Zona I sebagai zona nelayan, zona II sebagai zona ekonomi yang terdiri atas kafe-kafe dan pasar ikan, zona III sebagai zona keagamaan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan keagamaan, misalnya kegiatan Melasti atau ritual pembersihan diri dalam menyambut hari raya Nyepi, dan zona IV sebagai zona offshore atau zona laut yang digunakan untuk kegiatan perairan seperti melaut, penyewaan jukung atau perahu, hingga water sport atau olahraga air. Dan dalam setiap zona tersebut, tidak ada satupun yang lepas dari peran masyarakat di dalamnya.
3. Penerapan Community Based Tourism (CBT)
Suansri (2003) dalam bukunya yang bertajuk Community Based Tourism Handbook, menuturkan bahwa penerapan konsep CBT di suatu daerah ditilik dari 5 prinsip, yakni prinsip ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan politik. Pada prinsip ekonomi, konsep CBT diharapkan mampu menghasilkan dana untuk pengembangan komunitas, membuka lapangan pekerjaan di sektor pariwisata, hingga menghasilkan pendapatan bagi masyarakat lokal. Pada prinsip sosial, konsep CBT diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan rasa bangga komunitas, pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, serta penguatan organisasi komunitas bagi generasi muda dan tua.
Selanjutnya, melalui prinsip budaya, konsep CBT diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk menghormati budaya mereka dan budaya luar, mengembangkan pertukaran budaya, dan melekatkan budaya pembangunan dalam budaya lokal. Pada prinsip lingkungan, konsep CBT diharapkan mampu mengembangkan carrying capacity area (daya dukung spesies biologis), menghadirkan sistem pembuangan sampah yang ramah lingkungan, dan meningkatkan kepedulian tentang pentingnya konservasi. Terakhir, pada prinsip politik, konsep CBT diharapkan mampu meningkatkan upaya partisipasi dari masyarakat lokal, meningkatkan upaya kekuasaan komunitas secara lebih luas, dan menghadirkan mekanisme yang menjamin hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam.
a. Prinsip Ekonomi
Prinsip ekonomi dalam konsep CBT diharapkan mampu menghasilkan dana untuk pengembangan komunitas, membuka lapangan pekerjaan di sektor pariwisata, hingga menghasilkan pendapatan bagi masyarakat lokal. Berdasarkan konsep tersebut, dalam implementasinya di Desa Adat Kedonganan, masyarakat diberikan kesempatan untuk memiliki dan mengelola kafe yang ada, membuat usaha ikan bakar, menjual pasokan makanan laut atau seafood, menyewakan jukung (perahu) bagi wisatawan, hingga menjadi penari tarian tradisional Bali di kafe yang ada.
Kesempatan ini membawa berkah bagi masyarakat lokal Kedonganan dan luar Kedonganan dimana mereka dapat bekerja di kafe-kafe yang ada, di usaha ikan bakar, di perusahaan nelayan, hingga menjadi penjual jagung bakar dan pemusik di kawasan usaha ikan bakar. “Untuk yang lain (selain 24 kafe) boleh, seperti pedagang jagung dan pemusik. Kita ada MOU dengan pedagang jagung. Kemudian pemusik juga ada setiap makan malam di sini (kawasan usaha ikan bakar). Itu bukan liar, tapi kita kelola. Jadi kalo adik-adik mengikuti, hampir semua suku ada, suku Jawa, Batak, Bugis. Semua ada disini. Karena kita terbuka disini,” jelas Made Pakris mengenai ketenagakerjaan di pariwisata Kedonganan.
Upaya pembangunan wisata berbasis masyarakat ini tidak lepas dari peran serta aparatur desa, melalui dukungan dana dari LPD Desa Adat Kedonganan Dilansir dari WALHI dalam Ekonomi Nusantara: Tawaran Solusi Pulihkan Indonesia (2021), peran LPD Adat Kedonganan sangat besar dalam pembangunan 24 kafe. LPD Desa Adat Kedonganan menyalurkan kredit total senilai Rp12.000.000.000 untuk investasi awal. Masing-masing kafe mendapat fasilitas kredit senilai Rp500.000.000. Sementara setiap krama (masyarakat adat), juga diberikan fasilitas kredit tanpa agunan senilai Rp5.000.000 – Rp10.000.000. Sejalan dengan klaim WALHI, Ketua BPKP2K, Made Pakris menyebut LPD memberikan pinjaman bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan pinjaman modal. “Ini kan cukup besar biaya membangun usaha, fisiknya, kemudian biaya operasionalnya, dibantu lah oleh keuangan LPD. Pada saat kita meminjam kesitu, ya kemudian hasil daripada operasional itu untuk membayar,” jelasnya.
b. Prinsip Sosial
Perkembangan sektor pariwisata di Kedonganan berimpak terhadap kehidupan masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam prinsip sosial, konsep CBT diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan rasa bangga komunitas, pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, dan penguatan organisasi komunitas bagi generasi muda dan tua.
Dikutip dari Suasapha dalam Jurnal JUMPA berjudul Implementasi Konsep Pariwisata Berbasis Masyarakat Dalam Pengelolaan Pantai Kedonganan, ketika terdapat 67 kafe di Kedonganan yang pemiliknya tidak semuanya adalah warga lokal Kedonganan, timbul rasa kekhawatiran atas “tidak mau menjadi penonton di tanah sendiri” di benak masyarakat Kedonganan. Mereka kemudian mengusulkan ke desa adat untuk melakukan penataan ulang di kawasan pariwisata Pantai Kedonganan. Hal ini menunjukan adanya kesadaran komunitas untuk mempertahankan wilayahnya untuk tetap dikelola masyarakat setempat. “Orang-orang Bali menjadi penonton di rumahnya sendiri, kan sering denger begitu. Kedonganan gak mau begitu, dia mau menjadi raja di rumahnya sendiri,” ucap Made Pakris.
Pengelolaan kawasan wisata secara mandiri juga sejalan dengan peran-peran lintas gender dan generasi dalam tata kelola ataupun manajemen kerja. Ketika kelompok masyarakat dihibahkan kafe, desa adat dan lembaga terkait tidak mengintervensi pembagian kerja tiap orang. Kelompok masyarakat akan berdelebrasi tentang peran kerja, tata kelola, dan kegiatan-kegiatan lain di lantai produksi, sesuai dengan kemampuan dan pengalaman dengan tidak memandang gender dan generasi.
“Kita, desa adat maupun lembaga ini tidak masuk. Ya, itu kan. Ya, mereka dengan berdasarkan pengalaman seperti apa untuk mengelola itu, kita tidak masuk di situ,” sambung Made Pakris.
c. Prinsip Budaya
Berada di pusat turisme Bali, Desa Adat Kedonganan memelihara kearifan lokalnya untuk terus hidup dan beradaptasi dengan banyaknya penetrasi budaya asing di Bali sebagaimana prinsip budaya, konsep CBT yang mengharapkan masyarakat untuk menghormati budaya mereka dan budaya luar, mengembangkan pertukaran budaya, dan melekatkan budaya pembangunan dalam budaya lokal.
Dinukil dari WALHI dalam Ekonomi Nusantara: Tawaran Solusi Pulihkan Indonesia, sejumlah tradisi Kedonganan sampai saat ini masih ajeg sebab dijaga kelestariannya, seperti tradisi ngujur, tradisi mebuug-buugan, hingga upacara odalan dan melasti. Tradisi ngujur yaitu tradisi dimana para warga membantu mengangkat jukung atau perahu nelayan yang datang melaut ke daratan lalu bersama-sama membersihkannya. Biasanya para nelayan akan memberikan ikan sebagai ucapan terima kasih kepada warga yang membantu. “Masyarakat kedonganan kalau ikan untuk lauk pasti dikasi itu juga bila ngujur,” ujar Ketut Suardinata.
Lebih lanjut, terdapat tradisi mebuug-buugan yaitu melumuri tubuh dengan lumpur di pantai timur Kedonganan lalu berjalan kaki ke pantai barat untuk membersihkan diri di laut dan dengan percikan tirta. Tradisi ini dilakukan sehari setelah hari raya Nyepi dan hanya ada di Kedonganan. Di saat bersamaan ,tradisi yang dilakukan telah menjadi atraksi wisata budaya bagi wisatawan yang berkunjung ke Kedonganan. Ada pula upacara keagamaan Hindu seperti odalan dan melasti. Melasti adalah upacara penyucian diri dalam menyambut hari raya Nyepi yang dilaksanakan di pantai barat Kedonganan. Pada pelaksanaan upacara melasti ataupun odalan di Pura Segara, 24 kafe yang ada di pesisir pantai barat ditutup. “Tidak, (kami) tutup. Khusus untuk kegiatan agama itu sudah diatur. Contoh seperti upacara odalan Pura Segara, kita wajib tutup. Jadi tidak selalu harus buka,” ujar Made Mahendra, Manager Aroma Cafe sekaligus Ketua LPM Kedonganan.
Hal ini menunjukkan bagaimana budaya dengan nilai-nilai spiritual yang dirawat masyarakat setempat telah memberikan impak pada kelangsungan pariwisata di Kedonganan dan tetap menerapkan batasan-batasan agar tidak mengusik kesakralan yang telah dijaga selama ini. Selain itu, dengan adanya 24 kafe di Kedonganan, pemuda pemudi Kedonganan yang bisa menari Bali memiliki kesempatan untuk memperoleh penghasilan dari keterampilan menarinya tersebut sekaligus terus menjaga seni tari tradisional tetap hidup dan dikenal.
d. Prinsip Lingkungan
Pengelolaan wisata penting untuk mempertimbangkan daya dukung dalam mendukung turis yang berkunjung. Definisi daya dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya sebagaimana yang termaktub dalam UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Linier dengan prinsip lingkungan, konsep CBT diharapkan mampu mengembangkan carrying capacity area (daya dukung spesies biologis), menghadirkan sistem pembuangan sampah yang ramah lingkungan, dan meningkatkan kepedulian tentang pentingnya konservasi.
Pada implementasinya, para pelaku wisata di Desa Adat Kedonganan telah menyediakan septic tank di setiap kafe untuk limbah-limbah yang mereka produksi. “Kalau kita di sini menggunakan septic tank. Ada beberapa titik. Jadi setiap tempat, contoh (tempat) cuci piring punya septic tank-nya khusus. Untuk toilet, septic tank-nya khusus. Di dapur, septic tank-nya khusus. Banyak septic tank jadinya di sini,” jelas Made Mahendra. Pemilahan sampah organik dan anorganik juga sudah dilakukan untuk memudahkan petugas DLHK dalam mengangkut dan mengolah sampah. Selain itu, Kedonganan sendiri memiliki TPS (Tempat Penampungan Sementara) 3R Kedonganan Ngardi Resik yang mengolah sampah-sampah organik masyarakat Kedonganan dan limbah dapur dari kafe, seperti sisa makanan, isi perut ikan, dan limbah buah, untuk dijadikan pupuk kompos atau pupuk POC (pupuk cair). “Satu kafe kita ambil limbahnya, artinya limbah dapur, sisa makanan. Sisa makanan, isi perut ikan, nah itu yang kita mau olah dengan dijadikan pupuk POC. Pupuk cair ya. Sama limbah buahnya, terutama yang bisa dicampurkan nanti di POC itu sendiri,” jelas Ketua TPS 3R KNR, Wayan Widiantara.
Lebih lanjut, masyarakat Kedonganan yang memiliki ternak juga berkontribusi dalam upaya pengelolaan sampah dengan mengambil dan memberi sampah sisa makanan untuk diberikan kepada ternak mereka. “Kalo sisa makanan tuh rata-rata hampir semua tuh ngambilnya dari yang ngambil itu orang Kedonganan. Kan banyak punya usaha ternak babi kayak gitu-gitu di Kedonganan. Kita lebih ke ngasih orang Kedonganan. Maksudnya dia lebih membutuhkan lah, biar ga usah jauh-jauh dia nyari, kita ngasihnya ke orang Kedonganan,” ujar pengelola New Furama Cafe, Gede Eka. Selain itu, adanya BPKP2K juga membantu dalam menjaga kebersihan kawasan pariwisata Pantai Kedonganan seperti mengadakan kegiatan pembersihan pantai bersama-sama.
Adapun para nelayan di kawasan pantai timur Kedonganan mulai membersihkan mangrove dari sampah plastik dan jaring-jaring nelayan yang lepas di sekitar tahun 2020-an saat pandemi COVID 19. Sebab inisiasi tersebut, mangrove di pantai timur Kedonganan sudah dapat dibudidayakan kembali dan dimanfaatkan pariwisata juga serta berimpak pada bertambahnya jenis biota laut di pantai timur. Ketua kelompok nelayan Wana Segara Kertih, Nyoman Sunarta menyampaikan, “Dengan kita lakukan bersih mangrove, jadi otomatis ikan-ikan yang dulunya tidak berani ke mangrove, sekarang sudah berani bertelur, beranak dia ke sini. Jadi diuntungkan.” Hal ini menunjukkan peningkatan kepedulian terhadap pentingnya konservasi dan perkembangan daya dukung spesies biologis. Wisatawan juga kerap datang ke pantai timur Kedonganan untuk melakukan tur mangrove, kano, dan fidel.
e. Prinsip Politik
Pada dasarnya, konsep CBT adalah konsep yang berlandaskan pada partisipasi masyarakatnya. Masyarakat berkontribusi dan memanfaatkan peluang yang ada dari potensi desa untuk keberlangsungan pariwisata di Kedonganan. Pada penerapan konsep CBT di Kedonganan, setiap 6 banjar, Desa Adat, Kelurahan, dan LPM Kedonganan, mendelegasikan satu orang sebagai jajaran di Badan Pengelola Kawasan Pariwisata Pantai Kedonganan (BPKP2K). Wewenang yang dimiliki oleh delegasi setiap lembaga dapat menjamin akuntabilitas program pengelolaan. Tidak hanya itu, informasi-informasi perihal partisipasi keamanan dan kebersihan dapat tersalurkan secara efektif melalui forum rapat. “Saya kan disini wakil-wakil dari banjar. Banjar itu juga terlibat di sini, kelian dinas dan kelian adatnya. Pada saat rapat Banjar, saya pasti akan menyampaikan kepada warga Banjar yang notabene sebagai pengelola di sini. Dia sebagai owner di sini. Itu medianya. Menyangkut masalah partisipasi, keamanan, kebersihan, bersama-sama menjaga,” ucap Made Pakris.
Apabila merujuk tingkatan partisipasi masyarakat yang dilansir dari International Association for Public Participation (Arnstein, 1969) yaitu: (1) manipulation atau manipulasi; (2) therapy atau terapi; (3) informing atau pemberitahuan; (4) consultation atau konsultasi; (5) placation atau penentraman; (6) partnership atau kemitraan; (7) delegation atau delegasi; dan (8) citizen control atau kontrol masyarakat. Terlihat masyarakat kedonganan mencapai tingkat delegation atau delegasi dalam penyelenggaraan aktivitas wisatanya.
Meskipun demikian, partisipasi masyarakat Kedonganan dalam tahap pelaksanaan dinilai kurang oleh Ketua BPKP2K, Made Pakris. “Kurangnya partisipasi mereka menyangkut masalah keamanan kebersihan. Kita undang ketua kelompok ownernya. Ketua kelompok owner-nya lah yang nanti akan menyampaikan di masing-masing anggotanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kan wakil-wakil dari Banjar ini. Banjar itu juga terlibat di sini kelian dinas dan kelian adatnya. Pada saat rapat Banjar, saya pasti akan menyampaikan kepada warga Banjar yang notabene sebagai pengelola di sini. Dia sebagai owner di sini. Itu medianya. Menyangkut masalah partisipasi, keamanan, kebersihan, bersama-sama menjaga. Berbuih lah ceritanya. ‘Oh siap, siap’. Begitu kita butuhkan, ‘Ampura, saya lagi bekerja. Ampura, saya ngajak cucu’. Ya sudah lah maklum aja.”
4. Penutup
Kedonganan kini menjadi salah satu destinasi wisata populer di Bali, khususnya bagi mereka yang ingin mengecap lezatnya hidangan laut di tepi pantai Kedonganan atau berburu ikan-ikan segar tangkapan nelayan. Namun, apa yang dimilikinya kini tidak lantas membuat Kedonganan ongkang-ongkang kaki. Enggan berdiam tanpa peran, masyarakat Kedonganan mampu berdikari dengan mengimplementasikan konsep Community Based Tourism. Partisipasi aktif dari masyarakat, pembentukan lembaga, pengelolaan daya tarik yang berwawasan lingkungan, serta adanya usaha pariwisata dari dan untuk masyarakat adalah fondasi kuat dalam penyelenggaraan CBT di Desa Adat Kedonganan. Masyarakat yang diusung sebagai pelaku utama merupakan bagian penting untuk memastikan pembangunan industri wisata yang berkelanjutan.
Konsep Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) di Kedonganan menekankan partisipasi masyarakat lokal melalui pengelolaan 24 kafe, menjual pasokan makanan laut atau seafood di mina wisata, fasilitasi wisata air dengan menyewakan jukung (perahu) bagi wisatawan, hingga menjadi penari tarian tradisional Bali untuk menghibur wisatawan, integrasi antar sektor inilah yang telah menjadi pemikat wisatawan di Kedonganan. Daya tarik ini mampu menguatkan prinsip-prinsip Community Based Tourism, dari segi ekonomi, budaya, dan lingkungan. Pengembangan pantai timur untuk ekowisata mangrove juga turut mendukung penerapan konsep ini. Sinergi antara masyarakat dengan pemegang kebijakan juga terlihat dalam pengambilan keputusan yang diperlukan demi keberlangsungan pariwisata Kedonganan.
Desa Adat Kedonganan berdasarkan 5 prinsip penerapan CBT, terlihat bahwa terjadi ketimpangan pada prinsip politik, tepatnya pada partisipasi masyarakat di lingkup keamanan dan kebersihan. Meskipun struktur partisipatif telah terbentuk, ada beberapa tantangan dalam melibatkan masyarakat. Sebab, tidak dapat dipungkiri, menggerakan seluruh masyarakat akan sulit jika tidak dibarengi dengan inisiatif dalam diri. Keamanan dan kenyamanan adalah dua hal esensial yang sangat berdampak pada kesan wisatawan ketika berkunjung. Sejalan dengan konsep sadar wisata, Sapta Pesona, poin “kenangan” menjadi kunci repetisi kunjungan wisatawan pada objek wisata. Desa Adat Kedonganan perlu berbenah dan meninjau kembali kiat-kiat yang efektif untuk menggerakan masyarakat secara masif untuk sadar akan pentingnya poin ini.
Maka dari itu, patut untuk diungkap ke publik tentang kebijakan partisipatif masyarakat dan pemantauan juga evaluasi terhadap kebijakan program keamanan dan kebersihan. Hal ini dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai, memberikan umpan balik, dan introspeksi. Selain itu, perlu adanya kolaborasi inovatif dengan sektor swasta sebagai penyedia sumber daya dan edukasi bagi masyarakat. Dengan pendekatan-pendekatan inovatif dan transparansi agar dapat menjaga dan memperluas kualitas partisipasi masyarakat dalam mendukung industri wisata berkelanjutan di Kedonganan.
Penulis : Wulan, Dian
Penyunting : Trisna Cintya
Daftar Pustaka
Andika, P. V. (2022). Mengenal Arnstein’s Ladder dalam Menata Partisipasi Publik. URL: https://iap2.or.id/mengenal-arnsteins-ladder-dalam-menata-partisipasi-publik/. Diakses pada 05 Agustus 2024.
Dewi, N. K. P., dkk. (2023). Resiliensi Desa Kedonganan dalam Pembangunan Daya Tarik Wisata (DTW) Kabupaten Badung di Era New Normal. Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN), 1(2), 49-51.
Indriani, C., dkk. (2021). Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pali Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja. Development Policy and Management Review (DPMR), 1(1), 59.
Kristianto, F. (2023). Ada FishGo Nelayan Langsung Go. URL: https://bali.bisnis.com/read/20231103/537/1711641/ada-fishgo-nelayan-langsung-go. Diakses pada 06 Agustus 2024.
Nawabali.id. (2023). Jalur Inspeksi Ecomangrove Ulam Sari Kedonganan, Permudah Aktivitas Nelayan dan Peneliti. URL: https://nawabali.id/jalur-inspeksi-ecomangrove-ulam-sari-kedonganan-permudah-aktivitas-nelayan-dan-peneliti/. Diakses pada 06 Agustus 2024.
Sembiring, B. J. E., dkk. (2021). Ekonomi Nusantara: Tawaran Solusi Pulihkan Indonesia. Jakarta Selatan: Eksekutif Nasional WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia).
Suansri, P. (2003). Community Based Tourism Handbook. Bangkok: Responsible Ecological Social Tour-REST.
Suasapha, A. H. (2016). Implementasi Konsep Pariwisata Berbasis Masyarakat Dalam Pengelolaan Pantai Kedonganan. JUMPA, 2(2), 63-68.
Syafiqah, K. K., dkk. (2022). Implementasi Konsep Community Based Tourism (CBT) Dalam Mendukung Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan pada Destinasi Wisata Sanghyang Kenit di Kabupaten Bandung Barat. MAHACITA: Jurnal Pecinta Alam dan Lingkungan, 1(2), 4-5, 8-12.
Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Wijaya, N. S., & Sudarmawan, I W. S. (2019). Community Based Tourism (CBT) Sebagai Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di DTW Ceking Desa Pekraman Tegallalang. Jurnal Ilmiah Hospitality Management, 10(1), 78.
Wiwin, I Wayan. (2018). Community Based Tourism Dalam Pengembangan Pariwisata Bali. Pariwisata Budaya, 3(1), 70.

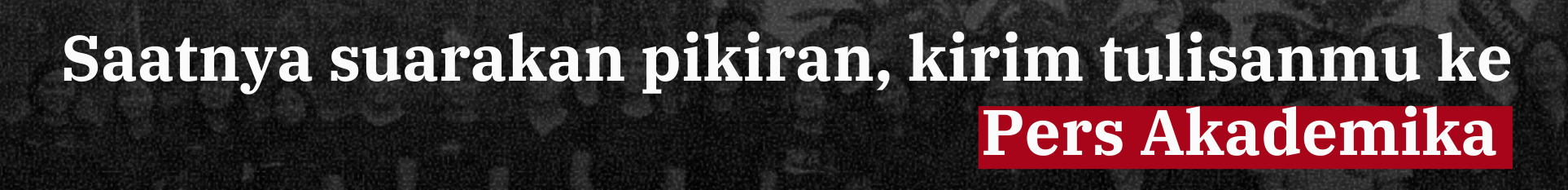







Monitoreo de condicion
Aparatos de balanceo: importante para el rendimiento fluido y efectivo de las dispositivos.
En el entorno de la tecnología contemporánea, donde la rendimiento y la estabilidad del aparato son de gran importancia, los equipos de calibración cumplen un rol crucial. Estos dispositivos especializados están creados para ajustar y asegurar piezas móviles, ya sea en equipamiento productiva, automóviles de traslado o incluso en dispositivos caseros.
Para los profesionales en reparación de equipos y los profesionales, trabajar con dispositivos de calibración es esencial para asegurar el operación estable y fiable de cualquier dispositivo móvil. Gracias a estas soluciones avanzadas sofisticadas, es posible reducir notablemente las sacudidas, el sonido y la carga sobre los sujeciones, mejorando la duración de componentes importantes.
Igualmente importante es el rol que desempeñan los dispositivos de balanceo en la asistencia al comprador. El asistencia experto y el conservación regular aplicando estos aparatos habilitan brindar prestaciones de gran estándar, aumentando la agrado de los clientes.
Para los propietarios de negocios, la financiamiento en equipos de balanceo y dispositivos puede ser clave para incrementar la eficiencia y eficiencia de sus dispositivos. Esto es principalmente significativo para los inversores que administran modestas y modestas emprendimientos, donde cada elemento cuenta.
Asimismo, los dispositivos de equilibrado tienen una extensa aplicación en el campo de la fiabilidad y el supervisión de excelencia. Posibilitan identificar probables fallos, reduciendo arreglos elevadas y perjuicios a los sistemas. Además, los información obtenidos de estos aparatos pueden aplicarse para maximizar procedimientos y aumentar la presencia en buscadores de investigación.
Las zonas de uso de los equipos de equilibrado incluyen múltiples sectores, desde la producción de bicicletas hasta el control ambiental. No interesa si se refiere de extensas manufacturas de fábrica o modestos espacios hogareños, los dispositivos de balanceo son indispensables para asegurar un operación óptimo y sin riesgo de paradas.
Platform Daster4D adalah pilihan terbaik para penikmat game slot. Menyajikan game slot menang mudah dengan tingkat kemenangan tinggi, isi saldo praktis, dan customer support 24 jam. Rasakan serunya bermain dan cuan tiada akhir sekarang juga!