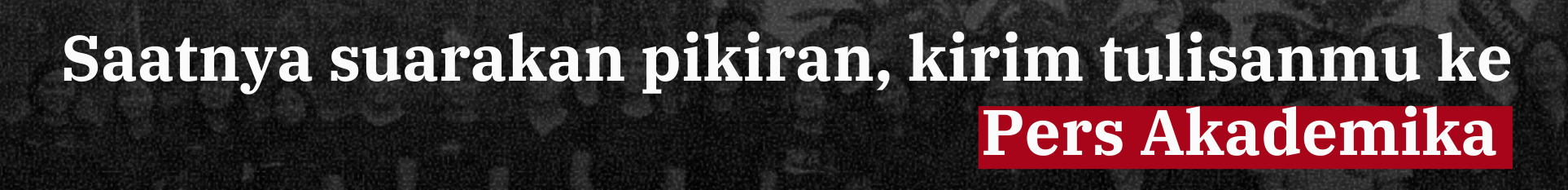Bagaimana Sejatinya Wajah Warisan Budaya Dunia di Bentang Jatiluwih?

Subak Jatiluwih menyandang gelar warisan budaya dunia sekaligus sebagai daerah tujuan wisata. Namun, di tengah hiruk-pikuk pariwisata di sana, management plan Jatiluwih yang disusun kala mengusulkan subak sebagai warisan budaya dunia kepada UNESCO malah tertimbun, tak diindahkan. “Warisan harus dijaga secara aktif, bukan sekadar dipertahankan di atas kertas, ” tutur Alit Artha ketika membahas soal wajah Jatiluwih di hari ini.
Jatiluwih Sebelum Pariwisata
Sebelum pariwisata berkembang pesat di Jatiluwih, saat-saat sebelum gedung-gedung beton menjamah tanah sawah yang hijau, wilayah ini pernah bernapas dalam harmoni pedesaan yang murni. Keindahan alamnya yang damai, udara pegunungan yang sejuk, lanskap sawah berundak (terasering) serta kehidupan masyarakat pedesaan yang penuh kesadaran akan makna, merupakan daya tarik utamanya. Jatiluwih dulu adalah potret Bali yang masih perawan, jauh dari hiruk pikuk modernitas. Sekarang, bagi Jatiluwih yang hilang bukan hanya wajah, tetapi cara kita melihat dan menghargainya. Ketika waktu terus mengalir, beranjak dari satu masa ke masa yang lain, Jatiluwih dalam pesonanya hari ini, menyimpan jejak-jejak leluhur yang samar-samar terbenam. Melihat keadaan hari ini, saat gedung restoran atau villa beradu megah dengan sawah. Maka terkesan bahwa sawah bukan lagi sumber harapan utama, melainkan tanah yang harus digarap agar villa dan restoran memiliki aksesoris yang cantik. Ketika perubahan tersebut mulai terasa melewati batas-batas nurani, maka mengingat merupakan bentuk tanggung jawab.
Jejak nenek moyang tak hanya hidup dalam cerita, tetapi juga terpatri dalam lanskap, dan sistem sosial yang membentuk keseharian masyarakatnya. Jatiluwih dengan keindahannya menghampar di kaki Gunung Batukaru. Desa yang terletak di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, ini tergabung ke dalam kawasan Catur Angga Batukaru yang meliputi beberapa pura suci, seperti Pura Petali, Pura Besikalung, Pura Batukaru, Pura Tambawaras, dan Pura Muncaksari. Selain itu, wilayah ini juga memiliki beberapa Subak (sistem irigasi sawah secara tradisional-red) dan 12 desa, dimana salah satunya adalah Jatiluwih.
Catur Angga merupakan salah satu Cultural Heritage (warisan budaya dunia) yang telah diakui oleh UNESCO sejak tahun 2012. Kawasan ini tidak hanya istimewa karena bentang alamnya, namun lebih dari itu karena filosofi hidup yang tertanam di dalamnya. “Kemudian untuk kawasan Catur Angga Batukaru adalah kondisi murni dimana Tri Hita Karana (filosofi hidup masyarakat Bali) diimplementasikan dalam kehidupan sehari hari, dimana kita percaya dalam aspek palemahan (hubungan harmonis manusia dengan lingkungan), pawongan (hubungan harmonis sesama manusia), parahyangan (hubungan harmonis manusia dengan Tuhan),” kata Alit Artha yang merupakan Ketua Tim Pemetaan Kawasan Subak yang menjadi bahan utama untuk diajukan ke UNESCO agar diakui sebagai WBD.
Subak kerap menjadi sebuah kata yang mengalir indah di benak. Namun ia bukan sekadar sistem irigasi sawah semata. Subak adalah perwujudan filosofi hidup yang tercermin dalam kehidupan masyarakat di Jatiluwih. Pada masa silam, konsep pertanian masih terjaga, sawah bukan hanya dipandang sebagai ladang pangan, tetapi ruang sakral yang memupuk nilai-nilai bertani yang penuh kesadaran dan rasa syukur. Dahulu semangat gotong royong masih terjalin begitu kuat. Di mana ketika musim bercocok tanam tiba, para petani akan berkumpul dan bersama-sama turun menggarap sawah. Hal ini juga ditegaskan oleh I Nengah Tirta, salah satu pekaseh (ketua) di Subak Jatiluwih, “Istilahnya menanam padi itu, sistemnya gotong royong,” ujarnya saat diwawancarai pada (14/07/2025). Gotong royong antar petani ini tidak hanya sekadar kerja bersama, tetapi juga terorganisasi dalam kelompok-kelompok yang disebut Sekaa. Masing-masing Sekaa memiliki peran yang spesifik dalam seluruh rangkaian aktivitas bertani. Mulai dari mengolah tanah, mengatur pengairan, mejukut atau membersihkan gulma, hingga panen.
Dalam praktiknya, subak lahir sebagai local wisdom (pengetahuan tradisional) yang hadir sebagai pedoman kultur agraris masyarakat. Siklus pertanian dan ritual tidak terlepas dari konsep Tri Hita Karana yang bersemayam dalam setiap langkah yang ditempuh. Pertanian di Jatiluwih dilakoni melalui praktik yang masih tradisional. Dalam mengolah lahan, dahulu petani Jatiluwih mengandalkan alat-alat tradisional dan menggunakan bajak yang ditarik oleh sepasang sapi. Mengutip dari laman Tatkala.co yang berjudul “Jatiluwih, Ritus Padi, dan Hal-hal Dibaliknya,” dijelaskan serangkaian proses dan ritual yang ditempuh petani di Jatiluwih dalam mengolah sawah mereka selama berabad-abad. Seluruh praktik yang dijalani bukan sekadar rutinitas, melainkan perwujudan konkret dari filosofi Subak yang menanamkan harmoni antara manusia, alam, dan spiritualitas dalam setiap tahap bertani.
Seperti misalnya, sebelum mulai menggarap lahan sawahnya, para petani senantiasa dan tidak pernah lupa untuk menghaturkan kepada alam dan sang pencipta, sebagaimana yang terpatri dalam konsep parahyangan dan pawongan. Salah satu contoh tradisi tersebut, maka dilangsungkanlah upacara Mapag atau Magpag Toya (menjemput/mengambil air) ke sumber mata air seperti sungai atau danau, dengan harapan kepada Tuhan yang bermanifestasi sebagai Dewa Wisnu untuk memberikan air yang berlimpah, yang kemudian akan dialirkan melalui sistem subak. Mulai dari sebelum bercocok tanam hingga panen selesai, cerminan nilai-nilai luhur ini terpatri di setiap tapak yang ditempuh para petani di desa Jatiluwih. Sehingga hamparan keindahan dan panorama sawah berundak tidak hanya menakjubkan netra, namun juga mencerminkan wujud konkret dari nilai-nilai kearifan lokal yang kental tersebut. Lakon hidup yang lahir dari filosofi lokal ini, pada akhirnya menjadi daya tarik tersendiri yang kemudian memikat jutaan mata dari penjuru dunia. Alhasil, sematan yang diberikan kepada Jatiluwih sebagai “Warisan Budaya Dunia” benar-benar mencerminkan wajahnya sebagai ruang hidup budaya masyarakat. Namun kegusaran pun perlahan muncul bersamaan dengan momen tersebut. Apakah di kemudian hari filosofi ini masih disadari atau mulai terbenam di benak?
Munculnya pariwisata
Bali memang selalu lekat dengan pariwisata. Boleh dikata bahwa pariwisata ibarat tulang punggung perekonomian Bali yang utama sejak dulu hingga hari ini. Dari biru di pantai hingga hijau di sawah, semuanya tak luput dari dekap pariwisata, begitupun Jatiluwih. Pada laman kulkulbali.co, Bella Andini dalam tulisannya yang bertajuk “Catur Wana Jatiluwih, Konservasi, dan Pariwisata,” dipaparkan bahwa Jatiluwih, secara etimologi dalam bahasa Bali berasal dari kata “jati” yang berarti “sesungguhnya” dan “luwih” yang berarti “indah, bagus, baik”, sehingga dalam bahasa Bali Jatiluwih berarti tempat yang memang benar-benar sungguh indah. Hamparan persawahan dengan sistem terasering menjadi paras yang orang ingat tentangnya. Begitu juga dengan paduan harmoni dari hijau ilalang dan padi-padi yang menguning, menjadi pemandangan indah yang senada dengan namanya.
Benih pariwisata mulai tumbuh sekitar tahun 1980, Bella Andini menyebutkan bahwa hal tersebut bermula dari adanya proyek swasembada pangan pemerintah Indonesia kala itu. Pembangunan jalan dan irigasi untuk menunjang peningkatan sektor pertanian pada masa itu mempermudah akses kunjungan ke Jatiluwih. Dalam proposal Nomination for Inscription on The UNESCO World Heritage List: Cultural Landscape of Bali Province yang diajukan oleh Alit Artha bersama timnya, disebutkan bahwa awal mula pariwisata masuk ke Jatiluwih erat kaitannya dengan daya tarik lanskap sawah terasering subak yang unik, serta nilai budaya Tri Hita Karana yang mendasari pengelolaan alam, manusia, dan spiritualitas. Lambat laun keasrian itu menjalar dari mulut ke mulut hingga merebak ke manca negara, dunia mulai mengenal keelokannya. “Jatiluwih terkenal itu dari tahun 90-an. Sudah terkenal, kita juga sudah mendapatkan kunjungan (pariwisata-red) dari tahun 90-an, hampir berbarengan lah sama Penglipuran sebenarnya,” kata I Putu Eka Saputra, sekretaris Manajemen Operasional Daya Tarik Wisata Jatiluwih pada (15/07/2025). Selaras dengan pernyataan I Nengah Kartika, “Dari tahun 1994, kami ditetapkan menjadi desa wisata, bersamaan dengan Sebatu dan Penglipuran,” imbuh perbekel Desa Jatiluwih tersebut ketika ditemui pada (15/07/2025).
Jejak pariwisata mulai akrab memijak tanah Jatiluwih. Menyibak pandangan tentang bentang pesawahan itu. Antara ladang pangan dan sebuah peluang cuan. Selain itu, sawah tidak lagi hanya menjadi ruang tumbuh bagi padi-padi untuk mengisi lumbung, tetapi juga sebuah wadah rekreasi untuk membasuh lelah bagi mereka yang melancong ke sana. Kedatangan wisatawan membawa perubahan bagi petani yang semula hanya bergulat dengan tanah dan benih padi saban harinya. Satu di antaranya ialah I Made Gendra. Mengutip dari laman BaleBengong dalam tulisan berjudul “Subak Jatiluwih, Warisan Dunia dalam Ancaman” petani di Jatiluwih itu kini juga menambah profesi menjajakan dagangan kepada para pelancong. Ia menjual aneka makanan dan minuman di gubuk yang terletak persis di samping area trekking utama Jatiluwih. Tak ada data resmi pada laman pengelola yang mencatat rata-rata kunjungan wisatawan ke DTW Jatiluwih yang terpublikasi luas. Menurut kabar dari laman BaliPost yang berjudul “Pertahankan Kualitas, Wisata Jatiluwih Tambah Jalur Tracking” disebutkan bahwa rata-rata kunjungan wisatawan mancanegara dapat menyentuh angka 1000 pelancong per harinya disusul kisaran wisatawan domestik di angka 200-300 pengunjung per hari. Sekretaris manajemen operasional DTW Jatiluwih menuturkan bahwa aktivitas pariwisata di persawahan tersebut sepenuhnya menyerap tenaga kerja lokal yang direkrut setelah melalui proses seleksi. “Pengelolaan untuk di daya tarik wisata khususnya di daya tarik wisata di sini 100% masyarakat lokal. Jadi sistem untuk menjadi karyawan di manajemen operasional ini adalah seleksi,” jelas Eka Saputra. Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa manajemen operasional berfokus dalam upaya mendatangkan wisatawan. “Sebanyak-banyaknya dengan catatan tidak merusak alam,” kata Eka Saputra. Tak hanya itu, manajemen juga mengatur pembagian pemasukan yang diperoleh dari aktivitas pariwisata di sana. Eka menjelaskan bahwa di tahun 2024 lalu, manajemen mengalirkan dana CSR kepada petani sebesar 600 juta rupiah. Hibah juga datang dalam bentuk pemberian bantuan pupuk, bibit tani, serta tunjangan untuk keperluan upacara di subak. Pekaseh sekaligus petani bernama Nengah Tirta, mengakui adanya perbedaan sebelum dan sesudah pariwisata masuk. Jika dahulu petani masih harus membayar pahpahan saat ada upacara di subak mereka, kini biaya tersebut dapat ditutupi dari pemasukan pariwisata. “Ada kok kesenjangan, artinya ada perbedaan. Kalau saya pribadi, lebih enak yang sekarang,” kata Nengah Tirta ketika diwawancarai pada (15/07/2025).
Aktivitas Pariwisata-Wisatawan di Jatiluwih |
Di sana, bersemayam pula warisan berharga
I Wayan Alit Artha Wiguna yang merupakan Ketua Tim Pemetaan Kawasan Subak yang menjadi bahan utama untuk diajukan ke UNESCO menuturkan bahwa sejak tahun 2000 pemerintah mengusulkan subak sebagai warisan budaya dunia. Selain fungsi praktis mengelola air, subak juga memiliki dimensi religius, karena air irigasi dianggap sebagai karunia dari Dewi Danu yang dipercaya sebagai Dewi Danau. Para petani wajib memberikan sebagian kecil hasil panennya sebagai sesajen di pura subak yang didedikasikan untuk Dewi Danu dan dewa-dewi kesuburan lainnya. “Dalam hal ini tidak hanya Bali barangkali Indonesia lewat provinsi Bali mengusulkan subak sebagai warisan dunia,” terang Alit Artha. Ia mengungkap bahwa upaya yang dilakukan pemerintah tersebut tidaklah singkat prosesnya. “Hampir 8 tahun diusulkan. Ga sampai-sampai, tidak bisa diterima,” imbuh penyuluh pertanian itu. Pada masa itu, Alit Artha tengah menempuh pendidikan strata 3 di Bogor. Kemudian ia diajak oleh dosennya kala itu untuk bergabung dalam tim penyusun proposal untuk mengajukan beberapa situs di Bali sebagai warisan budaya dunia kepada UNESCO, yang salah satunya ialah subak Jatiluwih.
Mengenai subak, Alit Artha menyebutkan bahwa ia bersama tim mesti dapat membuktikan bahwa sistem irigasi tersebut merupakan nilai yang autentik dan juga universal. Bukan sistem irigasi semata melainkan juga sebuah nilai yang religi. Hal itu senada dengan pernyataan Sumiyati. Dalam buku “Sarasastra V” akademisi Universitas Udayana tersebut menjelaskan bahwa subak merupakan manifestasi dari filosofi Tri Hita Karana yang diakui memiliki nilai universal luar biasa (outstanding universal value). Alit Artha menuturkan bagaimana filosofi keharmonisan tersebut tercermin dalam kehidupan pertanian dalam subak. “Diimplementasikan petani memelihara hubungan harmonis antara manusia dengan manusianya, manusia dengan lingkungan, (yaitu-red) dengan subaknya dalam berbagai aktivitas seperti pertanian organik. Kemudian hubungan manusia dengan Tuhan yang diterjemahkan dengan adanya pura di setiap subak, setiap pemilik sawah memiliki pura,” ujar alumnus IPB Bogor itu.
Adapun sederet penjelasan mengenai subak yang dipaparkan dalam proposal Nomination for Inscription on The UNESCO World Heritage List: Cultural Landscape of Bali Province. Pertama, subak merupakan organisasi petani yang bersifat otonom dan demokratis, yang bersama-sama bertanggung jawab atas penggunaan air irigasi secara adil dan efisien untuk menanam padi. Bukan hanya pengelolaan air secara praktis; subak juga memiliki dimensi keagamaan yang berasal dari kepercayaan bahwa air irigasi adalah anugerah dari Dewi Danau, Dewi Danu. Dari sudut pandang komparatif dijelaskan bahwa salah satu hal yang menonjol dari subak ialah keberhasilan inovasi budaya tersebut dalam menciptakan lanskap yang sangat indah dan telah menjadi dasar keberlanjutan ekologi bagi peradaban Bali selama seribu tahun terakhir. Komponen lanskap yang dikelola oleh subak tidak hanya terbatas pada sawah terasering. Lanskap ini juga mencakup danau, mata air dan sungai yang menyediakan air irigasi; bendungan kecil, terowongan, saluran air, jembatan air, serta sistem pura air berjenjang yang dibangun dan dikelola oleh subak. Siklus ritual di sawah juga mendorong kerja sama di dalam dan antar subak, serta mengingatkan para petani akan konsep utama Tri Hita Karana.
Kendati demikian, di balik gelar warisan budaya yang kini sudah disematkan kepada Jatiluwih serta situs WBD lainnya, ada perjuangan panjang yang dilalui oleh Alit Artha bersama tim penyusun lainnya. Dimulai sejak 2009, 2010, 2011, hingga akhirnya diterima pada tahun 2012. Pemetaan wilayah yang diusulkan masuk dalam WBD menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi kala itu.
Pada hari ini, eksistensi subak juga berhadapan dengan hiruk pikuk pariwisata di Bali. Sumiyati memaparkan bahwa subak mesti menyesuaikan kondisi perkembangan zaman. Sinergi subak dengan bidang pariwisata layak dilakukan. Asal tak memudarkan filosofi subak sejatinya. Pengembangan organisasi subak harus dapat menempatkan subak sebagai subjek bukan sebatas objek yang ditonton dan petani yang semestinya melakon sebagai pemeran utama hanya menonton perubahan di panggungnya sendiri. Untuk menunjang keberlanjutan subak tersebut, Sumiyati juga menyebut perlu dibentuk organisasi yang mengelola secara profesional tetapi tetap terintegrasi dengan pengelolaan subak. Harapnya dapat membantu petani dan anggota subak meningkatkan penghasilannya. Rancangan tersebut juga tertuang dalam management plan yang disusun Alit Artha dan tim. Alit berujar bahwa angka besar kunjungan wisatawan ke Jatiluwih akan mustahil tanpa adanya subak dan petani di sana. Oleh karena itu, kesejahteraan petani menjadi salah satu bagian penting dalam perencanaan tersebut. Bagaimana seyogyanya denyut kehidupan WBD Jatiluwih berdetak di sana, semua itu telah disusun dalam management plan yang terdapat dalam Nomination for Inscription on The UNESCO World Heritage List: Cultural Landscape of Bali Province.
Proposal-Nomination for Inscription on The UNESCO World Heritage List: Cultural Landscape of Bali Province |
Tahun 2012, ketika usulan WBD akhirnya diterima oleh UNESCO, tim pengusul selanjutnya membentuk sebuah organisasi seperti badan rencana. Lembaga tersebut bertugas menyusun sebuah program kerja yang kelak dapat berdampak untuk petani. Beberapa di antaranya ialah asuransi petani, asuransi kecelakaan kerja, beasiswa kepada anak petani khususnya yang ingin menempuh pendidikan di bidang pertanian, dan lain sebagainya. “Kalau petani tidak bisa bayar (asuransi-red) pemerintah wajib membayar, memberikan asuransinya, kemudian juga memberikan insentif kepada petani yang memang bisa mempertahankan budayanya, kemudian wajib menyediakan sarana prasarana irigasi. Itu wajib,” tegas Alit Artha.
WBD dahulu, DTW kemudian
Ketika dunia menyebut Jatiluwih sebagai Warisan Budaya Dunia, seberkas harapan sempat tumbuh. Pengakuan itu seolah menjadi penanda bahwa cara hidup yang dijalani turun-temurun akhirnya mendapat ruang untuk dijaga. Namun alih-alih menguatkan akar, yang berkembang justru cabang lain, pariwisata yang tumbuh lebih cepat dari pelestarian. Apa yang dulu dijaga dalam sunyi, dihormati lewat laku harian, mulai dikemas sebagai tontonan. Dari luar, semuanya masih tampak sama. Tapi sedikit demi sedikit, arah yang ditempuh bergeser dari apa yang pernah dirancang. Yang dibangun bukan lembaga pelestarian, melainkan manajemen wisata. Yang dirawat bukan lagi sistemnya, melainkan tampilan luarnya.
Padahal, sebuah management plan telah diajukan bersamaan dengan pengakuan itu, berisi rencana tentang bagaimana kawasan ini seharusnya dijaga. Namun jalur yang diambil setelah penetapan justru menjauh dari rancangan tersebut. “Yang kita janjikan kepada UNESCO tidak kita lakukan. Yang sudah disusun di dosir, tidak kita jalankan,” ujar I Wayan Alit, yang terlibat langsung dalam penyusunannya. Ia menyebut bahwa setelah status WBD diberikan, yang dibentuk justru DTW (Daya Tarik Wisata) bukan Balai Pengelola Warisan Budaya Dunia seperti yang direncanakan sejak awal.
Salah satu yang paling mendasar dan paling diabaikan adalah RDTR, Rencana Detail Tata Ruang. “Itu hal pertama yang saya ajukan, tahun 2013,” ujarnya. “Tapi tidak pernah direspons. Sampai sekarang pun hanya janji mau ketemu. Begitu-begitu terus. Nonsense. Karena kepentingannya sudah berbeda.” Tanpa RDTR, batas antara kawasan lindung dan ruang bangunan menjadi kabur. Desa tidak memiliki pijakan hukum untuk menolak pembangunan, bahkan saat sawah perlahan dialihfungsikan. “Konsepnya adalah pelestarian. Tapi ini sekarang alih fungsi. Jadi kan tidak tetap,” tegasnya.
Pemerintah pusat pun, menurutnya, kerap tidak memahami realitas di lapangan. Beberapa lahan yang sudah berdiri bangunan permanen, justru masih dimasukkan ke dalam zona Lahan Sawah Dilindungi (LSD). “Itu banyak terjadi,” ujarnya. Padahal, di Jatiluwih seharusnya tidak ada alasan untuk tidak ditetapkan sebagai kawasan LSD. “Yang mana boleh dibangun, yang mana tidak boleh dibangun itu harusnya dari dulu sudah diterjemahkan. Tapi sampai sekarang tidak pernah ada,” tegas Alit.
Dalam situasi seperti itu, desa tidak punya pijakan kuat untuk menolak pembangunan. Sementara di sisi lain, tekanan kebutuhan terus datang. Ketika ruang kian menyempit dan kunjungan wisata terus meningkat, muncul pertanyaan yang tak lagi sederhana: siapa yang sebenarnya diuntungkan? Apakah Jatiluwih dijaga demi wisatawan yang datang dan pergi, atau demi petani yang hidup dan bertahan di dalamnya? Kegelisahan itu tak lahir dari penolakan terhadap pariwisata. Tak ada yang menolak kehadiran pengunjung, kegiatan ekonomi, atau promosi kawasan. Masalahnya bukan pada pariwisatanya, tetapi pada urutan prioritasnya. Pariwisata bisa hadir sebagai teman dari pertanian, tapi tidak bisa menjadi tuan atasnya.
Namun dalam praktiknya, urutan itu justru terbalik. Janji-janji yang dulu diajukan bersama pengakuan Warisan Budaya Dunia tak dijalankan sebagaimana mestinya. “Ya karena kita tidak menjalankan management plan. Apa yang kita janjikan kepada UNESCO tidak kita lakukan. Jadi yang sudah disusun di sini, tidak kita lakukan,” ujar I Wayan Alit. “Ngeles-ngeles terus, baik dari pemerintah provinsi maupun Indonesia, selalu ngeles.” Tanpa arah yang berpijak pada komitmen awal, pelestarian pun berubah menjadi klaim tanpa isi. Padahal, dalam dokumen UNESCO tertulis dengan tegas: protection and management of the property, bahwa warisan harus dijaga secara aktif, bukan sekadar dipertahankan di atas kertas.
Menata Jatiluwih semestinya
Pengelolaan warisan budaya, jika dimaknai secara jujur dan bertanggung jawab, semestinya menjadi jalan untuk menjaga alam dan budaya yang ada sambil tetap membuka ruang bagi pariwisata yang tidak merusak. Sebab, yang ditawarkan kepada dunia bukan sekadar lanskap indah nan terasering, tetapi keseluruhan sistem kehidupan yang melekat padanya, satu ekosistem sosial dan ekologis yang diwariskan dan dijaga lintas generasi. Pengakuan sebagai Warisan Budaya Dunia pun tak datang begitu saja, ia datang membawa tanggung jawab bersama yang sejak awal telah diterjemahkan ke dalam rencana tindak lanjut konkret: management plan. Dokumen ini bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan pijakan bersama untuk menjaga keberlanjutan kawasan secara menyeluruh. Bukan hanya lanskap fisiknya, tetapi juga kehidupan sosial dan nilai budaya yang menyertainya. “Bentang budaya itu. Ya salah satunya bagaimana kita memanajemen subak ini dengan konsep management plan yang sudah kita submit sebagai bagian daripada dosir ini. Itu yang tidak kita lakukan,” ujar I Wayan Alit.
Sejak 2013, Alit dan timnya telah menyiapkan beragam program, mulai dari penguatan kelembagaan, pendidikan, hingga pelatihan pertanian dan pariwisata berkelanjutan. Namun semua itu tidak pernah dijalankan. “Mereka tidak mau menerima apa yang mau kita lakukan,” tambahnya. Jika rencana-rencana tersebut dijalankan sebagaimana mestinya, maka pengelolaan Jatiluwih bisa dilakukan dengan lebih adil dan berpihak pada masyarakat lokal. “Kalaupun itu dijadikan daerah tujuan wisata, wisata tidak ada masalah,” ujar Alit. “Tapi seperti tadi yang saya konsepkan, harus prioritas yang mengerjakan adalah masyarakat di sana. Anak-anak muda di situ sebagai guide-nya.” Ia menyebut model di Angkor Wat, Kamboja, sebagai contoh di mana warisan budaya dikelola oleh masyarakat lokal yang tinggal dan hidup di dalamnya.
Sebagian besar program tersebut tidaklah utopis. Justru sangat membumi, berpijak pada kebutuhan nyata warga. Misalnya, pemberian beasiswa bagi anak-anak petani yang ingin melanjutkan pendidikan di bidang pertanian. Atau pelibatan warga sebagai pemandu lokal yang benar-benar memahami dan mewakili cerita tempatnya sendiri. “Tidak boleh ada guide luar yang bercerita tentang hal itu,” ujar Alit. “Harus di-takeover guide lokal di situ.” Konsep akomodasi pun dirancang bukan dengan hotel atau villa besar, tetapi melalui sistem homestay. Rumah-rumah petani disiapkan menjadi tempat menginap bagi wisatawan, dengan standar yang disusun bersama. Dengan begitu, perputaran ekonomi tetap terjadi, tapi tidak dengan mengorbankan tatanan sosial yang telah lama menopang kehidupan di sana.
Situasi semacam ini tak bisa terus dibiarkan. Jika ingin warisan ini tetap hidup dan bermakna, maka arah pengelolaan harus dikembalikan ke jalurnya. Menata ulang Jatiluwih bukan berarti memulai dari nol. Yang dibutuhkan bukan hanya penataan ruang, tapi perbaikan arah dan cara pandang. Pelestarian tak akan bermakna tanpa keterlibatan nyata petani dan masyarakat adat yang selama ini menjadi penjaga lanskap hidup. Untuk itu, struktur kelembagaan harus dikaji ulang, agar keputusan-keputusan tidak dikuasai logika pariwisata semata, dan petani benar-benar punya suara. Karena itu, management plan semestinya tak tinggal sebagai dokumen usang, tapi seharusnya menjadi pijakan hari ini, bukan hanya untuk melangkah, tapi untuk kembali mengakar.
Penulis: Friskila, Gung Putri, Gita
Penyunting: Putri Wara
Sumber foto: Dokumen Pribadi
kampungbet kampungbet kampungbet kampungbet kampungbet kampungbet kampungbet kampungbet kampungbet kampungbet