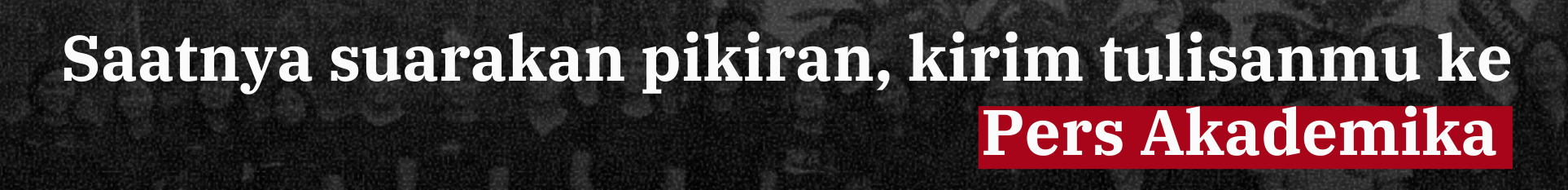Merekah Jernih Menjadi Jurnalis Humanis

“Aku baru resign Januari dari NGO kedua,” ujar I Gusti Ayu Diah Pramesti. Kalimat itu ia lontarkan sebagai pembuka obrolan sore, Rabu (29/03). Ketika banyak anak muda berburu bangku kerja di ruang tertutup yang sejuk, Gusti Diah malah merindukan berpeluh menjadi pendengar setia masyarakat akar rumput.
Ada dua hal yang membuat Gusti Diah (24) tak betah. Pertama, target menulis yang ditentukan oleh lembaga itu melebihi batas wajar. Kedua dan yang paling menyesakkan baginya, nyaris tidak ada kesempatan untuk bertemu masyarakat yang termarjinalkan. “Biasanya aku ke lapangan ketemu petani, wawancara. Nah, di sini tuh nggak dapat. Aku terus di kamar, nggak ada interaksi,” ungkap perempuan asal Klungkung itu di salah satu sudut Ruang Hijau Terbuka, Universitas Udayana.
Di sela obrolan, Gusti Diah mengaku ini kali pertamanya kembali berkunjung ke Udayana setelah lulus dari Ilmu Komunikasi. Pun termasuk meninggalkan meja dan karpet lusuh di pers mahasiswa. Baginya, menjadi bagian pers mahasiswa merupakan awal perjalanan dalam membuka hati dan telinga. Bahwa ada banyak cerita mereka yang jungkir balik berjuang, yang setiap hari batinnya berdebat perihal melawan atau berserah. Di tengah kesumpekan itu yang diinginkan hanyalah dukungan.
Warga Tumpang Pitu, Banyuwangi, yang pertama kali mengajarkannya. “Jadi gunung yang melindungi mereka sekarang udah dikeruk jadi tambang emas, ancamannya kampung bisa kena tsunami. Orang-orang ini kadang nggak perlu uang, secara materialis gitu nggak, perlunya dukungan. Semangat untuk memperjuangkan hak mereka,” kisahnya.
Gusti Diah menggugat tambang Tumpang Pitu ketika masih menjadi mahasiswa. Lima tahun berlalu, tulisannya masih setia berpihak pada masyarakat akar rumput. Sebagai salah satu kontributor dari Balebengong, media jurnalisme warga di Bali, nama Gusti Diah santer terdengar di bilik isu lingkungan. “Sekarang kan lagi era motor listrik, nggak bikin polusi, tapi dapatnya dari nikel. Ada aktivitas besar yang tetap berjalan di luar, tapi kita sebagai individu itu dibikin seolah salah dan dipaksa yang hijau-hijau. Itu (dampaknya) nggak signifikan,” paparnya menyoal ketimpangan aksi ramah lingkungan.
Bagi Gusti Diah, di sanalah peran jurnalis dibutuhkan. Aksi personal dalam lingkaran kecil memang diperlukan. Namun, gaung dukungan pemberitaan yang tepat akan mengusik aktor besar perusak lingkungan yang sesungguhnya. “Jadi voice of voiceless. Menceritakan lagi kondisi masyarakat yang termarjinalkan. Orang-orang jadi tahu gimana kondisi aslinya dan ngelahirin dukungan juga, mereka jadi bisa menyatakan sikap,” jawab Gusti Diah soal peran penting seorang jurnalis.
Tapi nyatanya tak banyak jurnalis yang konsisten mengenyam peranan itu. Akan selalu ada pihak-pihak yang merayu. Pun mata pena jurnalis berganti, yang tadinya tajam kini tumpul karena saban hari menyuarakan yang itu-itu. “Aku lihat di media arus utama, belum terlalu ada keberpihakan pada mereka yang termarjinalkan. Mereka (jurnalis) posisinya terhimpit. Kalau beritanya ini lawan pemerintah, nggak berani,” tuturnya pelan. Mendung yang menggelayut di langit kala itu seolah ikut mengamini cerita Gusti Diah.
Jurnalisme Indonesia Dulu dan Kini
Sulit mencari jurnalis yang independen, pun untuk menjadi salah satunya. Pada masa orde baru banyak terjadi pembredelan media massa yang berseberangan dengan pemerintah. Dikutip dari Kompas.com, setidaknya sebanyak 70 surat kabar yang dibredel. Sebut saja Harian Kompas, Tempo, Monitor, DeTIK, dan Editor. Pencabutan izin terbit saat itu ada kalanya hanya berlangsung sementara. Namun sebagai jaminannya, para petinggi meminta media untuk menulis surat perjanjian. Kurang lebih
isinya menyepakati untuk berhenti mengkritik segala urusan pemerintah. Sehingga tak heran bila media independen hampir mustahil ditemui kala orde baru.
Sedari dahulu media massa menjelma ruang yang begitu sensual, menggugah setiap mata yang meliriknya. Seperti tulisan Noam Chomsky dalam bukunya “Politik Kuasa Media”. Menarasikan mengerikannya propaganda media yang menyihir rakyat Amerika di masa pemerintahan Woodrow Wilson yang semula anti-perang menjadi histeris dan haus akan perang. Narasi tersebut seolah mengamini kondisi saat ini, media massa masih menjadi alat propaganda bagi yang berkuasa. Dunia jurnalisme seolah menjadi kendaraan bagi mereka yang ingin mencapai tujuannya. Konflik kepentingan turut menggerogoti independensi media massa. Ditekan dari berbagai sisi, untuk menjaga hayatnya jurnalis diperlukan donor untuk tetap menyelenggarakan kegiatan dan menjaga api advokasi tetap menyala.
Akhirnya, media massa ditempatkan pada kebimbangan, antara kepentingan komersial atau advokasi. Di era disrupsi, media massa mesti tetap menyadari marwahnya sebagai ruang advokasi kepentingan masyarakat. Mengutip dari laman resmi Dewan Pers Indonesia (DPI), sepanjang tahun 2015 DPI menerima pengaduan, pemberitahuan dan permohonan perlindungan dari masyarakat menyoal praktik jurnalisme yang berbenturan dengan kode etik. Fakta ini hanyalah perwakilan sepenggal kisah keruhnya dunia jurnalisme dalam pusaran bisnis informasi. Menengok keruhnya industri media massa, Gusti Diah berseloroh “Konsekuensinya kalau mau jadi jurnalis yang idealis harus siap miskin,” ujarnya sembari tertawa kecil.
Kejernihan pemaknaan informasi menjadi sesuatu yang begitu mahal, sulit terjangkau. Wahyu Nugroho, Dosen Sosiologi Universitas Udayana mengungkap dalam tulisannya, lambat-laun masyarakat yang disebut sebagai “masyarakat tontonan” akan menuju pada sikon “masyarakat seremonial”; masyarakat yang ajeg merayakan sesuatu namun tak paham ihwalnya. Ini nantinya hanya menemui kekosongan. Karena segala sesuatu telah melampaui definisinya sendiri.
Di sinilah peranan jurnalis muda dituntut untuk mengambil posisi dalam menciptakan keberimbangan informasi. Ini disampaikan oleh Calvin Damas Emil, Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Udayana “Kita dikasih perspektif lain terhadap sebuah peristiwa, nggak cuma dari satu aja kita dapat dan kita bisa menentukan sikapnya akan seperti apa, mendukung, menolak dan lain-lain. Dibandingkan sebagai alternatif, justru menjadi pelengkap arus informasi,” jelasnya.
Jurnalis Muda
Secercah harap menyibak kekhawatiran akan gamangnya arus informasi yang deras mengalir. Jurnalis muda, menyuburkan harap. Asa menjadi bekal jurnalis muda tuk menggapai mimpinya. Alih-alih dipandang sebagai juru selamat, jurnalis muda seringkali dipandang sebelah mata. Belicia Rafaela (17), siswa SMAK Santo Yoseph yang tergabung dalam Saint Journal, membagikan pengalamannya, “Dari pandangan kalangan teman-teman sih. Setiap kali saya bilang ada kegiatan yang berhubungan dengan jurnalistik, mereka pasti meremehkan saya dan mengatakan tidak bermanfaat.”
Kala suara jurnalis muda terdengar tak penting di lingkarannya sendiri, komunitas Global Youth Conference (GYC) melakukan sebaliknya. Keyakinan GYC terhadap peran anak muda begitu besar. Itu pula yang mendorong Devi Ariasih (20) bergabung bersama komunitas GYC semenjak SMA. “GYC menurutku suatu tempat dimana anak muda, tuh diajak kumpul, dimana tujuannya memang anak muda itu sebenarnya punya power.”

Berkat GYC, kemampuan Devi kian berkembang. Jika dulu torehan pemikirannya hanya dinikmati seorang diri, kini khalayak umum dapat menikmati karyanya melalui situs web GYC. “Mulai aku menulis yang sampai dipublikasi di website, walaupun websitenya itu belum besar. Tapi mulainya dari sini,” syukur gadis kelahiran Denpasar itu. Kala bertumbuh bersama GYC, atensi Devi dalam menulis teralih menuju isu SDGs (Sustainable Development Goals).
Ironi dibalik perhelatan G20 di Bali pun tak luput dari penglihatan Devi. Menjelang G20, stakeholders sibuk melakukan persiapan. Pemasangan paving rupanya termasuk dalam daftar persiapan G20. Perbaikan infrastruktur memang penting, kendati bagi Devi itu bukanlah yang utama. Lokasi sekitar perhelatan masih terlilit perihal pengelolaan sampah. “Di dekat sana sampahnya masih banyak kenapa nggak ngurusin itu aja?” tanyanya keheranan. Enggan berdiam diri, Devi lantas menyuarakan keprihatinannya melalui tulisan. Gairahnya dalam menulis kemudian menimbulkan mimpi untuk membentuk kelompok jurnalis SDGs. Dirinya berharap masyarakat tak lagi mengesampingkan isu SDGs jika kelompok jurnalis SDGs terealisasi.
Menyambut Angin Segar
Industri jurnalistik tak melulu soal tulisan dan video liputan belaka. Nyatanya kini terdapat jurnalisme komik yang memberi angin segar bagi industri jurnalistik Indonesia. Kendati demikian, gema jurnalisme komik belum terdengar hingga seluruh sudut. Posisi komik di koran-koran masih sebatas konten hiburan fiksi. Mengubah stereotip masyarakat memang tak semudah membalikkan telapak tangan. Namun, seorang pemuda Asal Bandung, Hasbi Ilman (28) memberi gebrakan baru di dunia jurnalistik. Jauh sebelum desas-desus jurnalisme komik terdengar, Hasbi yang kala itu masih menempuh pendidikan di Universitas Islam Bandung, merintis alternatif komik non fiksi bernama Jurnalis Komik.
Perlahan Jurnalis Komik mematahkan stereotip komik sebagai konten pojokan. Berangkat dari rasa bosan akan komik-komik fiksi, Hasbi merangkul beberapa teman pers mahasiswanya untuk merintis Jurnalis Komik. “Jadi ya kalau misalnya memang nggak ada di Indonesia, kenapa nggak saya aja coba bikin?” kenang Hasbi. Media yang dianggap sebagai kecelakaan kampus ini, kini menjelma jadi media yang doyan mengisahkan cerita kecil yang kadang tersembunyi dari publik. Hasbi mengenalkan Jurnalis Komik dari mulut ke mulut. Acap kali Hasbi menyambangi pameran-pameran untuk membagikan zine. “Kayak emang nggak tau malu sih, cuma ya namanya juga usaha,” ungkapnya terkekeh.
Hasbi mengaku proses pembuatan setiap edisinya memakan waktu selama seminggu. Pun habis dibaca tak sampai lima menit. Namun, goresan itu tak sembarang, melainkan menyimpan unsur human interest. “Kita kenapa milih komiknya ala-ala kartun gitu ya ada alasannya, karena pembaca itu semakin dekat dengan isunya. Semakin sederhana gambar itu semakin orang-orang relate. Sehingga sasaran pembaca kita itu justru orang-orang yang belum baca komik,” aku Hasbi. Hingga kini Jurnalis Komik memiliki 25 ribu lebih pengikut pada akun Instagramnya. Dirinya berharap dapat berkeliling Indonesia untuk menceritakan isu di tiap daerah melalui Jurnalis Komik.
Arus peradaban yang begitu cepat memang tak terhindarkan, namun tak semestinya jurnalisme humanis jadi terkikis. Tulisan bertajuk “Objek, Kecabulan, dan Godaan: Telaah Ekstasi Komunikasi” oleh Wahyu Budi Nugroho, mengungkapkan bila dunia ini bergerak demikian cepatnya. Maka hendaklah kita melawan balik dengan melakukan perlambatan; penghayatan atas dunia. Seperti halnya Gusti Diah, Devi Ariasih, dan Jurnalis Komik yang perlahan menyelami dunia. Menyisakan waktu untuk tumbuh bersama masyarakat akar rumput. Semoganya senantiasa merekah jernih, menjadi jurnalis humanis. (kar/dyt/kw)